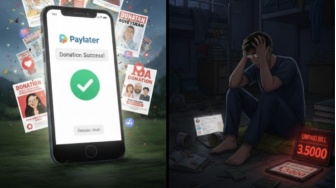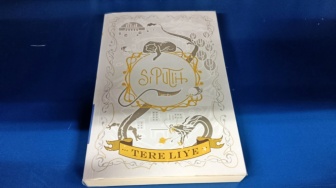Malam itu, bapak tidak pulang. Padahal, ibu sudah menyiapkan kopi panas di meja makan, rokok linting kesukaan bapak juga masih utuh, menunggu disulut. Ibu bilang, bapak sedang di jalan, mungkin terjebak macet, seperti biasa.
Tapi malam semakin larut, dan bapak tak kunjung tiba. Kegelisahan mulai mengendap di wajah ibu; langkahnya mondar-mandir di ruang tamu, menyibakkan tirai setiap lima menit sekali, menatap jalanan yang kosong tanpa lalu-lalang.
"Bapak pasti pulang," gumam ibu, seolah lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada meyakinkanku.
Tak lama kemudian, ketukan keras terdengar di pintu. Tidak biasa, pikirku. Bapak selalu membawa kunci cadangan, tak pernah ia mengetuk.
Ketika pintu dibuka, dua orang pria berdiri di sana. Seragam mereka rapi, wajah mereka datar. Tanpa basa-basi, mereka menyodorkan selembar kertas kepada ibu. Aku melihat ibu menggigil saat membaca tulisan itu.
“PELANGGARAN!!!,” kata yang tertulis di sana, tertera dengan huruf besar dan tebal di atas surat.
"Bapak ditahan karena bicara terlalu banyak," ucap salah satu pria dengan suara dingin yang mengiris malam.
Aku bingung, tak mengerti.
Sejak kapan bicara terlalu banyak bisa membuat seseorang ditahan? Ibu tidak menjawab, hanya menangis sambil menggenggam surat itu erat-erat.
Pria itu mengangguk singkat, lalu berbalik, meninggalkan rumah kami dalam sunyi yang mendadak terasa lebih mencekam. Ibu masih berdiri di ambang pintu, sorot matanya terpaku pada surat itu, seolah memeluk sisa-sisa harapan yang lebur.
***
Esok harinya, burung-burung gereja seperti mewartakan berita hangat. Kabar tentang bapak sudah tersebar di seantero penjuru desa.
Orang-orang mulai berbisik, mata mereka menatap curiga. Ada yang berkata bapak ikut-ikutan bicara tentang keadilan, tentang kemerdekaan bersuara. Ada yang bilang bapak terlalu keras kepala, tak tahu diri. Ada juga yang diam saja, tapi mata mereka berkata lebih dari kata-kata.
Rumah kami mendadak sepi. Tak ada lagi tetangga yang mampir untuk meminjam gula atau sekadar mengobrol obrolan yang obral. Mereka semua menjauh, takut tertular “penyakit” yang bapak bawa.
"Penyakit bicara," begitu mereka menyebutnya, sambil menutup pintu rapat-rapat jika kami lewat.
Setiap malam, aku mendengar sajak-sajak elegi bersenandung dari tangis ibu yang mengalun di kamarnya. Aku tak berani mendekat, apalagi bertanya.
Aku tahu, ibu tak ingin terlihat lunglai di hadapanku. Dia ingin tetap menjadi sosok yang kuat, meskipun di dalam hatinya sebongkah lubang besar tak mungkin tertutupi. Purnama demi purnama berlalu sejak bapak dibawa pergi, dan kehidupan di desa kami pun berubah, layaknya sebuah lakon yang silih berganti babak.
***
Setiap hari, sekelompok pria berseragam berkeliling desa, tapi sesekali mereka tak lagi mengenakan seragam yang sama. Mereka menyamar dalam berbagai rupa; penjual bakso, tukang ojek, pedagang keliling, dan banyak lagi. Dengan penampilan sederhana, mereka mengetuk pintu-pintu rumah, mengundang warga untuk "berbicara."
Awalnya, banyak yang menerima ajakan tersebut dengan ramah-tamah, menganggap sebagai percakapan lumrah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang tak pernah kembali, meninggalkan kekosongan yang mencekik di desa kami.
"MUSIM BISU TELAH TIBA," ujar ibu pada suatu malam, suaranya serak saat kami duduk di meja makan yang terasa semakin lapang.
Aku tak sepenuhnya mengerti apa yang ibu maksud, tapi aku tahu itu ada hubungannya dengan para pria berseragam itu. Mereka adalah utusan dewa sunyi yang pembawa bisu, datang untuk membungkam setiap suara yang dianggap berbahaya.
Desa kami menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di pekarangan, tak ada lagi ibu-ibu yang merumpi di pasar. Bahkan burung-burung pun tampaknya enggan berkicau, takut suaranya akan dianggap terlalu nyaring.
Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, aku melihat seorang pria tua duduk di bangku depan rumahnya. Dia menatap langit, matanya kosong, bibirnya komat-komit seolah sedang merebus kata, tapi tak ada suara yang keluar.
Pria itu adalah Pak Sardiyo, tetangga kami yang dulu sering bercerita tentang perjuangan dan kemerdekaan. Dia adalah orang yang paling tahu tentang selak-beluk di desa kami. Tapi kini, ia tak lagi pandai beretorika; bisu dan tanpa ekspresi. Ingin sekali aku bertanya apa yang sebenarnya tengah terjadi, tapi ibu melarangku.
“Jangan terlalu banyak bertanya, Nak. Banyak bertanya itu berbahaya,” kata ibu.
Malam itu, ibu menjadi semakin pendiam. Dia tak lagi berbicara tentang bapak, tak lagi menangis di malam hari.
Dia hanya menjalani harinya dengan tenang, seolah-olah sudah menerima predestinasi yang telah menjadi garis tangannya. Namun, aku tahu, di dalam hatinya, ibu masih merindukan bapak. Dan aku tahu, bapak pun merindukan kami.
Musim bisu terus berlangsung, konon tak ada yang tahu kapan musim ini akan berakhir. Orang-orang di desa kami hanya bisa berharap, suatu hari suara mereka akan kembali.
Tapi sampai saat itu tiba, mereka akan tetap bisu, hidup dalam keheningan yang membeku. Seperti yang bapak selalu katakan, "Kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.”
Di penghujung hari, aku masih menunggu di balik jendela, berharap sosok bapak muncul di ujung jalan. Tapi yang kulihat hanya bayang-bayang pria berseragam, berjalan perlahan, menyebarkan keheningan dan hawa cekam ke setiap sudut desa. Dan malam itu, sebelum tidur, aku mendengar ibu berbisik pelan.
"Bapak tidak akan pulang, Nak. Dia sudah menjadi hantu di musim bisu ini."
Kata-kata itu bergema di kepalaku, mengisi malam dengan rasa takut yang semakin kalut. Aku tak ingin percaya, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa ibu mungkin benar.
“Bapak, jika kau mendengar, kami masih menunggumu. Meski hanya dalam hening— sampai musim bisu berakhir.”