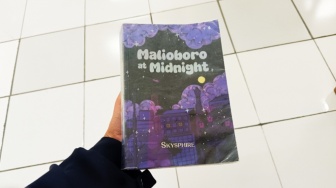Cerita Fiksi
Mutiara Tidak Pernah Mengancam Laut

“Dan ingat ya, Mut,” kata ibunya sambil mengaduk teh sore, “pendidikan, karier, rezeki. Apa pun kesempatan yang datang padamu itu bukan ancaman. Itu berkah.”
Mutiara tersenyum. Senyumnya tipis, seperti garis cahaya yang muncul di antara awan mendung. Kalimat itu tidak baru, tapi entah kenapa selalu terasa seperti rumah. Memang benar, terkadang kita kerap lupa akan fakta terpenting. Bahwa hal-hal baik adalah semua berkah. Sesuatu yang patut disyukuri. Terlepas banyak label dan omongan miring. Hal baik, tetap hal yang seharusnya membuat kita bersyukur.
Di teras, angin berembus pelan. Daun mangga berbisik, seolah ikut nimbrung percakapan.
“Bu,” Mutiara menyandarkan dagu di telapak tangan,
“kenapa sih orang-orang gampang banget curiga sama perempuan sekolah tinggi?”
Ibunya melirik, mengangkat alis. “Curiga gimana?”
“Kayak… dianggap bakal rusak. Rumah tangga rusak, laki-laki minder, dapur kosong, cinta punah,” jawab Mutiara sambil tertawa kecil. “Padahal kan nggak ada hubungannya.”
Ibunya terkekeh. “Ah, itu karena banyak yang masih mikir hidup kayak permainan jungkat-jungkit.”
“Naik satu, yang lain harus turun?” Mutiara menimpali.
“Nah,” kata ibunya sambil menunjuknya. “Padahal kalau mau, bisa duduk bareng di bangku panjang.”
Mutiara tertawa lebih lepas. Ia teringat suara-suara yang sering mampir ke hidupnya, tanpa diundang.
Perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi.
Nanti susah diatur.
Cowok jadi minder.
Ujung-ujungnya juga di dapur.
Kalimat-kalimat itu sering datang sambil senyum. Kadang sambil makan. Kadang sambil bercanda. Tapi tetap saja, menyisakan rasa pahit di ujung lidah.
“Bu,” Mutiara berkata pelan, “kenapa pendidikan perempuan selalu dikaitkan sama kesepian?”
Ibunya berhenti mengaduk. Menatap Mutiara lama.
“Karena banyak orang takut sendirian,” katanya. “Jadi mereka pikir semua orang juga harus takut.”
“Padahal,” Mutiara menghela napas, “sendiri dan kesepian itu beda.”
“Betul,” jawab ibunya. “Dan perempuan terdidik justru biasanya tahu cara menemani dirinya sendiri.”
Mutiara tersenyum. Angin sore mengibaskan ujung rambutnya. Ia ingat bagaimana dulu ia sering diminta mengecil, bukan agar muat di ruang sempit, tapi agar orang lain tidak merasa terganggu.
“Bu,” katanya lagi, “aku juga sering dengar yang bilang perempuan berkarier itu nggak butuh laki-laki.”
Ibunya mendengus kecil. “Itu lucu.”
“Lucu?”
“Iya. Seolah-olah mandiri artinya anti-cinta,” katanya.
“Padahal mandiri cuma berarti tidak menggantungkan hidup pada rasa takut.”
Mutiara terkikik. “Berarti kalau aku punya karier, aku tetap boleh jatuh cinta?”
“Boleh,” jawab ibunya cepat. “Menjadi perempuan yang berdikari itu bukan berarti kamu kehilangan gak untuk dicintai dan mencintai. Berdaya tidak sama dengan kehilangan perasaan. Boleh cinta, boleh butuh, tapi jangan hilang.”
“Jangan hilang?”
“Jangan hilang sebagai diri sendiri.”
Mutiara terdiam. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dalam.
Ia teringat obrolan dengan teman-temannya. Tentang perempuan yang dianggap terlalu pintar. Terlalu vokal. Terlalu tahu apa yang ia mau. Seolah itu adalah sebuah kesesatan yang harus dibasmi. Ia jadi terpikirkan akan berapa beratnya perjuangan RA Kartini untuk pendidikan wanita. Di era ini saja, anggapan buruk masih begitu kuat melekat. Apa lagi di era itu.
“Sebenarnya apa sih yang ditakuti orang-orang ke perempuan cerdas?” gumam Mutiara.
Ibunya mengangkat bahu. “Mungkin perempuan cerdas dianggap cermin.”
“Cermin?”
“Iya. Memantulkan ketakutan orang lain. Terkadang orang lain takut melihat dirinya sendiri. Mungkin bukan takut, tapi...”
Kalimat itu menggantung tanpa kepastian.
"Seperti perasaan tidak aman?" Tanya Mutiara
"Mungkin... perasaan seperti dilucuti?"
"Dilucuti?"
"Telanjang. Tanpa pakaian yang menutup. Seolah semua hal yang disembunyikan segenap jiwa harus terlihat. Mungkin, perasaan lemah yang mereka sadari itulah yang paling ditakuti."
"Tapi bukannya mereka juga bisa belajar dan menaikkan potensi diri juga ya? Kenapa justru takut?" Tanya Mutiara penasaran.
"Karena belajar itu sulit. Jauh lebih mudah menghibur diri dengan menyuarakan bahwa pendidikan bukan hal yang penting dan tidak perlu dilakukan."
Mutiara termenung sejenak. “Berarti masalahnya bukan di perempuannya.”
“Memang tidak.” jawab ibunya sambil tersenyum penuh makna.
Langit mulai berubah warna. Jingga bertemu ungu. Sore menutup hari dengan cara paling lembut.
“Bu,” Mutiara berkata lirih, “aku capek harus terus menjelaskan kalau pendidikan itu bukan perlawanan.”
Ibunya menepuk punggung tangannya. “Kamu nggak wajib menjelaskan ke semua orang.”
“Terus?”
“Jalani saja,” katanya. “Kadang hidup yang dijalani dengan utuh lebih keras suaranya daripada seribu debat.”
Mutiara mengangguk. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Bukan amarah. Bukan pembuktian. Tapi penerimaan.
Ia sadar, perempuan terdidik bukan berarti ingin mengalahkan siapa pun. Ia hanya ingin berdiri sejajar, mengobrol tanpa menunduk, mencinta tanpa mengecil.
“Bu,” Mutiara tersenyum lebar, “kalau aku sukses nanti, aku nggak bikin siapa-siapa kalah kan?”
Ibunya tertawa kecil. “Laut nggak pernah bikin mutiara lain tenggelam.”
Mutiara menatap ibunya. Kalimat itu terasa seperti puisi yang tidak ditulis, tapi dihidupi.
Ia bangkit dari kursi. Sore hampir habis. Tapi keyakinannya baru mulai tumbuh.
Karena akhirnya Mutiara paham.
Pendidikan bukan ancaman.
Karier bukan pembangkangan.
Rezeki bukan perebutan.
Dan perempuan yang tumbuh bukan sedang melawan dunia.
Ia hanya sedang menjadi dirinya sendiri, tanpa minta maaf.