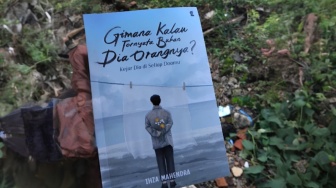“Ini melelahkan!” keluhku.
Bau uap susu dan ampas kopi yang lembap menyatu dengan pori-pori kulitku.
Sudah pukul sebelas malam. Tapi aku masih berdiri di balik mesin espresso, menatap tumpukan portafilter kotor yang menanti untuk disikat.
Tanganku sedikit gemetar saat memegang kain lap. Sendi-sendiku mulai memberi sinyal protes. Sebab aku sudah berdiri selama sembilan jam tanpa henti di atas lantai ubin yang dingin ini.
"Ris, meja nomor empat minta bill," ucap aka, teman shift-ku yang wajahnya sudah sekusut kertas bekas.
"Oke," jawabku singkat.
Aku berjalan gontai menuju meja pelanggan sambil memasang senyum profesional. Yang bahkan aku sendiri sudah mulai bosan memperlihatkannya.
Setelah pelanggan terakhir keluar, aku mengunci pintu kaca depan.
Aku bersandar di sana sejenak, menatap bayanganku yang terpantul di kaca, yang mulai buram oleh embun hujan.
Meski samar, aku bisa melihat kantung mataku mulai menghitam seperti mata panda.
“Ah duniaku selalu sama. Semua membossnkan!” celetukku.
"Ka, kamu ngerasa enggak sih, kita udah kayak zombi?" tanyaku sambil melempar celemek ke meja bar.
Raka yang sedang menyapu menoleh dengan dahi berkerut.
"Maksudmu?" tanyanya datar.
"Ya, liat deh kita ini. Setiap hari bikin ratusan kopi buat orang yang bahkan nggak liat muka kita,” jelasku.
“Pulang subuh, tidur sebentar, terus balik lagi ke sini. Apalagi hampir tiap hari ada aja yang komplain soal susu yang kurang creamy. Serius, capek, Bro,” rengekku setengah bercanda.
Seketika itu, Raka berhenti menyapu, dia menarik kursi tinggi di depan bar dan duduk di hadapanku.
"Coba liat dulu tanganmu, Ris,” suruhnya.
Aku pun langsung mengangkat tanganku yang memerah gara-gara terkena uap panas.
"Kenapa?" tanyaku heran.
"Tangan itu tadi bikin latte art bentuk hati buat cewek di meja pojok, kan? Kamu liat nggak muka doi pas kopinya dateng?" tanya Raka datar.
"Nggak merhatiin. Aku cuma pengen dia cepat minum dan cepat pulang," jawabku jujur.
Raka terkekeh, suara tawanya garing tapi terasa cukup hangat.
"Dia lagi nangis sebelum kopi pesanannya dateng, Ris. Tapi pas dia lihat gambar hati di kopimu, dia berhenti nangis. Dia ambil foto kopinya, terus senyum dikit. Mungkin buat dia, kopimu itu satu-satunya hal manis di harinya yang pahit."
Aku terdiam. Kalimat Raka benar-benar menohok. Tadi aku memang sempat melihat perempuan itu, tapi tidak benar-benar mengamatinya.
"Lelah itu manusiawi, Ris. Tapi jangan sampe rasa lelah malah bikin lupa kalok kamu itu lagi ngelakuin sesuatu yang berarti," lanjut Raka sambil berdiri lagi, lalu lanjut menyapu .
"Tapi bayarannya nggak sebanding sama capeknya, Ka," sanggahku lagi, mencoba mempertahankan keyakinanku yang berasal dari rasa lelah ini.
"Memang. Kalok cuma diliat dari hitungan angka di tabungan, kita kalah banget. Tapi coba pikir deh, kenapa kamu bertahan sampai setahun di sini?"
Raka balik bertanya tanpa melihatku.
Aku menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Penciumanku mulai merasakan aroma kopi yang tadi memuakkan kini menjadi sedikit lebih bersahabat.
"Mungkin karena aku belum punya pilihan lain?"
Raka berhenti menyapu tepat di depan kakiku.
"Bukan. Kamu bertahan karena kamu tahu, kalau berhenti sekarang, kamu nggak akan pernah sampai ke mimpi buat buka kedai kopimu sendiri di desa.”
Aku terdiam. Benar yang Raka katakan. Dulu, aku keukeh kerja di sini memang untuk mendapat lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Ya, selain untuk ngumpulin modal, aku juga pengin buka kedau sendiri di desa pas nanti pulang kampung.
“Kamu di sini bukan cuma buat kerja, kamu di sini buat belajar cara bertahan saat dunia lagi pahit-pahitnya,” sambung Raka.
Meski dia benar, tapi aku tiba-tiba saja tertawa mendengar nasehatnya.
"Kamu belajar bijak dari mana sih, Ka? Keseringan baca quotes di bungkus gula?" ledekku, mencoba mencairkan suasana.
"Aku belajar dari tiap gelas yang pecah, Ris. Pecah itu hancur, tapi pecahannya bisa bikin luka kalau nggak buru-buru dibersihkan. Sama kayak rasa lelahmu. Kalau nggak dikelola, dia bakal ngehancurin dan menyakiti semangatmu sendiri."
Aku tak menjawabnya. Tapi memilih melanjutkan pekerjaan. Mengambil spons dan mulai menyikat bak cuci piring.
Bunyi air mengalir terasa seperti backsound yang menenangkan. Aku mulai membayangkan Ibu di rumah, yang setiap bulan aku kirimi uang hasil keringat dari balik mesin espresso ini.
Aku membayangkan senyumnya saat menerima pesan singkat dariku yang mengabarkan kalau aku sehat-sehat saja. Juga membayangkan bagaimana Ibu merasa lega bisa menyimpan uang gajiku.
“Semua uang yang kamu kirim, Ibu tabung di rekening. Nanti kalo pulang, bisa kamu pake untuk mulai usaha.”
Begitulah yang selalu Ibu katakan setiap kali aku mengirim bukti transfer. Meski aku memintanya menggunakannya uang itu untuk kebutuhan rumah, tapi Ibu selalu menolak.
Alasannya cuma satu, supaya aku bisa segera mewujudkan impianku.
"Ka, sori ya aku tadi agak baper," kataku sambil terus menggosok.
"Santai, Bro! Besok pagi juga kamu bakal ngeluh lagi pas lihat antrean ojol di depan pintu," jawab Raka sambil tertawa.
"Iya sih. Tapi setidaknya sekarang aku tau, kalok aku capek, itu artinya aku lagi berjuang. Bukan pasrah sama takdir,” ucapku, seakan tertularan jiwa sok bijaknya Raka.
Aku menyelesaikan cucian terakhir. Tanganku masih pegal, punggungku masih kaku, tapi ada sesuatu yang hangat menetap di dadaku. Aku menyadari satu hal, rasa lelah ini adalah harga yang harus aku bayar untuk sebuah mimpi.
Aku bekerja, aku berguna, dan aku sedang membangun masa depanku sendiri. Meski lelah. Walaupun tak tahu kapan mimpi itu akan terwujud. Setidaknya, aku masih mengusahakan agar semua itu terjadi.
"Ayo pulang, Ris. Besok kita tempur lagi di jam sibuk," ajak Raka sambil mematikan lampu utama.
"Ayo. Tapi besok gantian ya, kamu yang bagian bersihin grease trap," balasku sambil nyengir.
"Enak aja! Tetap jadwalmu!"
Kami keluar dari kafe, mengunci pintu, dan membiarkan penat kami tertinggal di dalam ruangan yang gelap itu.
Di bawah lampu jalan yang temaram, aku melangkah menuju motor dengan perasaan yang lebih lega. Besok akan tetap melelahkan, aku tahu itu.
Tapi besok, aku akan membuat kopi dengan kesadaran bahwa di setiap tetesnya, ada semangat yang tidak boleh padam.
Karena, di setiap kesuksesan pasti ada perjuangan yang terasa lelah atau menyakitkan. Tak apa, semua pasti akan baik-baik saja selagi aku bisa menerimanya!