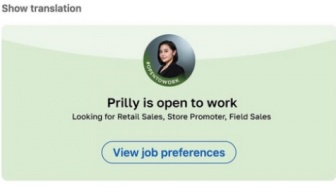Isu Uighur—dalam hal ini yang berkaitan dengan pelanggaran HAM—menjadi topik yang tetap memanas terlebih di dunia internasional. Dugaan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM Tiongkok sebagai negara yang menaungi Muslim Uighur terbisik kuat di tahun 2017 ketika pemerintah rezim komunis membuat kamp konsentrasi untuk menderadikalisasi Muslim Uighur di daerah Xinjiang. Belum lagi pada saat itu, pemerintah Tiongkok melebarkan pengawasannya terhadap Muslim Uighur dengan membuat banyak pos pemeriksaan, CCTV, dan keamanan—sampai pada kebijakan menahan 1 juta warga Uighur di kamp konsentrasi.
Tentunya pengadaan kamp konsentrasi tersebut disorot oleh berbagai elemen internasional layaknya Komite PBB, Human Right Watch, sampai Amerika Serikat pada 2018 sampai detik ini. Banyak yang menganggap tindakan Tiongkok dalam memberi 'edukasi' terhadap Muslim Uighur adalah wujud dari kekerasan, asimilasi paksa, sampai genosida. sehingga pemerintah rezim komunis Tiongkok dituntut untuk bertanggung jawab atas semua itu.
Dalam hal ini, polemik isu ‘penindasan’ pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur tentunya memiliki kronologi yang sudah berlangsung panjang, penyebabnya pun tentu tidak lepas dari bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok itu sendiri dalam hal yang berkaitan dengan identitas. Begitu juga dengan jawaban atas pertanyaan atas tidak maksimalnya peranan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim di dunia dalam menangani isu Uighur di forum internasional. Semua itu butuh ditelisik lebih dalam lagi permasalahannya.
Penyebab Tindak Diskriminatif Rezim Tiongkok terhadap Muslim Uighur
Fenomena pelanggaran HAM di Xinjiang, sebagaimana pembatasan kebebasan beragama—bahkan dilaporkan Muslim Uighur dipaksa murtad—, pelarangan ritual ibadah, praktik asimilasi melalui pemaksaan bahasa Mandarin sebagai standardisasi kurikulum sekolah maupun kamp konsentrasi, dipersulitnya pekerjaan Muslim Uighur, dan penyiksaan serta pembunuhan yang tersistematis. Semua itu bila dianalisis tidak lepas dari bagaimana arah kebijakan rezim komunis Tiongkok yang menginginkan terealisasinya One China Policy, bukan hanya konteksnya pada Taiwan saja melainkan juga seluruh teritori yang dianggap 'membengkang'.
Dengan dalih menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas negara—rezim komunis Tiongkok melakukan tindakan untuk 'menjinakkan' Muslim Uighur sekalipun dengan menghalalkan kekerasan. Tidak sedikit aksi unjuk rasa masyarakat Uighur yang dilibas habis oleh tentara militer Tiongkok, semisal kita dapat lihat ketika demo terjadi di Urumqi pada tahun 2009. Sementara di sisi lain, secara terus menerus sejak pasca proklamasi kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok diteruskan sampai saat ini, negeri bekas Dinasti Qing tersebut memiliki kebijakan untuk membuat etnis Han bermigrasi secara berbondong-bondong ke daerah Xinjiang.
Perlu diketahui, Han merupakan kelompok etnis terbesar di Tiongkok dengan jumlah sekitar 90% sehingga tak ayal rezim komunis memperkuat identitas itu sebagai upaya mengabsahkan integrasi. Semakin banyaknya migrasi etnis Han di Xinjiang menimbulkan gesekan dengan penduduk asli, terlebih dari segi 'kultur'—hal demikian bermuara kepada upaya Tiongkok untuk mengasimilasi Muslim Uighur, didukung dengan kebjiakan keluarga berencananya di sana. Kebijakan keluarga berencana tentu memberi manfaat bagi etnis Han yang tingkat pertumbuhannya 2x lipat lebih tinggi dibandingkan suku lain yang rata-rata hanya 15,9%.
Acapkali pemerintah Tiongkok mengkambing hitamkan etnis Uighur ketika peristiwa-peristiwa teror terjadi. Kecemasan akan pergerakan Muslim Uighur yang dikhawatirkan ingin melakukan tindakan separatisme atau memisahkan diri dari Tiongkok dan membangun negara sendiri bukanlah perihal yang baru-baru ‘kemarin sore’, membahas sejarahnya pun pastinya panjang karena sebelum dataran Tiongkok dikuasai Partai Komunis pun, daerah yang kini Xinjiang tersebut menjadi saksi bahwa banyak tokoh pergerakan Uighur yang berupaya mengabsahkan kemerdekaannya dengan memproklamasikan Turkestan Timur. Perihal itu tentu menjadi kewaspadaan rezim komunis dari masa ke masa, sehingga dalam kasus ini upaya ‘menghomogenkan’ Tiongkok menjadi jalan yang ditempuh untuk menjaga integritas negeri bekas Dinasti Qing itu. Seolah-olah bukan hanya kebebasan beragama dan peri kemanusiaan saja yang dikekang, tetapi juga mengungkung keberagaman (multikulturalisme).
Respon Indonesia yang Kurang Maksimal dalam Menangani Isu Uighur
Lantas ditengah terpuruknya nasib Muslim Uighur, di mana negara-negara ‘Muslim’ lain yang seharusnya datang untuk menolong sanak seukhuwahnya? Terlebih Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim di dunia. Hingga kini belum ada respon pasti Indonesia terkait antara mengencam atau setuju dengan kebijakan Tiongkok tersebut. Keberhati-hatian Indonesia tentu tidak mengherankan karena Tiongkok sendiri merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Belum lagi jumlah utang Indonesia—menurut Bank Indonesia—kepada Tiongkok mencapai 21,7 juta dolar USD atau setara 326,7 triliun. Menjadikan Tiongkok sebagai tempat pinjaman keempat terbesar setelah Jepang, AS, dan Singapura.
Tambah lagi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menjadi agenda pembangunan strategis tanah air tentu tidak lepas dari 'ketergantungan' dengan Tiongkok. Mengingat modal dari Kereta cepat Jakarta Bandung yang menggelontorkan lebih Rp.64,9 trilun atau sekitar 4,55 miliar USD tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok yang kian menguat tentu menjadi faktor kuat bagaimana Indonesia harus semakin hati-hati dalam menangani isu Uighur. Maka wajar saja apabila kita melihat Indonesia lebih memilih untuk menghindar apabila menghadapi perdebatan terkait isu Uighur di PBB maupun di forum internasional lainnya.
Di tengah kuatnya hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok yang sama-sama memperjuangkan kepentingannya di tengah isu Uighur, sekalipun dalam keadaan dilematis, Indonesia masih tetap memiliki peran ‘manusiawi’ dalam meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi di sana. Terlebih dengan bagaimana peluang dua organisasi massa terbesar yakni NU dan Muhammadiyah sebagai garda terdepan dalam mengawal kasus Uighur berjalan berbarengan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Harapnya peranan organisasi non-pemerintah terlebih yang berbasis agama di Indonesia mampu menggelorakan aktivitas bantuan kemanusiannya kepada saudara-saudara di Uighur untuk mengurangi penderitaan yang terjadi di sana, ini menjadi ikhtiar ke depannya agar sedikit demi sedikit permasalahan terkait peri kemanusiaan dapat diprioritaskan sebaik mungkin.
Penutup
Dapat diambil benang merah bahwa One China Policy menjadi kebijakan Tiongkok untuk memperkuat kedaulatan dan integritas nasionalnya sehingga tidak heran rezim komunis yang berkuasa menghalalkan segara cara termasuk tindak kekerasan, asimilasi paksa, dan genosida--yang menjadi fenomena di Xinjiang—untuk 'menjinakkan' Uighur yang selama ini dianggap membengkang. Dari fenomena penderitaan Muslim Uighur yang direnggut hak dan kebebasannya, timbul pertanyaan di mana negara-negara Muslim?
Terlebih dalam hal ini Indonesia. Sementara tidak sedikit khalayak telah memahami bahwa posisi dilematis Indonesia kini kian rumit, ketergantungan utang, investasi, maupun proyek dengan Tiongkok diyakini sebagai alasan penting bagaimana Indonesia hingga kini tidak bisa menyatakan sikap antara mendukung atau mengecam pelanggaran HAM di Xinjiang. Sekalipun begitu, Indonesia masih tetap berpeluang untuk meminimalisir tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana dengan mengirimkan bala bantuan terlebih melalui ormas-ormas Islam (misalnya NU dan Muhammadiyah) maupun elemen organisasi non-pemerintah yang terkait.