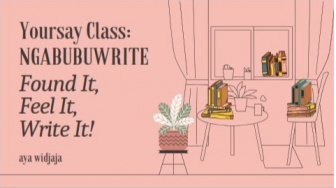Pendidikan merupakan wadah utama bagi anak-anak Indonesia untuk dapat mencapai apa yang mereka impikan. Meskipun pendidikan tidak akan menjamin kesuksesan seseorang, namun setidaknya dengan pendidikan dapat meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan.
Selain menimba ilmu berupa banyak mata pelajaran, di sekolah juga anak-anak dituntut untuk belajar mengenai sopan santun, tata krama, dan kebiasaan baik lainnya untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, setidaknya di lingkungan terdekatnya yaitu keluarga.
Indonesia mempunyai banyak talenta muda di bidang pendidikan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tidak akan pernah kehilangan murid-murid berprestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Namun, bagi saya, hal tersebut bukan tolok ukur bagaimana pendidikan Indonesia bisa dikatakan “maju”.
Sebagai kelahiran tahun 90-an akhir, pendidikan tata krama sudah menjadi fokus utama di sekolah yang saya tempati. Terkhusus di Jawa Barat sendiri, kita tidak akan kehilangan para anak yang jalan membungkuk di kala mereka berjalan melewati orang yang lebih dewasa. Pun, ketika di sekolah, mereka sudah terbiasa untuk mencium tangan ketika bertemu dengan guru—meskipun itu bukan guru yang mengajarnya di kelas. Pemandangan seperti itu sudah menjadi hal lumrah di kalangan siswa.
Berbeda dengan zaman sekarang, tata krama seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan, sudah banyak kasus murid yang melawan gurunya sendiri. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduknya yang sopan. Orang luar negeri pun dibuat keheranan ketika melihat anak-anak mencium tangan kepada orang yang lebih tua darinya.
Sebagai mantan seorang guru di sekolah swasta yang berbasis agama, saya melihat dengan jelas fenomena krisis tata krama tersebut. Tahun lalu saya berkesempatan untuk mengajar anak-anak kelas 4 SD di sebuah sekolah swasta yang ada di Bandung. Sekolah tersebut, seperti yang saya singgung sebelumnya, memang sangat menerapkan ilmu agama dalam kurikulumnya.
Di setiap sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak wajib untuk mengaji (murajaah dan ziyadah) selama kurang lebih dua jam bersama guru hafalannya masing-masing. Saat itu, saya memegang sembilan murid yang harus saya ajarkan mengaji. Hal tersebut tentunya tidaklah mudah, terlebih berhubungan dengan murid sekolah dasar.
Di kala mendampingi anak mengaji, masih ada anak yang tidak menerapkan tata krama ketika hendak membuka lembaran suci. Sebagai seorang guru, saya berperan untuk mencontohkan yang baik dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang hal yang harus dihindari dan harus dilakukan. Meskipun sudah berkali-kali diingatkan hingga berbusa, tetap saja masih ada murid yang belum berubah. Saya memaklumi hal tersebut, sebab bisa saja mereka bosan dan ingin segera menyelesaikan hafalannya—sebelum belajar mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah lain.
Saya dengan penuh maklum mendapati murid yang sulit untuk konsentrasi ketika di kelas karena tempat saya bekerja merupakan di sekolah swasta yang bisa dibilang biaya masuknya cukup mahal—sehingga banyak murid yang harus melalui pendampingan ekstra. Saya juga bisa bilang, rata-rata orang tua murid di sekolah tempat saya mengajar merupakan orang yang berkecukupan—yang mana mereka sangat mempercayai guru di sekolah untuk membimbing anaknya.
Dalam beberapa kesempatan, saat saya dan rekan saya melakukan home visit ke rumah orang tua murid, ada beberapa orang tua murid yang menyekolahkan anaknya dengan tujuan “yang penting ngajinya bener, urusan mata pelajaran lain yang jelek tidak begitu mempermasalahkan,” dan ada pula orang tua yang bertujuan agar anaknya dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah, sementara mereka sendiri sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
Selama setahun mengajar, saya bisa membedakan karakter murid yang selalu bertemu dengan orang tuanya di rumah dengan yang jarang bertemu karena sibuk bekerja. Mereka yang jarang bertemu orang tuanya memiliki tata krama yang kurang baik dan cenderung malas. Meskipun sebenarnya ada juga yang tetap menjaga sopan santunnya karena dirawat oleh neneknya di rumah. Berbeda dengan murid yang lebih sering bertemu dengan pengasuhnya dibanding orang tuanya sendiri.
Saya tidak sepenuhnya menyalahkan peran orang tua yang kurang terhadap pendidikan tata krama anak ketika di sekolah. Ketika di sekolah, tentunya guru yang harus berperan lebih aktif terhadap segala permasalahan murid sebelum dilimpahkan ke orang tuanya. Namun, meskipun sudah diberikan contoh dan pembiasaan, masih banyak murid yang meninggalkan budaya tata krama kepada guru di sekolah. Peran guru sebagai teman memang sudah menjadi hal yang biasa di era sekarang ini. Namun, jika hal tersebut melewati batas, murid pun menjadi berperilaku seenaknya.
China boleh berbangga dengan murid-muridnya yang cerdas, Singapura boleh berbangga dengan murid-muridnya yang jenius dan rajin, dan Indonesia memang boleh berbangga dengan murid-muridnya yang berkompetisi olimpiade hingga ke luar negeri, namun sejatinya Indonesia harus berbangga dengan murid-muridnya yang terkenal sopan santun, membungkuk saat melewati orang lain—yang kini sudah semakin ditinggalkan. Bagi saya sendiri, pendidikan tata krama jauh lebih penting nilainya dibandingkan dengan pendidikan matematika, biologi, dan lain-lainnya.
Guru bukan gila hormat atau semacamnya, namun bukankah tata krama sopan santun memang sudah selayaknya diterapkan oleh para murid di sekolah? Jika krisis tata krama ini semakin mengakar, lantas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hilangnya budaya tata krama di kalangan pelajar Indonesia?