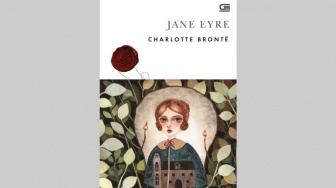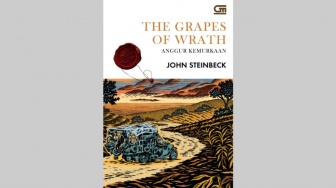"Yang penting halal," ungkapan yang telah menjadi semacam mantra sakti dalam masyarakat ketika berbicara tentang dunia kerja.
Sebuah petuah lama yang masih bergaung hingga kini, terutama ketika orang tua menasihati anaknya yang kesulitan mendapat pekerjaan atau ketika teman menghibur temannya yang terpaksa bekerja jauh di bawah kualifikasi.
Tapi di era ketika harga kebutuhan pokok terus menanjak sementara penghasilan sering mandek, akankah ungkapan ini tetap relevan?
Frasa ini lahir dari masa ketika sekadar bertahan hidup sudah menjadi prestasi tersendiri. Dari masa ketika kesederhanaan adalah kebajikan dan menuntut lebih dianggap keserakahan.
Bekerja halal menjadi kebanggaan karena menjamin seseorang tidak terjerumus dalam dosa dan aib sosial. Bekerja halal adalah bukti integritas, tanpa perlu mempertanyakan apakah pekerjaan itu adil atau memadai.
Namun zaman telah bergeser. Di kota-kota besar, gaji UMR nyaris mustahil untuk hidup layak. Seseorang mungkin bekerja dari pagi hingga malam, patuh pada semua peraturan kantor, tidak mencuri atau berbuat curang, tapi tetap tak mampu menyewa rumah yang layak atau menyekolahkan anak dengan baik.
Mereka tidak melanggar hukum, tidak pula melanggar agama. Tapi hidup mereka jauh dari sejahtera.
Sistem ekonomi yang kian kompetitif telah menciptakan dilema baru. Pengemudi ojek daring yang bekerja 12 jam sehari tetap harus khawatir tentang target yang semakin tinggi dan persaingan yang semakin ketat.
Pekerja kontrak yang setia pada perusahaan selama bertahun-tahun tetap tidak mendapat kepastian masa depan.
Guru honorer yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan tetap hidup dalam ketidakpastian. Semua pekerjaan ini halal, tapi apakah adil?
"Yang penting halal" seringkali menjadi pembenaran untuk kondisi kerja yang eksploitatif. Ketika pekerja dibayar rendah, dibebani jam kerja berlebih, atau tidak diberikan jaminan kesehatan yang memadai, mereka sering diingatkan untuk bersyukur, "setidaknya ini halal".
Seolah kehalalan adalah puncak tertinggi aspirasi kerja, dan menginginkan lebih adalah bentuk ketidaksyukuran.
Generasi muda kini mulai mempertanyakan paradigma ini. Mereka menyadari bahwa bekerja bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi juga untuk berkembang dan bermakna.
Mereka mulai memahami bahwa kelayakan upah, keseimbangan waktu kerja-istirahat, dan jaminan kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar.
Mereka tidak menolak konsep kerja halal, tapi menambahkan dimensi baru: kerja yang memberdayakan.
Penting untuk dipahami bahwa mengkritisi ungkapan "kerja apa aja yang penting halal" bukanlah seruan untuk mencari jalan pintas atau mengabaikan integritas. Ini adalah ajakan untuk mengevaluasi sistem kerja secara lebih komprehensif.
Halal tetap menjadi prasyarat mendasar, tapi perlu dilengkapi dengan standar kesejahteraan dan keadilan.
Di negara-negara dengan sistem kesejahteraan yang baik, "kerja apa aja" tidak berarti harus menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar hidup layak atau tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Ada batas minimum yang dijamin negara, sehingga "yang penting halal" tidak menjadi jebakan bagi pekerja untuk menerima apapun yang ditawarkan.
Pertanyaan kritisnya: mengapa harus ada pertentangan antara halal dan layak? Mengapa tidak bisa keduanya?
Mengapa masyarakat dan sistem ekonomi kita belum mampu menciptakan ekosistem di mana pekerjaan halal juga secara otomatis berarti pekerjaan yang memberikan penghidupan layak?
Barangkali sudah waktunya untuk merumuskan kembali filosofi kerja yang lebih sesuai dengan realitas masa kini. "Kerja yang halal dan bermartabat" atau "Kerja yang halal dan memberdayakan" mungkin bisa menjadi alternatif dari sekadar "kerja apa aja yang penting halal".
Karena pada akhirnya, bekerja bukan hanya soal menghindari dosa, tapi juga tentang membangun kehidupan yang bermakna.
Tunggu dulu, ini bukan berarti menolak pekerjaan sederhana atau rendah upah sebagai batu loncatan. Ini adalah seruan agar setiap pekerjaan, sekecil apapun, tetap harus menghargai martabat manusia yang melakukannya.
Dan seruan agar kita semua, sebagai masyarakat, tidak begitu saja menerima ketidakadilan dengan dalih kehalalan.
Singkatnya, ungkapan "kerja apa aja yang penting halal" mungkin perlu diperbarui, bukan ditinggalkan. Kehalalan tetap menjadi fondasi, tapi bukan atap.
Di atasnya, kita perlu membangun pilar-pilar keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Hanya dengan begitu, kerja tidak sekadar menjadi sarana bertahan hidup, tapi benar-benar menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.