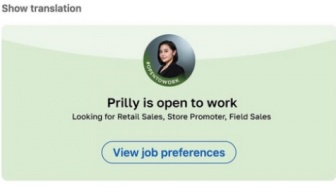Ada berita “seru” lagi dari negeri +62. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, baru saja mengumumkan bahwa sepanjang tahun 2024, nilai transaksi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia mencapai Rp1.459 triliun.
Dari angka fantastis itu, dugaan tindak pidana korupsi menyumbang porsi terbesar: Rp984 triliun.
Ya, kamu tidak salah baca. Sembilan ratus delapan puluh empat triliun rupiah duit rakyat, diduga raib lewat korupsi sepanjang tahun 2024. Itu baru angka dari laporan resmi PPATK, lho. Belum lagi yang lolos radar.
Uang sebesar itu kalau dibagi rata ke seluruh penduduk Indonesia, kita bisa dapat belasan juta rupiah per kepala.
Tapi sayangnya, uang itu malah mampir ke kantong-kantong haram, mengalir entah ke mana: properti mewah, mobil sport, villa di luar negeri, atau mungkin koleksi baju untuk kucing kesayangan.
Tapi, lucunya, begitu angka ini diumumkan, reaksi kita?
Paling-paling: "Oh... ya gitu deh."
Atau sekadar “Kasian banget ya negara kita... yaudah lanjut nonton drakor.”
Sejujurnya, korupsi di Indonesia sudah kayak acara tahunan. Kita pura-pura kaget, pura-pura peduli, lalu sibuk lagi dengan hidup masing-masing. Besok, ada kasus baru, kaget lagi. Siklus suci rakyat +62.
Saking seringnya, skandal korupsi sekarang lebih mirip serial TV ketimbang kejahatan serius. Ada drama, ada plot twist, ada tokoh antagonis, kadang ada plot redemption (yang biasanya berujung remisi).
Korupsi di Indonesia itu sudah kayak udara: ada di mana-mana, susah dilihat, tapi efeknya nyata bikin sesak.
Rp984 triliun ini bukan angka main-main. Itu hampir setara separuh APBN negara ini.
Bayangkan apa yang bisa dibangun dengan uang segunung itu: sekolah gratis, rumah sakit di desa-desa, jalan mulus dari Sabang sampai Merauke, subsidi pupuk buat petani, bahkan mungkin cukup buat membayar utang negara sebagian.
Tapi apa yang terjadi? Uang itu malah dirampok elite-elite berjas yang wajahnya kadang kita lihat di baliho “Pejuang Rakyat” tiap musim pemilu.
Uang itu justru “dicuci” dengan indah lewat bisnis properti, saham siluman, jet pribadi, dan kadang, koleksi tas mewah buat jalan-jalan ke Paris.
Kalau sudah rapi dicuci, siapa bisa bilang itu uang haram?
Toh, hukum di sini seringkali lebih ramah pada pelaku daripada pada rakyat yang menunggu keadilan.
Di negara normal, pencucian uang itu kejahatan berat.
Di sini? Ah, biasa aja. Ada bank-bank yang "khilaf," ada bisnis-bisnis yang "lengah," lalu duit haram bertransformasi jadi pendapatan sah.
Sementara itu, rakyat disuruh bangga karena katanya "pemberantasan korupsi terus jalan."
Jalan sih jalan, tapi kayak orang jogging di treadmill—capek, keringetan, tapi diam di tempat.
Pemerintah pasti akan bilang mereka serius melawan korupsi. Setiap tahun ada seremonial deklarasi antikorupsi, ada seminar nasional, ada tanda tangan besar-besaran di spanduk.
Tapi faktanya? Pelaku kelas kakap masih minum kopi di cafe hipster, sambil upload foto "work hard, play hard" di Instagram.
Aturan-aturan dibuat, tapi lembaga pengawas dilemahkan. Aparat sibuk menangkapi koruptor kelas teri, tapi sering pura-pura buta terhadap "ikan paus" yang menguasai laut.
Yang lebih tragis, kadang pelaku korupsi bisa melenggang bebas hanya karena “kurangnya bukti” atau permainan hukum berlapis-lapis.
Kalau korupsi sudah sebesar Rp984 triliun dalam setahun dan kita masih santai-santai saja, mungkin bangsa ini memang sudah naik level: dari negara berkembang jadi negara "terbiasa."
Jangan-jangan 5 tahun lagi, saat angka itu tembus Rp2.000 triliun, kita bakal tetap baca berita sambil ngemil keripik:
"Yah, biasalah. Negara kita emang begini."
Kalau kita serius mau perubahan, sudah waktunya sistem dibersihkan, bukan cuma seremoninya yang dirapikan.
Tangkap yang besar, buka semua jaringan, rampas asetnya, dan ingat: cuci otaknya juga, bukan cuma cuci uangnya.
Kalau tidak?
Selamat datang di Negara Koruptopia: di mana uang haram lebih cepat berkembang daripada ekonomi riil, dan keadilan cuma tinggal pajangan di lembaran konstitusi.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS