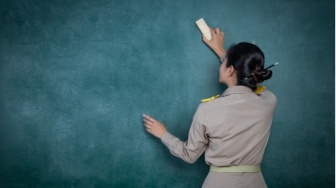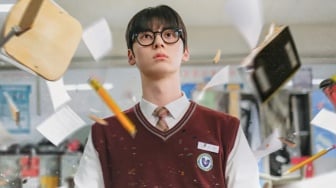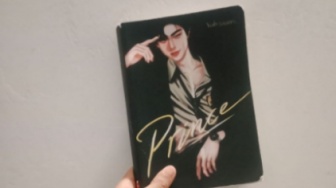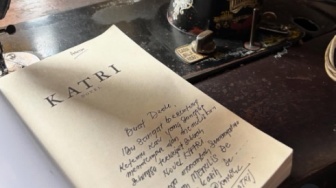Di tengah gelombang kampanye kesehatan mental dan jargon “work-life balance” yang kian marak, kita justru hidup dalam paradoks: kelelahan psikologis dijadikan lambang profesionalisme, kerja tanpa henti dipandang sebagai bukti loyalitas, dan burnout sebuah istilah yang sejatinya mengindikasikan kegagalan sistem telah bergeser menjadi simbol diam-diam kebanggaan. Budaya kerja “gila” ini tumbuh subur di ruang-ruang kantor, layar-layar digital, dan percakapan sosial media. Lelah dianggap keren, lembur dikultuskan, dan istirahat dianggap sebagai kemewahan yang hanya layak dinikmati oleh mereka yang “tidak cukup berambisi”.
Kita hidup di tengah masyarakat yang secara tidak sadar meromantisasi penderitaan. Di media sosial, seseorang yang mengunggah foto laptopnya yang masih menyala pukul dua pagi sering kali mendapatkan pujian, bukan keprihatinan. Di kantor, karyawan yang pulang terakhir dipandang sebagai “paling berdedikasi”, meski wajahnya sudah lesu dan matanya kosong. Di ruang akademik dan komunitas kreatif, seseorang yang mengalami kelelahan mental karena proyek yang tak berujung tetap dianggap sebagai “pekerja keras”, bukan korban sistem. Perlahan, kita menginternalisasi bahwa harga dari keberhasilan adalah pengabaian terhadap kesehatan diri sendiri.
Burnout bukan lagi sinyal bahaya, melainkan menjadi semacam lencana kehormatan. Ia bukan hanya terjadi karena pekerjaan yang menumpuk, melainkan akibat struktur dan budaya kerja yang sistematis mendorong individu terus berlari, bahkan ketika tubuh dan pikirannya sudah memberi sinyal untuk berhenti. Kondisi ini diperparah oleh standar sosial yang mengaitkan nilai diri seseorang dengan produktivitasnya. Orang yang sibuk dianggap berharga, sedangkan yang melambat dipandang malas atau tidak serius. Maka, tak heran jika banyak orang merasa bersalah saat beristirahat. Bahkan cuti pun harus dibenarkan dengan alasan-alasan logis, seolah-olah kebutuhan untuk pulih secara mental tidak cukup sah untuk diterima.
Realitas ini tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan di sektor pendidikan, nirlaba, hingga startup, tuntutan untuk selalu “siap siaga” telah menjadi normal baru. Tak sedikit yang menyebut kondisi ini sebagai internalisasi “kapitalisme performatif” di mana nilai manusia diukur berdasarkan output, dan segala bentuk kerentanan disembunyikan di balik senyum palsu dan laporan yang selesai tepat waktu. Bahkan ketika seseorang jatuh sakit karena stres kronis, respons lingkungan kerja sering kali tak lebih dari formalitas: bunga ucapan cepat sembuh, bukan perubahan sistemik.
Kontradiksi besar dalam budaya kerja modern adalah bagaimana organisasi begitu gencar menyuarakan pentingnya keseimbangan hidup, namun diam-diam menghargai mereka yang melanggarnya. Ada seminar tentang kesehatan mental, tetapi juga ada pesan WhatsApp yang dikirim di luar jam kerja. Ada program mindfulness, tapi juga ada deadline tidak realistis yang memaksa karyawan untuk tetap bekerja saat akhir pekan. Banyak perusahaan ingin tampak progresif, tetapi dalam praktiknya, yang dihargai adalah mereka yang rela berkorban.
Di sisi lain, para pekerja pun sering kali menjadi bagian dari lingkaran ini. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dianggap tidak kompeten, membuat banyak orang memilih diam. Mereka tahu bahwa sistemnya salah, tetapi lebih takut dianggap “tidak tahan banting”. Maka mereka bertahan, terus menekan emosi, mengubur kelelahan, dan merayakan luka sebagai bagian dari perjalanan sukses. Burnout pun tidak lagi dilihat sebagai kegagalan sistemik, tetapi sebagai semacam rite of passage yang harus dilalui untuk “naik level”.
Budaya ini juga memiliki dimensi kelas. Tidak semua orang bisa memilih untuk berhenti atau rehat. Mereka yang berada dalam kondisi finansial tertekan, atau yang bekerja dalam sektor informal, tidak punya pilihan selain terus bertahan. Maka burnout bukan hanya masalah psikologis, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi, politik organisasi, dan distribusi kekuasaan di dunia kerja. Yang kaya bisa berlibur untuk healing, sementara yang miskin harus menahan tangis dalam kesunyian.
Yang paling tragis, banyak dari kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang sakit. Kita terbiasa merasa lelah. Kita terbiasa menekan diri. Kita terbiasa menganggap itu semua sebagai bagian dari hidup dewasa. Maka kita terus bekerja, bahkan saat tubuh kita mulai memberontak. Kita terus menulis laporan, menghadiri rapat, membalas email, mengisi spreadsheet, meski pikiran kita sudah berkabut dan dada sesak tanpa alasan jelas. Kita tahu ini tidak sehat, tetapi kita juga tidak tahu bagaimana cara keluar.
Ulasan ini bukan ajakan untuk berhenti bekerja. Tapi ini adalah upaya untuk mempertanyakan nilai-nilai yang kita warisi dan wariskan. Mengapa kita begitu memuliakan kelelahan? Mengapa sistem kerja dibangun di atas pengorbanan diam-diam? Mengapa istirahat dianggap sebagai kelemahan, bukan kebutuhan? Sudah saatnya kita berhenti menjadikan burnout sebagai medali tak terucap. Kita perlu menciptakan budaya kerja baru yang menghormati batas, mengutamakan keberlanjutan mental, dan memberi ruang bagi manusia untuk menjadi manusia bukan mesin produksi. Dunia kerja seharusnya tidak menjadi medan perang, tetapi tempat di mana orang bisa tumbuh, berkontribusi, dan tetap sehat.
Dan pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah “Seberapa keras kamu bekerja?”, tapi “Apakah kamu masih utuh ketika pulang?” Jika jawabannya tidak, maka bukan kamu yang harus berubah. Sistemnya yang harus dirombak.