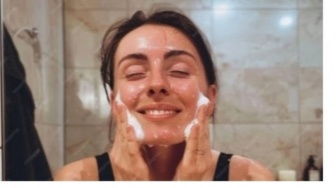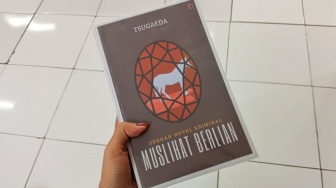Setiap tanggal 1 Mei, jalanan kota-kota besar di berbagai penjuru dunia dipenuhi oleh barisan manusia yang membawa spanduk, meneriakkan yel-yel, dan mengibarkan bendera perjuangan. Inilah May Day—sebuah hari yang tidak hanya merayakan kerja, tapi juga menyuarakan perjuangan.
Lebih dari sekadar tanggal merah di kalender, May Day telah menjelma menjadi simbol ketegangan sosial-politik antara buruh dan kekuasaan, antara rakyat dan negara, antara harapan dan realitas sebagaimana hasil studi yang ditemukan oleh Fisher (2020).
Dari Pabrik ke Panggung Dunia
Asal-usul May Day, sebagaimana yang dicatat oleh Fisher (2020), tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan kelas pekerja. Bermula dari tuntutan jam kerja delapan jam di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, May Day perlahan menjadi ajang internasional untuk menyuarakan hak-hak buruh.
Pada 1889, Kongres Sosialis Internasional di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Sejak itu, May Day menjadi panggung global yang memperlihatkan bagaimana kekuatan buruh dapat bersatu melampaui batas negara dan ideologi.
Namun, seperti semua simbol perjuangan, May Day juga tidak pernah steril dari kepentingan politik. Di banyak negara, hari ini diresmikan sebagai hari libur nasional. Pemerintah bahkan menyelenggarakan pawai resmi lengkap dengan orasi dari para pemimpin politik.
Di sisi lain, organisasi buruh independen dan gerakan rakyat tetap menjadikan May Day sebagai hari perlawanan. Di sinilah May Day menunjukkan wajah gandanya: perayaan sekaligus protes, ritual sekaligus resistensi.
Politik dan Ideologi: May Day di Tangan Negara
Di negara-negara sosialis seperti Tiongkok, Korea Utara, atau bekas Yugoslavia, May Day tidak hanya menjadi hari buruh, tetapi juga alat propaganda negara. Pemerintah menggelar parade besar-besaran yang menampilkan persatuan rakyat dan kepatuhan pada ideologi resmi. Media massa dikerahkan untuk menggambarkan loyalitas rakyat terhadap negara dan pemimpin mereka. Dalam konteks ini, May Day berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosialisme, mengukuhkan kekuasaan, dan menghapus ruang kritik.
Sebagaimana dicatat oleh Park (2020), dalam rezim seperti ini, May Day bukan semata-mata untuk pekerja, tetapi untuk negara. Ia menjadi panggung ideologis, tempat narasi kekuasaan dibacakan dengan megah. Barisan pekerja yang rapi, senyum yang dikoreografikan, dan slogan yang dikontrol menunjukkan bahwa perayaan ini telah diresmikan sebagai bagian dari mekanisme negara.
Ritualitas dan Resistensi: May Day sebagai Aksi Sosial
Namun May Day tak selalu tunduk pada kekuasaan. Di banyak negara dengan tradisi demokrasi, May Day justru menjadi ajang demonstrasi yang menantang status quo. Ribuan orang turun ke jalan membawa isu-isu kontemporer: upah minimum, sistem kerja kontrak, jaminan sosial, hingga perubahan iklim. Demonstrasi ini memiliki unsur ritual: dilakukan setiap tahun, dengan simbol dan narasi yang terus diperbarui. Di sinilah May Day tampil sebagai kekuatan oposisi yang terus hidup.
Menurut Peterson et al. (2012), ritualisasi dalam demonstrasi May Day berperan penting dalam menjaga daya tahan gerakan sosial. Meski seringkali tidak menghasilkan perubahan langsung, ritual ini menjaga nyala kesadaran kolektif, menjadi ruang ekspresi solidaritas, dan menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih adil.
Namun, tingkat “oposisi” dalam May Day sangat tergantung pada budaya dan situasi politik di masing-masing negara. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, May Day lebih bersifat seremonial karena sistem kesejahteraan sosial relatif mapan. Di Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, May Day sering berubah menjadi ajang konfrontasi yang sarat risiko represi.
Simbol Global, Makna Lokal
Yang menarik dari May Day adalah kemampuannya menjadi simbol global yang tetap mengakar pada konteks lokal. Di satu negara, ia bisa menjadi alat legitimasi negara; di negara lain, ia menjadi ajang perlawanan sipil. Di satu sisi, May Day adalah hari libur dengan parade yang penuh warna; di sisi lain, ia adalah ruang demonstrasi, terkadang disambut gas air mata dan pembatas kawat berduri.
Dengan demikian, May Day adalah cermin dari dinamika politik dan sosial suatu bangsa. Ia bisa menunjukkan apakah negara mendengar suara buruh atau sekadar menjadikannya ornamen dalam upacara kenegaraan. Ia juga bisa menjadi indikator apakah rakyat masih percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari jalanan.
Menjaga Makna di Tengah Komodifikasi
Tantangan terbesar May Day hari ini bukan hanya represi atau kooptasi negara, tapi juga komodifikasi. Ketika perayaan ini dipenuhi oleh diskon toko dan konten media sosial yang dangkal, maknanya bisa terkikis. Oleh karena itu, penting untuk terus menghidupkan kembali ruh perjuangan dalam May Day—agar ia tak sekadar menjadi seremoni tahunan, tapi tetap menjadi napas perjuangan buruh dan rakyat.
Dalam dunia yang kian terfragmentasi oleh algoritma dan disrupsi ekonomi, May Day tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa kerja manusia bukan sekadar angka di laporan perusahaan, tapi inti dari kehidupan sosial itu sendiri. Dan selama ketimpangan masih ada, selama suara buruh masih diredam, May Day akan terus hidup—sebagai ritual, sebagai panggung, dan sebagai perlawanan.