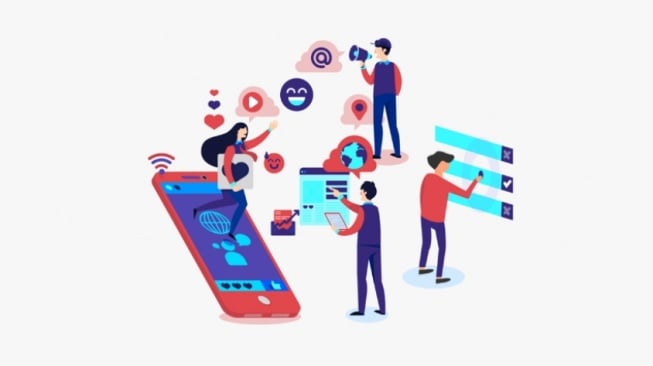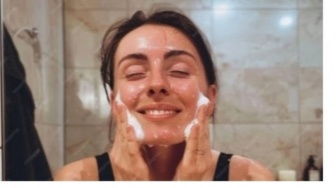Hidup di era digitalisasi hari ini, manusia serba terhubung dengan apa pun melalui digitalisasi. Segenggam teknologi seperti ponsel mendapatkan notifikasi bunyi tanpa henti, informasi datang dari segala arah, dan dunia terasa seperti tak pernah tidur. Di tengah derasnya arus digital seperti inilah, generasi muda khususnya Generasi Z, hidup dalam pusaran koneksi yang tanpa batas.
Laporan Indonesia Gen Z Report 2024 dari IDN Research Institute dan Populix mencatat, bahwa jumlah Gen Z di Indonesia mencapai 74,93 juta jiwa, sekitar 27,9 persen dari total penduduk. Mereka dikenal kreatif, cepat beradaptasi dengan teknologi, dan sangat aktif di dunia maya. Namun di balik keunggulan itu, generasi ini juga menghadapi tantangan besar, seperti tekanan sosial, stres, dan krisis emosional yang kian meningkat.
Penelitian Arsyad, Kurniawan, & Setiawan (2023) dalam Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health mencatat, angka gangguan emosional di Indonesia naik dari 6 persen pada 2013 menjadi 9,8 persen pada 2018, dengan lebih dari 19 juta penduduk terdampak. Sementara survei Jakpat (2022) yang dikutip The Jakarta Post menemukan bahwa 59 persen anak muda mengalami stres akibat tekanan akademik dan sosial. Ironisnya, semakin banyak “teman” di layar, justru semakin sedikit ruang untuk merasa benar-benar dekat dan tenang.
Koneksi Tanpa Batas, Makna yang Mulai Hilang
Istilah hyperconnected society pertama kali diperkenalkan oleh World Economic Forum (2009) dan dipopulerkan oleh Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution (2016). Schwab menggambarkan dunia yang terus terhubung, manusia, mesin, dan sistem digital saling berinteraksi tanpa jeda.
Namun, koneksi tanpa batas itu ternyata membawa efek samping yang berakibat kelelahan mental, kehilangan empati, dan pudarnya makna pertemuan manusia. Dunia yang sibuk berbicara justru semakin sunyi dari makna.
Di sinilah peran pendidikan amatlah penting. Sekolah dan kampus seharusnya tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk menemukan kembali nilai kemanusiaan. Peneliti pendidikan C.H. Sam (2021) menekankan pentingnya safe space dalam pembelajaran, ruang aman bagi siswa untuk berekspresi tanpa rasa takut dihakimi.
Guru dan Dosen: Peneduh di Tengah Bising Dunia Digital
Pendidik hari ini ditantang untuk bukan hanya mengajar, tapi juga menenangkan. Mereka perlu menjadi pendengar yang peka dan pembimbing yang lembut. Ada tiga hal sederhana yang bisa dilakukan:
Pertama, ciptakan ruang dialog di kelas agar siswa bisa berbagi perasaan dan keresahan mereka. Kedua, berikan waktu jeda, momen hening atau refleksi singkat di sela kegiatan belajar. Ketiga, hadirkan nilai spiritual dan moral bukan lewat ceramah, tapi lewat keteladanan dan doa yang hidup.
Riset The Dynamics of Prayer in Daily Life and Implications for Well-Being menunjukkan bahwa doa dapat menurunkan stres dan meningkatkan ketahanan psikologis. Aktivitas spiritual seperti shalat, misalnya, mampu memperkuat mindfulness atau kesadaran diri. Artinya, pendidikan yang menumbuhkan spiritualitas sejatinya membuat siswa tak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara emosional.
Shalat: Jeda dari Dunia, Pelajaran untuk Jiwa
Dalam Islam, shalat bukan sekadar kewajiban, melainkan latihan untuk menenangkan batin dan menata kesadaran. Shalat mengajarkan manusia berhenti sejenak dari kesibukan, menundukkan ego, dan kembali kepada Tuhan.
Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, “Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan shalat.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Pesan ini mengingatkan bahwa shalat adalah ruang istirahat bagi jiwa, bukan sekadar ritual harian.
Penelitian oleh Mohd Nasir Abdullah dkk. dalam Journal of Religion and Health (2017) menemukan bahwa orang yang melaksanakan shalat dengan penuh kesadaran memiliki tingkat stres lebih rendah dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dengan kata lain, shalat bisa menjadi terapi spiritual bagi guru dan siswa untuk menumbuhkan ketenangan, fokus, dan empati.
Islam Berkemajuan: Menyatukan Ilmu dan Iman
Dalam pandangan Risalah Islam Berkemajuan, manusia adalah ‘abdullah (hamba Allah) sekaligus khalifah di bumi, pembawa rahmat bagi semesta alam. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kemajuan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh ranah moral dan spiritual.
Artinya, pendidikan berbasis Islam Berkemajuan harus mampu menyeimbangkan rasionalitas dengan spiritualitas, serta teknologi dengan moralitas. Guru dan dosen berperan bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pembawa cahaya—menuntun generasi agar tidak hanyut dalam arus digital, melainkan tetap berpijak pada nilai-nilai Ilahi.
Menyalakan Cahaya di Tengah Riuh Digital
Mendidik di era hiperkoneksi bukan sekadar melatih siswa agar mahir teknologi, tapi juga menuntun mereka agar tetap manusiawi. Di tengah kebisingan digital, pendidik dipanggil menjadi peneduh: menghadirkan ketenangan, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Seperti Rasulullah SAW yang mendidik dengan cinta dan doa, guru masa kini pun perlu mengiringi pengajarannya dengan kasih dan harapan. Rasulullah bahkan mendoakan muridnya, Ibnu Abbas, “Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah tafsir kepadanya.” Doa itu menjadi simbol bahwa pendidikan sejati tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga pada ketulusan hati.
Semoga para pendidik masa kini mampu menyalakan cahaya itu, agar di tengah arus hiperkoneksi, lahir generasi yang cerdas nalar, tenang jiwanya, dan teguh dalam iman serta kemanusiaan.