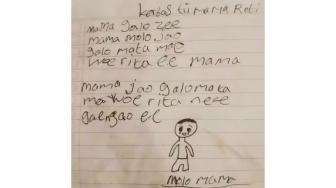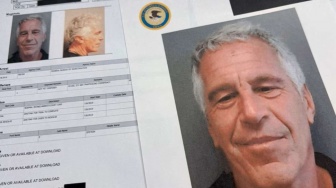Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan pernyataan Prabowo soal kekayaan negara yang katanya luar biasa setelah dikonsolidasikan lewat Danantara.
Ia mengatakan aset kelolaan Danantara diprediksi bisa mencapai Rp17.139 triliun. Iya, triliun. Dengan "t". Buat konteks: itu hampir 11 kali lipat lebih besar dari APBN 2024 yang ‘cuma’ Rp3.325 triliun. Bahkan, hanya dari dua aset awal—Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran—nilai yang terkumpul sudah sekitar Rp1.153 triliun.
Kalau angka-angka ini dibacakan sambil zoom-in wajah di TV nasional, mungkin banyak yang spontan tepuk tangan. Tapi begitu TV dimatikan dan kita balik ke realita—macet, harga beras naik, BPJS antre, kosan naik harga—muncul pertanyaan mendasar: "Buat apa sih pamer angka segede itu ke publik, kalau dampaknya ke rakyat masih nggak terasa?"
Coba bayangin kamu punya paman super kaya, rumahnya tiga lantai, koleksi mobilnya berjejer dari Mercy sampai Tesla. Tapi setiap kali kamu minta tolong bayar uang sekolah, jawabannya selalu, “Lagi ada proyek besar, ya bersabar dulu ya.”
Mirip, kan?
Itulah perasaan sebagian besar rakyat ketika negara disebut-sebut “kaya banget”, tapi kenyataannya, fasilitas publik masih gitu-gitu aja. Jadi, rakyat disuruh bangga karena nilai nominal asetnya tinggi, tapi kenyamanan dasarnya nggak naik-naik juga.
Kalau memang negara sekaya itu, kenapa kita belum merasakan hasilnya?
Mari kita bahas inti dari semuanya: Danantara. Ini adalah BUMN baru yang dibentuk untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset-aset negara yang selama ini “nggak jelas nasibnya”.
Presiden Prabowo menyebut ini sebagai terobosan luar biasa. Bahkan dia menyentil birokrasi lama yang katanya gagal melihat potensi aset negara.
Oke, fair enough. Tapi di sinilah letak bahayanya. Ketika aset sebesar itu dikelola oleh satu entitas—tanpa struktur audit independen yang jelas, tanpa keterlibatan publik yang transparan, dan belum ada skema investasi yang konkret—ini bukan inovasi, ini potensi kekacauan.
Sudah ada yang bilang di medsos: "Ngeri sih ngebayangin aset segede itu dikontrol oleh satu tangan, tanpa kontrol ketat. Bila gagal, tidak dianggap sebagai kerugian negara."
Dan itu benar adanya. Karena beda dari APBN yang harus melalui proses pengawasan DPR, BUMN seperti Danantara bisa bergerak lebih fleksibel—dan di situ celah pengawasan makin longgar.
Yang bikin tambah gatal adalah ketika nilai-nilai fantastis ini diumumkan dengan gaya seolah kita semua seharusnya kagum dan bersyukur. Tapi lagi-lagi: apa dampaknya buat rakyat? Apakah keberadaan Danantara bakal bikin harga sewa kos turun? Jalanan makin mulus? Internet desa makin kencang?
Sampai saat ini, jawabannya belum jelas.
Alih-alih menjelaskan bagaimana aset ini akan diubah jadi layanan publik yang lebih baik, negara justru sibuk memoles angka besarannya. Padahal kita butuh roadmap: apa tujuannya? Siapa yang akan menikmati hasilnya? Bagaimana transparansi dan risikonya?
Karena sejarah sudah berkali-kali ngajarin kita: uang yang besar tanpa pengawasan itu kayak main petasan di ruang tertutup—suaranya bisa keren, tapi risikonya bisa menghancurkan segalanya.
Kekayaan negara nggak ada gunanya kalau warganya tetap merasa miskin. Dan kalau pengelolaan aset ini hanya jadi ajang gengsi tanpa menyentuh kebutuhan dasar rakyat, maka Danantara cuma akan jadi seperti folder kosong yang dinamai “Rencana Hebat”, tapi isinya masih coming soon.
Narasi “negara kita kaya kok” udah sering kita dengar. Tapi itu narasi yang gampang dijual dan gampang dipolitisasi.
Masalahnya, narasi nggak bisa menggantikan distribusi. Mau negara punya tanah seluas langit, kalau aksesnya tetap dikuasai segelintir orang atau institusi yang nggak transparan, ya rakyat tetap di posisi penonton.
Kita nggak butuh ilusi kaya. Kita butuh kesejahteraan yang nyata, yang bisa dirasakan langsung oleh orang-orang biasa.
Jadi, kita harus ngapain?
Pertama, jangan langsung kagum hanya karena angka besar diumumkan di media. Justru saat angka-angka itu muncul, kita harus lebih kritis: siapa yang pegang, bagaimana dia mengelola, dan untuk apa semua itu?
Kedua, dorong transparansi. Danantara harus punya mekanisme pelaporan publik. Audit independen, keterlibatan masyarakat sipil, dan pengawasan media itu wajib hukumnya. Bukan sekadar pelengkap.
Dan yang terakhir: jangan biarkan narasi “kita kaya” bikin kita lupa bahwa kenyataan rakyat masih penuh tantangan. Karena kalau kekayaan negara cuma bisa dibanggakan di podium, tapi tidak bisa dinikmati di dapur rakyat—itu bukan kemajuan, itu cuma pentas.
Aset triliunan? Keren. Tapi kami tunggu bukti nyatanya, bukan sekadar angka di slide presentasi.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS