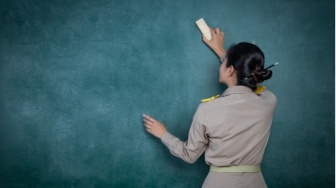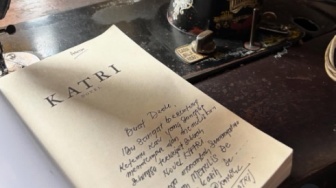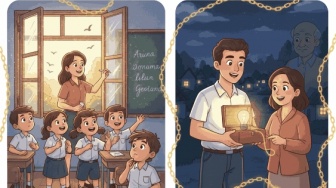Jogja dikenal sebagai kota budaya, kota pelajar, kota kenangan. Tapi siapa sangka, di balik harmonisasi suara gamelan dan aroma gudeg, terselip satu nada sumbang yang terus menghantui para pelancong dan warga lokal: parkir nuthuk. Iya, itu lho, tarif parkir yang mendadak melonjak tanpa aba-aba, seperti harga cabai di musim hujan.
“Selamat datang di Jogja! Silakan nikmati keindahan Malioboro, dan jangan lupa bayar parkir Rp15.000 di pinggir jalan umum!” Tentu saja ini bukan slogan resmi, tapi tampaknya sudah jadi SOP tidak tertulis para juru parkir (jukir) nakal yang berkeliaran lebih lihai daripada ninja.
Fenomena ini bukan baru kemarin sore. Dari laporan warga yang diminta bayar Rp15.000 di depan BCA Mangkubumi, hingga pembelaan klasik ala “biaya kas kampung”, semuanya menunjukkan bahwa masalah ini sudah menjelma menjadi budaya baru: budaya pungli berjubah parkir.
Lalu, ke mana pemerintah? Ke mana dinas perhubungan? Ke mana suara-suara garang waktu kampanye? Pertanyaan itu menggema seperti suara kentongan ronda yang diabaikan: terdengar, tapi dibiarkan.
Mari kita kupas “hama wisata” ini seperti membedah kerak di loyang, karena kalau dibiarkan, Jogja bukan lagi kota kenangan, tapi kota kenangan pahit — karena uang parkirnya lebih mahal dari cilok isi mozzarella.
Dari Jalan ke Jalur Setan – Kronologi Parkir Nuthuk
Parkir nuthuk bukan cuma keluhan, tapi telah menjelma menjadi pola. Pola yang bisa ditebak seperti sinetron kejar tayang: viral → sidak → pura-pura normal → kambuh lagi → repeat until amnesia.
Menurut regulasi resmi, tarif parkir mobil di kawasan Mangkubumi seharusnya hanya Rp5.000. Tapi apa daya, beberapa jukir justru menjual “pengalaman spiritual” dengan tarif Rp15.000. Katanya sih, Rp5.000 buat kas kampung. Tapi coba cek: ada kuitansinya? Ada LPJ-nya? Atau jangan-jangan kas kampung itu hanya istilah sopan dari “uang diam-diam”?
Malioboro, yang konon katanya kawasan pedestrian dan tertib, sering kali jadi ladang parkir liar yang mengular seperti antrean BTS (yang boyband, bukan infrastruktur). Belum sempat kita menikmati keindahan malam Malioboro, dompet sudah terasa lebih tipis karena parkir dadakan yang tarifnya lebih fleksibel dari kurs rupiah terhadap dolar.
Warga pun jengah. Wisatawan kapok. Sementara pemerintah masih asyik rapat koordinasi yang hasilnya hanya PDF panjang tapi tanpa gigi. Bahkan, laporan dan pengaduan publik ke dinas perhubungan lebih sering jadi bahan display daripada bahan tindakan. Kalau aduan warga diibaratkan nasi goreng, maka nasibnya sudah lewat jam makan dan basi di meja birokrasi.
Wisatawan Jadi Tumbal, Ekonomi Mikro Ikut Tersedak
Parkir nuthuk ini bukan hanya soal recehan yang menguap, tapi soal bagaimana citra kota ditentukan oleh interaksi paling remeh: parkir. Sebab tak semua wisatawan menilai kota dari museum atau prasasti. Kadang, kesan mendalam justru datang dari hal sepele: apakah mereka harus adu mulut dengan jukir? Atau bisa parkir tenang tanpa takut dompet dikuras?
Ketika satu keluarga dari Semarang harus membayar parkir Rp20.000 di pinggir jalan, mereka pulang membawa oleh-oleh berupa kisah getir, bukan bakpia. Dan sayangnya, testimoni macam itu lebih viral dari iklan pariwisata resmi Pemda DIY.
Dampaknya menjalar ke ekonomi mikro. Warung lesehan sepi karena orang ogah turun dari mobil. Toko oleh-oleh gigit jari. Pemandu wisata kelimpungan karena rombongan jadi membatalkan rute. Dalam ekonomi wisata, persepsi sangat menentukan. Jika Jogja dikenal sebagai kota “parkir mahal”, maka yang tumbuh bukan kunjungan wisata, tapi kecurigaan publik.
Literatur menyebutkan bahwa kemacetan dan parkir liar menurunkan kenyamanan dan produktivitas kawasan wisata (Morillo & Campos, 2014). Ditambah lagi, penelitian Alfaridzi et al. (2023) menunjukkan bahwa pungli dan tata kelola buruk justru menurunkan kepercayaan investor. Maka jangan heran jika investasi pariwisata mandek, dan UMKM lokal kembang-kempis sambil menanti keajaiban dari Satpol PP.
Tukang Parkir Liar, Kewenangan yang Menguap
Jika tukang parkir resmi punya rompi, peluit, dan SK dari Dinas, maka tukang parkir liar hanya butuh satu senjata: kepercayaan diri. Modal nekad dan tampang galak sudah cukup untuk menguasai satu petak jalan. Bahkan kadang lebih sakti dari aparat: bisa ngatur jalan, narik duit, dan bikin macet — tanpa izin dan tanpa malu.
Parkir liar bukan sekadar pelanggaran, tapi sudah menyerupai industri bayangan. Mereka tahu kapan dinas sidak, tahu harus pindah ke mana jika lokasi ramai, bahkan tahu teknik nego dengan aparat. Seolah-olah, ini semua bagian dari “ekosistem liar” yang justru tumbuh subur karena ketidaktegasan pemerintah.
Beberapa pihak berdalih bahwa jukir liar juga rakyat kecil yang cari makan. Benar. Tapi membiarkan mereka mengganggu ketertiban dan merusak citra kota demi “cari makan” itu ibarat membiarkan nyamuk menggigit karena kita kasihan dia lapar. Akhirnya, kota jadi sakit — dan nyamuknya makin berani.
Transportasi yang semrawut, kemacetan akibat parkir ilegal, dan distribusi barang yang terganggu merupakan efek domino dari pembiaran ini (Tsakalidis & Tsoleridis, 2015). Setiap detik yang terbuang karena macet adalah kerugian ekonomi. Tapi rupanya, sebagian pejabat kita lebih sibuk menghitung like di media sosial daripada menghitung kerugian riil akibat macet dan parkir liar.
Kenapa Tak Disemprot? Karena Semprotnya Pakai Angin
Pemerintah Kota Yogyakarta tak tinggal diam — katanya. Mereka mengklaim telah melakukan sidak, penindakan, dan patroli. Tapi nyatanya, semua itu seperti menyemprot hama dengan kipas angin: berbunyi, berputar, tapi tak berdampak.
Mengapa sulit menertibkan jukir nakal? Apakah ada “tameng” politik, atau memang pemerintah kita terjebak dalam sindrom “asal jangan ribut”? Setiap laporan viral, Satpol PP turun. Tapi begitu kamera mati, semuanya kembali seperti biasa. Jogja menjadi kota dengan manajemen “event-based”: hanya bergerak kalau diviralkan.
Coba tengok media sosial. Komentar warga seperti: “Bayar parkir, tapi kehilangan nggak ditanggung.” atau “Kalau nggak mau ribet, ya ikhlas aja dikerjain.” menunjukkan betapa masyarakat sudah capek. Bukan hanya pada jukir, tapi pada sistem yang membiarkan mereka tumbuh tanpa rem.
Kalau pengawasan tak diperketat, kalau tindakan tak berlanjut, dan kalau hukum hanya jadi aksesoris pidato, maka selamat datang di Jogja: kota di mana “parkir liar” punya hak lebih besar dari pemilik kendaraan itu sendiri.
Solusinya? Terapkan sistem parkir digital yang transparan dan langsung terintegrasi dengan sistem pembayaran. Terapkan sanksi bukan hanya pada jukir, tapi juga pada pengelola yang membiarkan praktik semacam ini terjadi. Jangan segan mencabut izin dan ekspos mafia parkir ke publik. Kalau perlu, adakan razia dengan live stream di media sosial, biar viralnya produktif.
Dari Kota Budaya ke Kota Bikin Emosi?
Parkir nuthuk hanyalah satu dari sekian banyak persoalan urban yang membusuk karena dibiarkan. Tapi ia menonjol karena langsung bersentuhan dengan rakyat — dari wisatawan yang mampir sebentar hingga warga lokal yang hidup sehari-hari. Ini bukan sekadar soal tarif, tapi soal moralitas tata kelola kota.
Jogja tak akan kehilangan pamornya sebagai kota budaya hanya karena satu dua jukir nakal. Tapi jika pembiaran terus terjadi, maka budaya pungli akan menggerogoti keistimewaan Jogja seperti rayap menggerogoti tiang rumah. Dan kelak, yang tersisa dari keistimewaan itu hanyalah slogan tanpa substansi.
Pemerintah harus tegas. Bukan sekadar pasang spanduk larangan, tapi hadir nyata di lapangan. Digitalisasi parkir bukan mimpi — banyak kota sudah memulainya. Yang kita butuhkan hanya kemauan politik dan keberanian menghadapi “kerajaan kecil” yang selama ini berlindung di balik istilah “masyarakat kecil cari makan”.
Jogja bisa. Jogja harus bisa. Tapi pertama-tama, semprot dulu hama bernama parkir nuthuk ini — jangan cuma pakai angin.