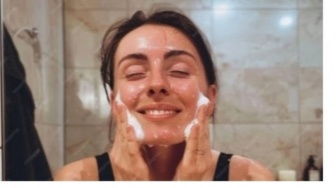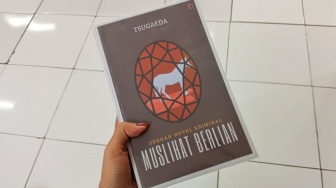Mari kita jujur. Di tengah belantara beton yang semakin panas dan ruang publik yang kian terkikis, mal telah bertransformasi menjadi oase modern. Sebuah katedral megah berpendingin udara tempat kita semua, dengan satu atau lain cara, datang untuk mencari keselamatan. Dan di antara para peziarah itu, ada dua sosok legendaris yang belakangan ini sering menjadi buah bibir, bahkan bahan gunjingan para pemilik modal. Ya, mereka itu disebut sebagai Rojali dan Rohana.
Rojali, singkatan dari "Rombongan Jajan Beli Kagak," dan pasangannya, Rohana, "Rombongan Hanya Nanya-nanya," adalah arketipe pengunjung yang dianggap sebagai "hama" oleh ekosistem retail. Mereka adalah para "pengunjung hantu." Mereka datang berbondong-bondong, memenuhi koridor mal yang berkilauan, mata mereka berbinar menatap etalase yang memajang mimpi-mimpi dalam bentuk tas kulit, sepatu lari keluaran terbaru, atau ponsel pintar yang kameranya bisa menangkap kawah di bulan. Mereka mungkin akan mampir ke sebuah toko, menyentuh bahan kemeja dengan lembut, bertanya pada pramuniaga, "Ini diskonnya bisa nambah lagi, Mbak?" sambil berharap ada keajaiban. Setelah puas berkeliling, mungkin satu-satunya transaksi yang mereka lakukan adalah membeli dua gelas es teh manis di food court lantai paling atas, sekadar membasahi tenggorokan yang kering setelah napak tilas berjam-jam. Lalu, mereka pulang. Tanpa kantong belanjaan.
Bagi para peritel, mereka adalah anomali yang menyebalkan. Data foot traffic tinggi, tapi angka penjualan stagnan. Mereka dianggap parasit yang hanya menikmati fasilitas—AC gratis, toilet bersih, dan pemandangan barang-barang mewah—tanpa memberikan kontribusi sepeser pun. Tapi, tunggu sebentar. Mari kita tarik napas dalam-dalam, hirup udara mal yang sejuk ini, dan bertanya dengan sedikit lebih waras, "apakah benar Rojali dan Rohana yang salah? Apakah hasrat mereka untuk tidak membeli adalah sebuah dosa kapitalisme? Ataukah keberadaan mereka justru merupakan termometer paling jujur yang mengukur suhu asli perekonomian kita?", sebuah realita yang jauh lebih pahit dari janji-janji manis yang kerap kita dengar.
Menyalahkan Rojali dan Rohana karena tidak belanja di mal itu ibarat memarahi cermin karena menunjukkan wajah kita yang kusam dan lelah. Mereka bukanlah penyebab masalah; mereka adalah gejala. Gejala dari sebuah penyakit ekonomi yang lebih dalam, yang akarnya menjalar hingga ke kebijakan-kebijakan di menara gading pemerintahan, jauh dari lantai marmer mal tempat mereka berjalan-jalan. Ini bukan cerita tentang orang-orang yang tidak mau belanja. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang ingin, tapi tidak bisa. Dan kegagalan untuk memahami itu adalah kegagalan terbesar kita semua.
Alun-Alun Modern dan Hak Rekreasi Kaum Urban
Sebelum kita menelanjangi data ekonomi yang rumit, mari kita pahami dulu fungsi mal dalam tatanan sosial masyarakat urban Indonesia kontemporer. Coba sebutkan satu tempat di kota besar yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga di akhir pekan, yang aman, bersih, sejuk, tidak becek saat hujan, punya banyak pilihan hiburan visual, dan—ini yang paling penting—gratis untuk dimasuki? Taman kota? Sebagian mungkin terawat, tapi banyak yang lain menjadi arena pertarungan nyamuk demam berdarah atau kurang penerangan di sore hari. Museum? Pilihan bagus, tapi tidak semua orang punya minat yang sama dan seringkali ada tiket masuk. Perpustakaan daerah? Suasananya terlalu hening untuk membawa anak-anak yang sedang aktif-aktifnya.
Mal, dengan segala kekurangannya, secara de facto telah mengambil alih peran alun-alun kota. Ia adalah ruang publik multifungsi tempat semua kelas sosial bisa berbaur, setidaknya secara fisik. Di sinilah seorang eksekutif muda yang baru membeli jam tangan mewah bisa berjalan berpapasan dengan keluarga Rojali yang kebahagiaan puncaknya adalah saat anak mereka bisa naik eskalator bolak-balik sebanyak lima kali.
Fenomena "cuci mata" atau window shopping bukanlah hal baru. Ini adalah bentuk rekreasi yang paling terjangkau. Bagi banyak keluarga, perjalanan ke mal adalah agenda utama akhir pekan. Bukan untuk berbelanja, tapi untuk "keluar rumah." Untuk melihat keramaian, merasakan denyut kehidupan kota, dan sejenak melarikan diri dari sumpeknya kamar kos atau rumah kontrakan yang sempit. AC mal adalah kemewahan yang bisa dinikmati tanpa perlu membayar tagihan listrik yang membengkak. Etalase yang ditata apik adalah galeri seni gratis. Pramuniaga yang ramah (meski kadang tatapannya sinis jika kita terlihat tidak potensial) adalah bagian dari interaksi sosial.
Menyalahkan mereka karena hanya "lihat-lihat" adalah sebuah pandangan yang luar biasa elitis dan ahistoris. Seolah-olah satu-satunya tujuan mulia datang ke pusat perbelanjaan adalah untuk melakukan transaksi. Ini mengabaikan fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang butuh ruang untuk sekilas ada dan bersama. Ketika negara gagal menyediakan ruang publik yang layak, nyaman, dan mudah diakses bagi warganya, maka jangan kaget jika warganya mencari alternatif lain. Dan mal, dengan segala gemerlapnya, adalah alternatif yang paling menggoda.
Jadi, ketika kita melihat Rojali dan Rohana, kita tidak sedang melihat sekelompok orang malas yang enggan bekerja dan berbelanja. Kita sedang menyaksikan manifestasi dari kebutuhan dasar manusia akan rekreasi dan ruang komunal. Mereka tidak mencuri, tidak merusak, tidak mengganggu ketertiban. Mereka hanya "menggunakan" ruang yang tersedia dengan cara yang paling sesuai dengan kapasitas kantong mereka. Mengkritik mereka sama jenakanya dengan mengkritik orang yang berteduh di halte saat hujan deras, hanya karena orang itu tidak berniat naik bus. Mereka hanya butuh tempat berlindung. Rojali dan Rohana pun sama, mereka butuh tempat "berlindung" dari kepenatan hidup, dan mal kebetulan adalah tempat terbaik untuk itu.
Autopsi Dompet Rojali: Janji Manis vs Realita Pahit
Sekarang, mari kita bedah alasan sebenarnya mengapa kantong belanjaan Rojali dan Rohana tetap kosong melompong. Jawabannya tidak terletak pada karakter mereka, melainkan pada angka-angka brutal dalam neraca keuangan rumah tangga mereka. Ini adalah panggung di mana janji-janji pemerintah yang megah berhadapan langsung dengan kenyataan di warung sebelah rumah.
Pemerintah, dalam setiap pidato dan rilis persnya, selalu menyajikan narasi optimis. Pertumbuhan ekonomi akan meroket, daya beli masyarakat akan ditingkatkan, dan—janji yang paling sering didaur ulang—jutaan lapangan pekerjaan akan diciptakan. Salah satu janji yang paling berkesan adalah penciptaan 19 juta lapangan kerja. Sebuah angka fantastis yang terdengar seperti solusi pamungkas bagi segala masalah. Namun, bagi Rojali, angka itu tetaplah sebuah abstraksi. Yang konkret baginya adalah harga sebungkus mi instan yang naik dua ratus perak, harga beras yang terus merayap naik, dan tarif listrik yang diam-diam mencekik.
Di sinilah data berbicara lebih keras dari slogan. Studi oleh Hafidzi & Afroh (2024) menyoroti bagaimana kenaikan harga barang pokok, terutama energi dan makanan, secara disproposional menghantam kelompok berpendapatan rendah. Rojali dan Rohana adalah representasi hidup dari data ini. Pendapatan mereka yang mungkin tidak seberapa, sebagian besar habis hanya untuk memastikan ada nasi di piring dan lampu di rumah tetap menyala. Ketika biaya untuk bertahan hidup (survival cost) sudah menyedot porsi terbesar dari penghasilan, apa yang tersisa untuk membeli kemeja baru atau sepatu diskon di mal? Jawabannya, tentu tidak ada.
Keinginan untuk membeli itu ada. Siapa yang tidak ingin memakai baju baru saat Lebaran? Siapa yang tidak ingin mengganti ponsel lamanya yang sudah sering hang? Hasrat konsumtif adalah bagian dari fitrah manusia modern yang dibombardir iklan setiap detik. Rohana mungkin sudah memimpikan tas tangan yang ia lihat di etalase itu selama berbulan-bulan. Tapi antara keinginan dan kemampuan, terbentang jurang yang dalam bernama daya beli.
Lebih jauh lagi, ketidakpastian ekonomi global, seperti yang diungkapkan oleh Massil et al. (2025), membuat masyarakat—bahkan yang kelas menengah sekalipun—cenderung mengerem pengeluaran. Mereka memilih untuk menahan belanja dan memperbanyak tabungan sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti PHK atau krisis ekonomi lanjutan. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati. Keputusan untuk membeli barang yang bukan kebutuhan primer menjadi sebuah pertaruhan besar. "Apakah saya benar-benar butuh ini?" menjadi pertanyaan yang menghantui setiap kali mereka memegang sebuah produk di mal.
Dan di mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan? Liu & An (2023) mencatat bahwa berkurangnya lapangan kerja di sektor manufaktur—sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti Rojali—telah menurunkan pendapatan masyarakat dan memperburuk kemiskinan. Pabrik-pabrik tekstil atau sepatu yang tutup berarti ribuan Rojali kehilangan pekerjaan tetapnya, lalu banting setir menjadi pengemudi ojek online atau pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak menentu. Bagaimana kita bisa berharap seseorang dengan pendapatan harian yang fluktuatif untuk berkomitmen pada cicilan barang elektronik?
Maka, menyalahkan para peritel yang lesu darah kepada Rojali dan Rohana adalah sebuah tindakan "kambing hitam" yang paling pengecut. Seharusnya, energi kemarahan itu diarahkan ke alamat yang benar, yaitu pemerintah. Mengapa janji peningkatan daya beli hanya menjadi macan kertas? Mengapa program-program ekonomi tidak terasa dampaknya di tingkat akar rumput? Mengapa 19 juta lapangan kerja masih terasa seperti fatamorgana di tengah gurun? Menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas janji-janji inilah yang seharusnya menjadi fokus, bukan mengutuk pengunjung yang datang ke mal dengan niat suci untuk mendinginkan badan dan pikiran.
Ekonomi 'Tetesan Embun' dan Fatamorgana Pertumbuhan
Pemerintah sering membanggakan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif. Di atas kertas, ekonomi kita terlihat sehat dan bertumbuh. Namun, apa yang dirasakan oleh Rojali dan Rohana seringkali berkebalikan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai model "ekonomi tetesan embun," sebuah kritik terhadap teori "ekonomi tetesan ke bawah" (trickle-down economics).
Teori trickle-down beranggapan bahwa jika pemerintah memberikan keuntungan bagi korporasi besar dan orang-orang kaya (misalnya melalui insentif pajak atau kemudahan investasi), kekayaan itu pada akhirnya akan "menetes" ke bawah dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, yang terjadi seringkali adalah "ekonomi tetesan embun." Tetesannya begitu kecil, begitu sedikit, dan seringkali sudah menguap sebelum sempat mencapai tanah yang kering kerontang di bawahnya.
Kue ekonomi memang membesar, tetapi irisan yang diterima oleh kaum pekerja dan masyarakat berpendapatan rendah tidak bertambah secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir elite yang memiliki akses ke modal dan kekuasaan. Proyek-proyek infrastruktur raksasa seperti jalan tol baru atau bandara megah memang terlihat mengesankan dan berkontribusi pada angka PDB. Tapi mari kita bertanya dengan jenaka, "Emangnya jalan tol bisa dimakan?" Bagi Rojali yang sehari-hari berjuang dengan biaya transportasi umum atau harga bensin eceran, kemegahan jalan tol adalah pemandangan yang ia nikmati dari kejauhan, bukan sesuatu yang secara langsung mengisi dompetnya.
Fatamorgana pertumbuhan ini berbahaya. Ia menciptakan dua realita yang paralel. Di satu sisi, ada narasi resmi pemerintah yang penuh dengan angka-angka positif dan optimisme. Di sisi lain, ada realita pasar tradisional dan warung kelontong tempat harga-harga terus naik dan daya beli terus tergerus. Mal menjadi titik temu dua realita ini. Gemerlap lampu dan kemewahan barang-barang di mal adalah representasi dari narasi optimisme itu. Sementara itu, Rojali dan Rohana yang berjalan melewatinya dengan tangan hampa adalah representasi dari realita pahit di tingkat akar rumput.
Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi dalam prioritas pembangunan. Fokus pada pertumbuhan makroekonomi seringkali mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan mikro. Pemerintah mungkin berhasil mengundang investasi asing miliaran dolar untuk membangun pabrik smelter baru di daerah terpencil. Ini bagus untuk neraca perdagangan. Tapi pada saat yang sama, pemerintah mungkin abai terhadap nasib jutaan UMKM yang terseok-seok karena persaingan dengan produk impor murah atau kesulitan mendapatkan kredit dari bank.
Rojali dan Rohana adalah korban dari ilusi ini. Mereka melihat kemakmuran di sekeliling mereka—di iklan TV, di media sosial para influencer, dan di etalase mal—tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya. Ini menciptakan sebuah frustrasi kolektif. Mereka tidak miskin dalam artian kelaparan absolut, tetapi mereka "miskin" dalam konteks masyarakat konsumeris yang terus-menerus mendikte bahwa kebahagiaan dan status sosial diukur dari apa yang kita miliki dan konsumsi. Kehadiran mereka di mal tanpa membeli adalah sebuah bentuk perlawanan pasif, sebuah pernyataan diam-diam yang berbunyi, "Kami ada di sini, kami melihat apa yang kalian tawarkan, tapi sistem yang kalian ciptakan tidak memungkinkan kami untuk berpartisipasi."
Suara Sunyi dari Lantai Marmer
Pada akhirnya, kisah Rojali dan Rohana adalah cerminan besar dari masyarakat kita. Mereka adalah kita, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Mereka adalah perwujudan dari angan-angan yang terbentur oleh kenyataan, dari keinginan yang terkekang oleh keterbatasan. Mereka berjalan di atas lantai marmer yang dingin dan berkilauan, di bawah cahaya lampu yang terang benderang, sebuah metafora sempurna untuk janji kemakmuran yang terlihat begitu dekat namun terasa begitu jauh.
Tindakan mereka yang hanya "lihat-lihat" bukanlah sebuah kemalasan atau kepasifan. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah protes sunyi. Sebuah laporan kondisi bangsa yang jauh lebih jujur daripada pidato kenegaraan manapun. Mereka adalah bukti hidup bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata hanya akan menciptakan etalase-etalase indah yang tidak bisa dijangkau oleh rakyatnya sendiri.
Jadi, lain kali Anda pergi ke mal dan melihat sebuah keluarga yang tertawa riang hanya karena mencoba kursi pijat gratis, atau sepasang anak muda yang menghabiskan waktu berjam-jam di toko buku tanpa membeli satu pun, janganlah menghakimi mereka sebagai "Rojali dan Rohana." Lihatlah mereka sebagai barometer. Lihatlah mereka sebagai pengingat.
Dan kepada para pemangku kebijakan dan pemilik modal, berhentilah bertanya, "Kenapa mereka tidak belanja?" Mulailah bertanya pada diri sendiri, "Sistem seperti apa yang telah kita ciptakan sehingga mereka tidak bisa belanja?" Jawabannya mungkin tidak akan nyaman didengar, tapi di sanalah letak kunci untuk membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya bertumbuh di atas kertas, tetapi juga menyejahterakan di dunia nyata. Karena ekonomi yang sehat bukanlah tentang seberapa banyak barang di etalase, melainkan tentang seberapa banyak orang yang mampu tersenyum saat membawanya pulang.