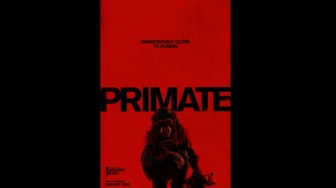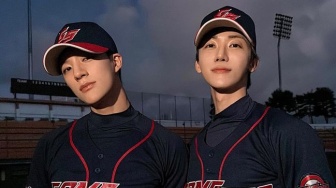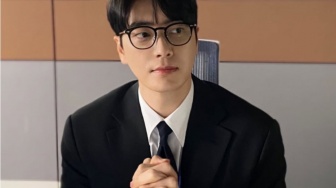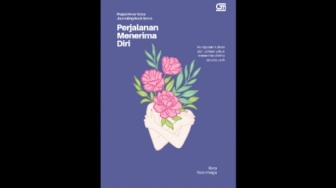- Politik ketakutan dijalankan lewat pasal karet & intimidasi digital, bikin rakyat memilih diam.
- Jika dibiarkan, demokrasi hanya jadi formalitas, ruang publik bebas perlahan terkunci.
- Kasus Ferry menunjukkan kritik publik makin sering dilabeli pidana tanpa bukti jelas.
Setiap kali ada kasus hukum yang menjerat aktivis atau tokoh publik, aparat akan beralasan, “Ini bukan soal orangnya, ini soal pesannya.” Kita bisa ganti namanya siapa saja—Ferry Irwandi, aktivis HAM, jurnalis investigasi, atau mahasiswa yang bikin thread panjang di Twitter. Ketika suara mereka terlalu keras, aparat akan muncul dengan solusi, label pidana.
Dalam kasus Ferry, tuduhannya bahkan belum jelas. Komandan Satuan Siber TNI hanya menyebut adanya dugaan tindak pidana terkait pernyataan soal algoritma internet.
Belum ada bukti, belum ada detail, hanya sebuah stempel yang cukup membuat publik merinding, dugaan pidana. Dan seringkali, kata-kata itu sudah cukup untuk membentuk opini publik bahwa orang yang kritis dianggap salah, bahkan sebelum proses hukum dimulai.
Secara teori, hukum seharusnya netral. Tapi dalam praktiknya, hukum bisa menjadi senjata politik. Dengan melabeli kritik sebagai pidana, aparat menciptakan efek jera yang jauh lebih besar daripada kasus individualnya. Bukan cuma Ferry yang kena imbas, tapi ribuan orang lain yang sedang mengetik kritik di laptop atau HP masing-masing.
Inilah yang disebut politik ketakutan. Bukan cuma menindak satu orang, tapi seolah memberi pesan keras kepada semua orang, “Kalau kamu bicara terlalu keras, lihat apa yang terjadi.”
Di era Orde Baru, politik ketakutan dijalankan dengan cara terang-terangan, mulai dari penculikan aktivis, sensor media, hingga pelarangan buku. Orang tak perlu benar-benar ditangkap untuk merasa takut. Cukup ada beberapa contoh korban, maka sisanya akan memilih diam.
Reformasi 1998 seolah menjanjikan kebebasan. Media menjamur, demonstrasi jalanan meledak, internet mulai jadi ruang ekspresi alternatif. Tapi politik ketakutan tidak hilang, hanya berubah wajah.
Kini, bukannya senjata laras panjang, yang dipakai adalah pasal karet. UU ITE misalnya, jadi momok yang menakutkan bagi banyak orang.
Kalimat sepele di media sosial bisa dianggap pencemaran nama baik atau menyebarkan hoaks. Dan kalau aparat tidak turun tangan, ada buzzer yang siap menyerbu akunmu, melaporkan massal, atau mengintimidasi di kolom komentar.
Publik pun akhirnya tahu kalau bicara kritis berarti siap menanggung risiko. Kalau beruntung, hanya kehilangan akun. Kalau sial, bisa dilaporkan ke polisi.
Politik ketakutan tidak perlu menangkap semua orang yang bersuara, cukup satu atau dua orang publik figur. Dengan begitu, orang lain akan berpikir berkali-kali sebelum ikut menyuarakan kritik yang sama.
Kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, misalnya, sering jadi alarm untuk gerakan masyarakat sipil yang lebih luas. Ketika satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena menolak tambang atau proyek besar, ratusan warga lain yang berniat melakukan hal serupa mundur perlahan. Ketakutan lebih efektif daripada represi total, karena ia membuat orang memilih diam secara sukarela.
Dalam konteks Ferry, logika yang sama bisa terbaca, seorang influencer yang punya audiens besar, dikenal dengan gerakan edukasi dan tuntutan rakyat, diberi cap dugaan pidana. Kalau sosok dengan massa sebanyak itu bisa dibidik, apalagi kita yang hanya punya ratusan follower?
Demokrasi sejatinya berdiri di atas ruang publik yang terbuka, di mana kritik, ide, dan suara minoritas bisa hidup. Tapi kalau ruang publik itu dikawal dengan ancaman pidana, maka yang tersisa hanyalah demokrasi formalitas, dimana ada pemilu, ada partai, ada parlemen, tapi rakyat lebih banyak diam.
Kita seperti kembali ke zaman di mana orang berbisik saat bicara politik, tapi dengan medium berbeda, jika dulu di warung kopi, maka sekarang di grup WhatsApp pribadi.
Politik ketakutan ini makin berbahaya karena arena yang diperebutkan adalah internet, ruang paling vital bagi generasi muda. Di sinilah mahasiswa mengorganisir aksi, jurnalis independen mencari pembaca, dan tempat aktivis menggalang solidaritas. Kalau ruang ini dikuasai dengan cara intimidasi, maka satu-satunya tempat bebas rakyat akan terkunci.
Dan ironisnya, aparat yang menjalankan politik ketakutan di internet seringkali tidak bisa mengimbangi kreativitas publik digital. Meme, satir, dan kritik justru lahir dari keterdesakan. Tapi kalau intimidasi berlanjut, lama-lama humor pun bisa kehilangan daya. Kita akan punya dunia digital penuh hiburan, tapi tanpa kritik.
Sejarah mengajarkan bahwa politik ketakutan selalu berumur pendek, tapi meninggalkan luka panjang. Orde Baru bertahan tiga dekade, tapi rasa trauma dan diam rakyat masih terbawa hingga sekarang. Begitu juga kriminalisasi aktivis di era pasca-reformasi, setiap kasus meninggalkan rasa was-was yang diwariskan ke generasi berikutnya.
Kita sering bicara soal jangan sampai demokrasi mundur. Tapi tanda-tanda kemunduran itu sudah dimulai dari hal-hal kecil, dari sebuah kritik yang dibungkam, dari seorang aktivis yang dituduh pidana, dan dari influencer yang ditakut-takuti. Dari sana, perlahan-lahan, publik belajar bahwa diam lebih aman daripada bersuara.
Kalau politik ketakutan ini terus dibiarkan, lama-lama kita akan terbiasa. Kita akan menganggap wajar kalau kritik dilabeli pidana. Kita akan merasa normal kalau influencer harus berhati-hati bicara algoritma. Kita akan lupa bahwa dulu internet pernah jadi ruang paling bebas.
Pertanyaannya, apakah kita rela? Atau kita akan melawan, meski dengan cara menolak diam, menolak lupa, dan terus menjaga ruang publik tetap hidup?