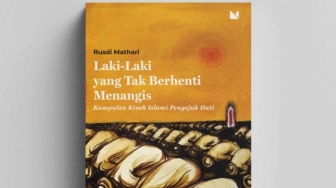Merantau selalu punya tempat istimewa dalam imajinasi anak muda Indonesia. Sejak dulu, cerita tentang para perantau digambarkan sebagai kisah keberanian dan kemandirian, seolah seseorang baru dianggap “dewasa sungguhan” ketika berani hidup jauh dari rumah.
Ada rasa bangga ketika bisa berkata, “Aku merantau,” seakan itu menjadi bukti bahwa kita siap menantang hidup. Tetapi di balik kebanggaan itu, ada juga sisi lain yang jarang diceritakan: rasa sepi yang tiba-tiba menyergap, tekanan hidup yang datang tanpa jeda, hingga kebingungan mencari jati diri.
Pada titik ini, muncul pertanyaan yang sering kita abaikan apakah merantau benar-benar membuat seseorang tumbuh, atau malah berpotensi membuatnya tersesat?

Bagi mahasiswa baru, terutama yang pertama kali meninggalkan rumah, merantau ibarat membuka pintu menuju dunia yang benar-benar berbeda. Semua terasa asing: lingkungan yang belum dikenali, teman baru yang belum tentu cocok, rutinitas yang berubah total.
Tidak ada lagi suara ibu yang mengingatkan untuk sarapan atau bertanya apakah sudah pulang dengan selamat. Tidak ada lagi ayah yang siap menjemput ketika hujan turun deras. Semua hal kecil yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba terasa sangat berarti ketika tidak ada lagi yang mengurus. Dari sinilah proses belajar dimulai pelan, tapi nyata.
Hari-hari awal merantau biasanya diisi dengan adaptasi: mencari kos yang nyaman, menata kamar seadanya, mencoba memahami jalan-jalan kota, hingga berlatih mengatur uang agar cukup sampai akhir bulan. Mandiri bukan lagi teori, tapi kewajiban.
Menyuci baju sendiri, memutuskan makan apa hari ini, memastikan kebutuhan terpenuhi tanpa ada yang mengingatkan, semua menjadi bagian dari perjalanan seseorang menuju kedewasaan. Meskipun melelahkan, pengalaman-pengalaman kecil ini sesungguhnya yang membentuk karakter seseorang.
Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Tidak semua perantau berhasil melewati masa-masa sulit ini. Ada yang terlalu larut dalam kebebasan sehingga lupa menjaga diri.
Ada pula yang tenggelam dalam kesepian karena tidak punya tempat pulang selain kamar kecil di kota asing. Beberapa kehilangan motivasi belajar, terjebak pergaulan yang tidak sehat, atau merasa tidak menemukan pegangan hidup. Di sinilah merantau menjadi ujian mental sesungguhnya: apakah seseorang cukup kuat berdiri sendiri tanpa dukungan langsung keluarga?
Tak sedikit yang akhirnya tumbang, merasa kewalahan, atau bahkan memutuskan pulang karena tidak sanggup melanjutkan. Tapi banyak juga yang bangkit justru karena jatuh. Mereka belajar memperbaiki diri, belajar mencari bantuan, dan mengenal batas kemampuan mereka sendiri. Merantau, pada akhirnya, bukan hanya soal jarak yang ditempuh, tetapi bagaimana seseorang menghadapi realitas hidup yang tidak selalu ramah.
Meski penuh tantangan, merantau tetap menyimpan keindahan yang sulit dijelaskan. Bertemu orang-orang baru dengan latar belakang berbeda, belajar menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada siapa pun, hingga menemukan hal-hal yang selama ini tidak disadari tentang diri sendiri—semua menjadi pengalaman berharga yang tidak semua orang miliki.
Ada kepuasan tersendiri ketika menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa menakutkan kini bisa ditangani seorang diri. Kadang justru di kota asing itulah seseorang menemukan keberanian, tujuan baru, bahkan identitas diri yang selama ini tersembunyi.
Lalu, apakah merantau menjadikan seseorang lebih baik atau lebih buruk?
Mungkin jawabannya tidak sesederhana itu. Merantau adalah ruang belajar besar yang mengajarkan tentang hidup, manusia, dan kedewasaan. Ia bisa menjadi batu loncatan menuju kemandirian, tetapi bisa juga berubah menjadi jebakan jika dijalani tanpa direction atau tanpa kemampuan untuk mengenali batas diri.
Pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa jauh kita pergi, melainkan seberapa besar kita tumbuh dari setiap langkah yang kita pilih. Merantau bukan tentang meninggalkan rumah, tapi tentang menemukan versi terbaik dari diri sendiri.