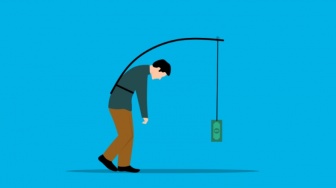Kolom
Jika Kota Tidak Ramah Pejalan Kaki, Gaya Hidup Sehat Sulit Diwujudkan?

Dalam wacana gaya hidup sehat, berjalan kaki sering disebut sebagai aktivitas paling sederhana dan murah. Ia tidak membutuhkan keanggotaan gym, peralatan khusus, atau waktu yang rumit untuk dijadwalkan. Namun, di sebagian besar kota di Indonesia, berjalan kaki justru menjadi aktivitas yang melelahkan, berisiko, dan sering kali dihindari. Di sini, muncul ironi yang jarang disorot: bagaimana mungkin gaya hidup sehat didorong, jika kota tempat orang hidup tidak dirancang untuk tubuh manusia?
Kota kerap dibayangkan sebagai ruang kemajuan, efisiensi, dan modernitas. Tetapi bagi pejalan kaki, kota sering terasa bermusuhan. Trotoar sempit, berlubang, terputus, atau berubah fungsi menjadi area parkir dan lapak pedagang. Menyusuri kota dengan berjalan kaki bukan pengalaman yang menenangkan, melainkan perjuangan untuk bertahan dari kendaraan bermotor, panas, dan ketidakpastian arah. Dalam kondisi seperti ini, berjalan kaki bukan lagi pilihan rasional, apalagi menyenangkan.
Infrastruktur yang Mengabaikan Tubuh
Masalah utama kota yang tidak ramah pejalan kaki terletak pada prioritas pembangunan. Sejak lama, perencanaan kota lebih memihak kendaraan bermotor. Jalan diperlebar, flyover dibangun, dan parkiran diperbanyak, sementara trotoar menjadi pelengkap yang sering dikorbankan. Tubuh manusia seolah dipaksa menyesuaikan diri dengan mesin, bukan sebaliknya.
Padahal, kota yang baik seharusnya dimulai dari skala manusia. Pejalan kaki adalah pengguna jalan paling dasar. Jika mereka tidak merasa aman dan nyaman, maka ada yang keliru dalam cara kota dirancang. Ketika trotoar tidak layak, orang terpaksa naik motor atau mobil bahkan untuk jarak yang sangat dekat. Aktivitas fisik harian pun tergantikan oleh pola hidup sedentari.
Dampaknya bukan hanya pada kesehatan individu, tetapi juga kesehatan publik. Kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ironisnya, solusi yang ditawarkan sering kembali ke ranah individual: olahraga lebih rajin, atur pola makan, dan jaga kesehatan. Padahal, lingkungan tempat tinggal tidak mendukung kebiasaan sehat tersebut.
Gaya Hidup Sehat sebagai Privilege
Di kota yang tidak ramah pejalan kaki, gaya hidup sehat perlahan berubah menjadi privilese. Mereka yang tinggal di kawasan dengan trotoar layak, taman kota, atau lingkungan yang aman untuk berjalan kaki memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup aktif. Sementara itu, warga di kawasan padat, pinggiran kota, atau wilayah dengan infrastruktur minim harus berjuang lebih keras untuk sekadar berjalan dengan aman.
Akibatnya, kesehatan tidak lagi semata soal pilihan personal, tetapi juga soal lokasi dan kelas sosial. Berjalan pagi di lingkungan hijau atau jogging di taman kota menjadi aktivitas yang tidak merata aksesnya. Kota menciptakan ketimpangan kesehatan yang sering kali tidak disadari, karena dibungkus dalam narasi tanggung jawab individu.
Lebih jauh, budaya kendaraan bermotor juga membentuk cara pandang masyarakat. Berjalan kaki kerap diasosiasikan dengan ketidakmampuan, bukan kesadaran kesehatan. Di beberapa konteks, orang yang berjalan kaki dianggap tidak praktis atau tidak efisien. Stigma ini semakin menjauhkan aktivitas berjalan kaki dari identitas gaya hidup modern.
Kota, Kesehatan Publik, dan Hak atas Ruang
Kota yang ramah pejalan kaki tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Berjalan kaki memberi ruang untuk memperlambat ritme, mengamati sekitar, dan terhubung dengan lingkungan. Ketika kota tidak menyediakan ruang aman untuk itu, warga kehilangan kesempatan berinteraksi secara lebih manusiawi dengan ruang hidupnya.
Ketiadaan trotoar yang layak juga mencerminkan persoalan yang lebih dalam: siapa yang dianggap penting dalam kota. Ketika pejalan kaki terpinggirkan, kota berubah menjadi ruang transit, bukan ruang hidup. Warga hanya bergerak dari satu titik ke titik lain secepat mungkin, tanpa benar benar mengalami kotanya sendiri.
Dalam konteks ini, berjalan kaki bukan sekadar aktivitas, melainkan hak. Hak atas ruang publik yang aman, inklusif, dan sehat. Hak untuk bergerak tanpa takut tertabrak, tersandung, atau diusir dari trotoar. Mengabaikan hak ini berarti mengabaikan kualitas hidup warganya.
Membangun Kota yang Layak Dijalani
Mewujudkan gaya hidup sehat tidak bisa hanya mengandalkan kampanye dan imbauan. Ia membutuhkan perubahan struktural dalam perencanaan kota. Trotoar yang lebar dan berkesinambungan, peneduh dari panas, penyeberangan yang aman, serta integrasi dengan transportasi publik adalah prasyarat dasar. Kota harus didesain agar berjalan kaki menjadi pilihan yang masuk akal, bukan pengorbanan.
Lebih dari itu, perubahan paradigma juga diperlukan. Kota bukan sekadar mesin ekonomi, tetapi ruang kehidupan. Ketika pejalan kaki diberi prioritas, kota menjadi lebih inklusif, sehat, dan manusiawi. Gaya hidup sehat pun tidak lagi menjadi beban individu, melainkan hasil alami dari lingkungan yang mendukung.
Pada akhirnya, kota yang tidak ramah pejalan kaki sedang memproduksi warganya sendiri yang tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Jika gaya hidup sehat benar-benar ingin diwujudkan, maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana warga hidup, tetapi bagaimana kota itu sendiri dirancang untuk dijalani.