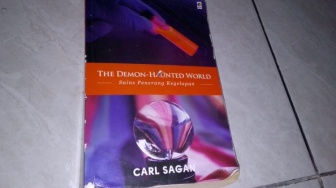Dalam beberapa tahun terakhir, authenticity menjelma menjadi kata kunci dalam budaya digital. Platform media sosial mendorong pengguna untuk tampil “apa adanya”, berbagi pengalaman personal, dan mengekspresikan emosi secara terbuka. Ironisnya, ajakan menjadi autentik ini justru berlangsung di ruang yang sangat terukur, di mana setiap ekspresi berpotensi dimonetisasi.
Platform digital bekerja dengan logika ekonomi perhatian. Unggahan yang terasa jujur, mentah, dan personal cenderung memperoleh keterlibatan tinggi. Dari cerita kegagalan karier, kecemasan hidup, hingga kemarahan sosial, ekspresi personal diubah menjadi konten yang bernilai ekonomi. Autentisitas tidak lagi sekadar nilai moral atau psikologis, tetapi juga aset yang dapat dikapitalisasi.
Dalam konteks ini, menjadi autentik berarti memasuki paradoks. Semakin seseorang menampilkan diri secara personal, semakin besar peluang visibilitas dan keuntungan. Namun, pada saat yang sama, ekspresi tersebut terjebak dalam mekanisme platform yang menuntut keterulangan, konsistensi persona, dan kepatuhan pada selera algoritma. Autentisitas lalu bergerak dari kejujuran spontan menuju bentuk performatif yang dioptimalkan.
Ketika Ekspresi Diri Menjadi Performa yang Dikurasi
Monetisasi ekspresi mendorong lahirnya praktik kurasi diri yang intens. Pengguna belajar, secara sadar maupun tidak, untuk mengenali jenis kejujuran yang “aman” dan “laku”. Tidak semua pengalaman layak dibagikan, dan tidak semua emosi mendapat ruang yang sama. Platform menghargai kejujuran yang bisa dikemas, disederhanakan, dan dikonsumsi cepat.
Dalam situasi ini, autentisitas sering kali bukan tentang mengungkapkan diri sepenuhnya, melainkan memilih bagian diri yang paling kompatibel dengan logika platform. Kesedihan harus punya narasi pemulihan, kritik harus dibungkus humor, dan kegelisahan harus terasa relevan secara universal. Ekspresi yang terlalu kompleks, ambigu, atau tidak ramah algoritma cenderung tenggelam.
Kondisi ini memunculkan tekanan psikologis baru. Individu dituntut untuk terus “menjadi diri sendiri” dalam versi yang konsisten dan dapat dikenali publik. Persona digital harus dipelihara agar tidak kehilangan audiens. Di titik ini, autentisitas berubah menjadi pekerjaan emosional. Ekspresi diri tidak lagi sekadar proses refleksi personal, tetapi bagian dari strategi keberlangsungan di ruang digital.
Fenomena ini juga mengaburkan batas antara ekspresi dan eksploitasi diri. Ketika pengalaman personal terus-menerus diproduksi sebagai konten, individu berisiko kehilangan jarak kritis terhadap emosinya sendiri. Apa yang semula menjadi ruang pengakuan dan pemulihan berubah menjadi komoditas yang harus selalu siap ditampilkan.
Mencari Makna Autentik di Tengah Logika Monetisasi
Dalam lanskap seperti ini, pertanyaan tentang makna autentisitas menjadi semakin penting. Jika semua ekspresi berpotensi dimonetisasi, apakah autentisitas masih mungkin? Jawabannya mungkin tidak terletak pada kemurnian absolut, melainkan pada kesadaran dan negosiasi.
Menjadi autentik di platform yang memonetisasi ekspresi berarti menyadari struktur yang membentuk cara kita berbicara, berbagi, dan tampil. Autentisitas bukan ketiadaan kepentingan ekonomi, melainkan kemampuan menjaga otonomi dalam menentukan apa yang dibagikan dan apa yang tetap menjadi wilayah privat. Ada batas yang sengaja dipertahankan, meski platform mendorong keterbukaan tanpa henti.
Pendekatan ini menuntut literasi digital yang lebih kritis. Pengguna perlu memahami bahwa dorongan untuk “jujur” sering kali berkelindan dengan kepentingan bisnis platform. Dengan kesadaran tersebut, autentisitas dapat dimaknai sebagai praktik selektif, bukan total. Kejujuran tetap hadir, tetapi tidak seluruhnya tunduk pada tuntutan visibilitas.
Pada akhirnya, autentisitas di era monetisasi ekspresi bukanlah soal menolak platform, melainkan merumuskan ulang relasi dengan teknologi. Ia hadir ketika individu mampu menggunakan ruang digital tanpa sepenuhnya dikendalikan olehnya. Dalam kondisi ini, autentisitas bukan lagi citra yang dijual, melainkan sikap reflektif untuk tetap menjadi subjek, bukan sekadar produk, di tengah ekonomi perhatian yang semakin agresif.