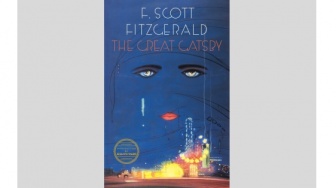Memasuki peralihan abad 20 ke abad 21, gender menjadi salah satu topik hangat yang tak pernah membosankan untuk dibahas. Beberapa waktu lalu, muncul dan mewabah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan feminisme di Indonesia sebagai buntut kekecewaan atas konstruksi gender dalam kehidupan keseharian di masyarakat.
Pemahaman yang sedikit banyak dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat yang menganut sistem gender biner, memarginalkan ruang gerak perempuan dalam publik.
Masyarakat membagi gender untuk menentukan apa yang dianggap sebagai keharusan, untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya, mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan, dan semacamnya seringkali dianggap sebagai kodrat perempuan. [1] Padahal, peran seperti itu merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya oleh masyarakat.
Pemahaman yang abu-abu mengenai konsep gender ini perlu diluruskan agar kelak di kemudian hari hal ini tidak menjadi pekerjaan rumah yang ditumpukkan untuk anak cucu kita.
Gender dan jenis kelamin merupakan kedua hal yang berbeda, masyarakat pada umumnya acuh tak acuh mengenai hal ini dan menganggap keduanya merupakan hal yang serupa. Bahkan kesalahpahaman ini juga mencaplok definisi gender yang ada di dalam KBBI, yakni jenis kelamin.
Jenis kelamin (sex) adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran sebagai bentuk upaya meneruskan keturunan. Sedangkan, gender adalah pembagian status dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap pantas oleh masyarakat.
Gender Biner di Indonesia
Seperti yang dikatakan di atas, Indonesia masih menganut sistem gender biner di mana segala peraturan yang mengikat segala ruang gerak seseorang diatur berdasarkan seks biologinya. Jenis kelamin yang diakui secara sah oleh negara yaitu laki-laki dan perempuan.
Berbagai kebijakan pemerintah selalu saja diatur berdasarkan laki-laki dan perempuan. Dimulai dari hal yang sederhana seperti seragam sekolah, laki-laki menggunakan celana dan perempuan menggunakan rok. Bagaimana dengan siswi yang enggan memakai rok ke sekolah? Pasti tidak dibolehkan masuk sekolah, diberi bimbingan, dan lain-lain.
Kapan gender itu bukan menjadi sebuah masalah dan gender itu menjadi sebuah masalah? Di negara yang menganut sistem gender biner, gender tidak menjadi masalah apabila terjadi kesepakatan kedua pihak antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian tugas dan kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.
Gender akan dipermasalahkan apabila adanya perbedaan perlakuan untuk akses, partisipasi, dan kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
Keberadaan 5 Gender di Suku Bugis
Jauh di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kebudayaan yang dapat dikatakan lebih maju dari kita yang hidup di perkotaan mengenai konstruksi gender, walau hal tersebut bisa dianggap menyimpang juga. Apakah semua perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat itu meresahkan? Rasanya tidak untuk kasus ini.
Suku Bugis, suku asli Sulawesi Selatan meyakini dan mengakui bahwa ada dua jenis kelamin yakni: laki-laki dan perempuan, dengan lima jenis gender yaitu: Orowane (laki-laki), Makkunrai (perempuan), Calabai (laki-laki yang menyerupai perempuan), Calalai (perempuan yang menyerupai laki-laki), dan Bissu (bukan laki-laki maupun perempuan). [2]
Suku Bugis menyadari bahwa sifat maskulin belum tentu dimiliki oleh setiap laki-laki, begitupun perempuan belum tentu memiliki sifat feminin dengan segala keharusannya.
Calabai (laki-laki yang menyerupai perempuan)
Calabai yang merupakan laki-laki secara biologis tidak serta merta dapat menukarkan dirinya menjadi seorang perempuan seutuhnya, merekapun tidak ingin menjadi seorang perempuan, akan tetapi peran dan identitas gendernya serta pakaiannya serupa dengan perempuan.
Sebagai contoh: dalam tradisi adat pernikahan Suku Bugis, sangat jarang calabai tidak dilibatkan dalam hal pengaturannya layaknya perempuan.
Calalai (perempuan yang menyerupai laki-laki)
Calalai sendiri merupakan kebalikan dari Calabai, mereka menjalankan peran sebagaimana hal-hal yang biasa dilakukan laki-laki dan mereka juga tidak segan untuk memakai pakaian laki-laki di lingkungan kerjanya.
Muncullah sebuah pertanyaan, “Bagaimana jika seorang calabai menikahi seorang calalai?” dikarenakan peran gender pada calabai dan calalai ini terbalik antara perempuan dan laki-laki.
Hal ini menjadi menarik dikarenakan pada akhirnya mereka yang dibesarkan sebagai laki-laki (calalai) dan terlahir sebagai laki-laki (orowane) diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah dan berstatus kepala rumah tangga. Serta, seseorang yang dibesarkan sebagai perempuan (calabai) dan terlahir sebagai perempuan (makkunrai) diwajibkan untuk bekerja di ranah domestik.
Bissu
Peran bissu bahkan lebih kompleks dari hal yang disebutkan di atas, selain karena mereka dianggap orang suci, mereka tidak boleh menonjolkan sifat maskulin maupun feminin.
Pada zaman dahulu, mereka dianggap sebagai perantara manusia dan dewa sekaligus para raja. Mereka sering dianggap sebagai waria, hal ini disebabkan kesalahpahaman masyarakat awam dalam memahami kebudayaan Suku Bugis.
Seperti yang dikatakan tadi, untuk menjadi seorang bissu seseorang harus memadukan semua aspek gender, mayoritas orang yang menjadi bissu terlahir dengan keadaan interseks, namun orang yang non-interseks juga dapat menjadi seorang bissu. Bissu ini sangat diistimewakan, bahkan mereka juga mempunyai pakaian mereka sendiri yang menyerupai gaun. [3]
Bissu dan empat gender Suku Bugis lainnya menjadi sebuah anomali bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat yang menganut sistem gender biner. Kembali kepada masyarakat Indonesia yang sudah merekonstruksi bahwa peran gender pada individu yaitu laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminin menjadi dasar penilaian bahwa hal di luar itu dianggap tidak “ideal” dengan harapan masyarakat.
Begitupun terjadi pada masyarakat Bugis sendiri. Meskipun dalam struktur masyarakat Bugis keberadaan lima gender tersebut sudah ada selama ribuan tahun, bukan berarti mereka bebas dari diskriminasi dan kemudian dengan otomatis diterima oleh masyarakat.
Melirik ke masa kini, konsep gender biner yang menjunjung tinggi maskulin dan feminin sebagai peran gender utama di kehidupan sehari-hari pada kenyataannya malah mendiskriminasi gender lain.
Selain kejam terhadap gender di luar sistem ini, gender biner juga berdampak buruk bagi penganutnya. Konsep patriarki, yang lahir dari sistem ini, memberi label bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua yang lemah dan harus dilindungi malah membuat kesenjangan di antara kedua gender ini. [4]
Ada perlunya kita berkaca kepada sejarah dan kebudayaan bangsa sendiri, meninggalkan sistem warisan dari zaman kolonialisme dan menjadi manusia seutuhnya.
Konstruksi gender yang diterapkan Suku Bugis mungkin tidak dapat diterapkan pada masa kini, namun konsepsi mengenai laki-laki tidak harus maskulin dan perempuan yang tidak harus feminin bisa menjadi acuan bagaimana kita harus menyikapi kemajemukan dalam hidup bermasyarakat.
Sebagian dari kita mungkin sudah sering meneriakkan perihal kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lupa bahwa yang lebih dibutuhkan dari kesetaraan itu ialah keadilan.