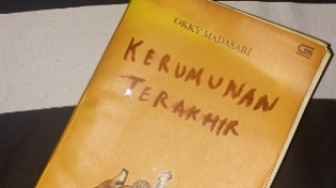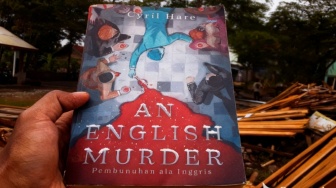Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara seringkali menggunakan penafsiran hukum. Diskursus hukum mengenal banyak sekali jenis penafsiran hukum melalui suatu interpretasi hukum. Interpretasi tersebut diantaranya: gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, futuristis, restriktif, dan ekstensif. Tulisan ini akan mengupas tiga interpretasi hukum yang setidaknya pernah atau sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.
1. Interpretasi Historis
Interpretasi Historis atau originalisme adalah metode untuk menafsirkan peraturan dengan melihat latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan tersebut. Penafsiran dilakukan dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk peraturan pada waktu pembentukannya.[1]Dapat diartikan pula bahwa penafisran ini dilakukan dengan cara memahami peraturan dalam konteks sejarah hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganut metode penafsiran ini adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan a quo merupakan putusan Pengujian Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan a quo dilakukan pembatalan terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang No.42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pemilu nasional tidak serentak atau pemilihan umum Presiden diselenggarakan setelah pemilihan umum legislatif.
MK memberikan putusan menggunakan perspektif original intent pembentukan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Rumusan tersebut ditafsirkan bahwa Pemilu yang terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD dilaksanakan secara serentak. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu, diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota”.[2] Dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilu Presiden, bahwa pemilu Presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif.[3]
2. Interpretasi Sistematis
Metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.[4] Penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative).[5] Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan metode interpretasi Sistematis/Logis terdapat dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan a quo berkaitan dengan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menarik dari putusan ini adalah cara MK dalam menafsirkan kewenangannya sendiri berkaitan dengan pengujian suatu Perppu.
Secara konstitusional, MK dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang (UU) didasari oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Jelas disebutkan yakni untuk menguji UU terhadap UUD. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah MK juga berwenang menguji Perppu yang belum mendapatkan pengesahan dari DPR? Dalam Putusan a quo, MK melakukan penafsiran dengan cara mengaitkan Pasal 22 mengenai pembentukan Perppu dengan kewenangan pembentukan sebuah UU (Pasal 20). Pertama, MK menguraikan secara rinci mengenai alasan dasar mengapa suatu Perppu itu diterbitkan. Kedua, MK menafsirkan syarat obyektif diterbitkannya suatu Perppu. Ketiga, MK menilai norma dan materi yang ada pada Perppu sebenarnya memiliki karakter yang sama dengan UU, namun harus diwadahi dalam bentuk Perppu karena terdapat beberapa alasan obyektif. Selanjutnya, MK berpandangan bahwa karena antara Perppu dengan UU memiliki karakter yang sama, maka MK juga berwenang menguji Perppu. Secara rinci sebagai berikut[6]:
“Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;”
Dengan demikian, sejatinya MK melakukan penafsiran secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan dua pasal dalam UUD NRI 1945, yakni Pasal 20 dan Pasal 22. Sehingga, pada akhirnya menemukan keterkaitan berupa kesamaan karakter materi antara kedua produk hukum tersebut.
3. Interpretasi Teleologis
Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum.[7] Dapat diartikan pula bahwa interpretasi memandang perlunya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat.[8] Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan metode ini ialah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2003 terkait Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap UUD NRI 1945. Hal yang menarik dalam Putusan a quo ialah UU SDA dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan MK menilai pasal-pasal yang dimohonkan dan dinyatakan tidak berlaku, menyangkut jantung dari materi UU SDA tersebut. Sehingga, keseluruhan muatan UU SDA dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penggunaan interpretasi teleologis atau sistematis dilakukan dalam hal menafsirkan Hak Menguasai Negara terhadap sektor sumber daya air.
Pada intinya, dalam Putusan a quo, bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan menyangkut hajat hidup orang. Oleh karena itu: (i) menjadi objek hak publik (res commune) yaitu hak yang dimiliki oleh warga negara secara bersama-sama; dan (ii) dikuasai oleh Negara. Sebagai res commune, hak guna pakai air tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak guna air memiliki dua sifat:
1. Hak in persona. Merupakan perwujudan HAM dan muncul dalam wujud Hak Guna Pakai Air
2. Hak yang timbul semata-mata karena izin yang diberikan oleh Pemerintah. Muncul dalam wujud Hak Guna Usaha Air
Hak guna pakai air harus dimaknai sebagai turunan dari hak hidup dan melejat pada tiap individu. Hak guna usaha air tidak boleh bersifat atau mengandung penguasaan dan karena itu harus diberikan lewat izin. Izin memungkinkan pemerintah mengendalikan jumlah atau volume air yang dipakai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa UU SDA masih mengandung unsur pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Konteks izin belum menjadi instrument utama dalam pengaturan ini. Dalam konteks Hak Menguasai Negara, UU SDA dan juga peraturan pelaksananya dianggap belum bisa menjawab tujuan dari penguasaan air oleh negara. Berdaasarkan pertimbangan MK tersebut, bahwa diperlukan pengaturan yang lebih baru yang mengatur penguasaan terhadap SDA dengan rezim izin. Dalam status quo saat ini, hal tersebut telah dituangkan dalam UU SDA baru, yakni UU Nomor 17 Tahun 2019. Sehingga, dalam konteks ini MK menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis.
Referensi:
[1] Ditjen PP Kemenkumham, “Penemuan Hukum oleh Hakim”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html diakses pada 19 Maret 2020.
[2] vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), Hlm. 602.
[3] Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, Hlm. 97.
[4] Sovia Hasanah, “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/ diakses pada 20 Maret 2020.
[5] Afif Khalid, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Al’ Adl, Vol. VI, No. 11, Januari-Juni 2014.
[6] Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm. 21.
[7] Jazim Hamidi, 2005, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta, UII Press 2005, hlm. 54.
[8] Loc. Cit., Ditjen PP Kemenkumham.