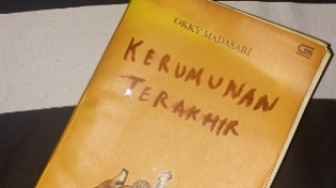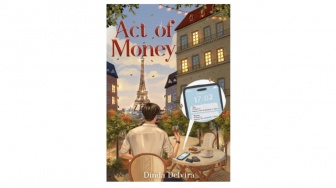Waktu awal masuk kampus, jujur saya tidak pernah berpikir tentang kekerasan seksual. Saya pikir kekerasan seksual itu ya kejadian-kejadian yang hanya terjadi di gang gelap pada malam hari. Dulu terpikir seperti itu.
Sampai tiba suatu hari. Hari itu biasa-biasa saja, saya baru ke kampus menjelang jam masuk kelas. Biasa, namanya murid teladan. Saya duduk bersama teman-teman dan menunggu dosen. Nah, ketika dosen masuk, saat itulah terasa ada yang berbeda.
Dosen saya masuk dan berdiri di depan kelas, dari cara beliau memanggil perhatian sudah aneh. Rasanya ada ketegangan di udara kelas di hari itu. Kata-kata yang keluar dari mulut dosen saya pun memecah ketegangan itu.
Salah satu teman saya ternyata menjadi korban tindakan tidak senonoh. Ya, dia kena pelecehan seksual. Saya tidak akan cerita detailnya cerita dosen saya, pokoknya modusnya berkedok penelitian. Diajak ke tempat sepi, terbayang lah kelakuan bejat pelakunya.
Momen itu membuat saya merasa seakan-akan saya keluar dari sebuah gua. Kampus yang semula tampak aman penuh mahasiswa-mahasiswa unyu kini tidak sesuci dulu. Kepolosan saya luntur.
Kampus sepertinya tidak langsung terpikir oleh orang-orang saat memikirkan kekerasan seksual. Kalau angkutan umum sih sudah biasa ya dengar beritanya. Tapi kampus? Tempat orang-orang terpelajar? Ah, rasanya tidak mungkin.
Tapi faktanya kampus merupakan tempat kekerasan seksual bisa saja terjadi. Melansir dari Kompas, sumber terbesar laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan berasal dari lingkungan kampus 27 persen.
Pelakunya pun bukan tipe-tipe preman. Menurut survei Nama Baik Kampus, pelaku terbanyak adalah sesama mahasiswa, diikuti dosen. Kurang berpendidikan bagaimana pelaku-pelaku ini?
Awalnya saya pikir "ah ini cuma satu kasus". Tapi ternyata hal ini hanya ujung dari sebuah gunung es raksasa. Kenyataannya Pusat Kajian Krisis UPI menerima 43 laporan kekerasan seksual per Januari 2021.
Itu juga hanya yang melapor. Mirisnya, hasil survei Nama Baik Kampus menemukan bahwa setengah penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kasus mereka.
Lantas kenapa orang-orang tidak melapor? Alasannya beragam, ada yang malu, takut, tidak sedikit juga yang tidak percaya bahwa laporan mereka akan memiliki dampak. Di sinilah diperlukan pengubahan sistem pelaporan di kampus, harusnya ada sebuah lembaga yang bisa mendampingi korban ketika melapor.
Laporan dari korban pun seharusnya ditindak secara cepat. Bagaimana orang mau percaya untuk melapor ketika laporan mereka jatuh di kuping batu? Ketika kampus mulai menindaklanjuti kasus kekerasan seksual secara serius, kepercayaan terhadap lembaga bisa terwujudkan.
Selain itu psikolog dapat dilibatkan dalam penanganan kasus. Tentunya setelah mendapat perlakuan tidak menyenangkan korban bisa mengalami trauma, sehingga dibutuhkan bantuan konseling untuk membantu korban.
Hal yang sama pentingnya dengan penanganan kasus adalah pencegahan. Mungkin terdengar sepele, akan tetapi dengan merancang workshop berisi penyuluhan tentang kekerasan seksual, kesadaran mengenai kekerasan seksual bisa ditingkatkan.
Pihak kampus dapat bekerja sama dengan psikolog untuk merancang workshop seperti ini. Psikolog dapat memberikan penyuluhan mengenai tindakan apa saja yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, sehingga orang-orang bisa memahami perilaku seperti apa yang harus mereka hindari.
Selain itu penting juga untuk mengajarkan langkah-langkah untuk melapor. Mungkin saja orang-orang tidak melapor karena tidak tahu caranya.
Kembali ke cerita tadi. Pada akhirnya saya mengetahui siapa pelakunya. Dia anak yang agamis, jauh dari bayangan tipikal seseorang yang bejat. Memang benar ungkapan orang inggris, sebuah buku tidak bisa dinilai hanya dari sampulnya.
Akhir kata, mungkin kampus bukanlah tempat yang aman. Kekerasan seksual memang sangat mungkin untuk terjadi di tempat manapun, termasuk kampus. Namun fakta kelam ini tidak menutup peluang untuk berusaha membuat kampus lebih aman.