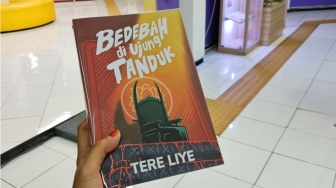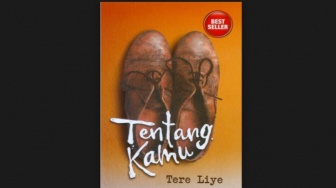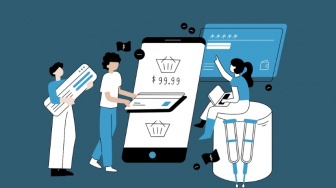Pria yang bernama Goreng itu terbangun dengan kebingungan. Ruang yang menjebaknya kini sebentuk ruang persegi dengan lubang berbentuk persegi pula di tengah-tengahnya. Di seberang, terdapat ranjang serupa dengan seorang pria yang terbaring santai.
Beberapa saat berlalu, dari lubang di atas mereka, turunlah peron persegi dengan aneka ragam makanan memenuhi permukannya. Tapi, semua itu bukan makanan baru. Mereka tengah berada di sel nomor 48 dan itu artinya, ada dua orang di 47 sel lain yang telah membabat makanan itu. Ya, sudah jelas, itu makanan sisa, tapi selagi pria bernama Goreng itu masih kebingungan, pria tua tadi langsung melahapnya dengan tergesa-gesa.
Itu adalah gambaran singkat dari pembukaan film Spanyol besutan sutradara Galder Gaztelu-Urrutia yang berjudul The Platform. Film yang dirilis tahun 2019 itu memang bukan film yang rumit dan berdurasi panjang. Kendati begitu, terlepas dari durasinya yang sekitar satu jam tiga puluh menit, ia sukses membuat saya terpaku dengan beragam adegan yang disuguhkan, sembari pikiran sibuk mencerna berbagai hal yang memancing untuk diinterpretasikan.
“Lebih baik memakan daripada dimakan,” ucap si pria tua kepada Goreng. Laki-laki itu kemudian paham dengan sistem dari sel yang bernama Lubang itu. Selain berbentuk aneh, vertikal dengan banyak lantai yang menghujam seperti sumur. Sel itu punya aturan unik: Setiap sebulan sekali, para penghuninya diacak dan dipindah ke lantai yang berbeda-beda.
Bila beruntung, mereka mendapat lantai paling atas, sehingga mereka memiliki kesempatan menikmati makanan lebih dulu dari orang-orang di bawahnya. Namun, bila kepalang sial, ia mendapat lantai di urutan bawah, sehingga peron beton itu hanya menyisakan piring dan pecahan beling saja.
Di lantai bawah itulah kebrutalan penuh darah terjadi, sebab naluri untuk bertahan hidup dikerahkan semaksimal mungkin oleh para penghuninya. Saat itu pula kata-kata yang diucapkan tokoh pria tua tadi mendapat validasinya.
Tentu, film ini bisa sangat mengganggu bagi beberapa orang. Sekian fragmen menampilkan barbarisme yang tak tanggung-tanggung, belum lagi darah yang bebas terciprat di sana-sini. Ini kemudian yang membuat genre film ini agak membingungkan: Ini film horor, sains-fiksi, thriller, atau gabungan dari ketiganya? Namun, terlepas dari kesan mengganggu dan sedikit membingungkan itu, satu hal yang pasti membuat yakin adalah fungsi film ini dimaksudkan sebagai kritik sosial atas realitas kejamnya hierarki di masyarakat.
Dari fakta bahwa makanan yang dihidangkan tampak mencukupi untuk seluruh penghuni sel, kita lantas bertanya-tanya, kenapa penghuni di lantai atas selalu membabat makanan secara rakus? Andai mereka memakannya sesuai dengan kebutuhan mereka, asumsi yang bisa dipegang adalah makanan itu bisa sampai ke lantai paling bawah. Dengan begitu, tidak ada yang sampai kelaparan dan harus memakan kertas atau memakan daging teman satu sel sendiri.
Sayangnya, itu tidak terjadi sama sekali. Anggapan yang hidup di kepala para penghuni sel itu bahkan seperti ini: Yang di bawah biarlah di bawah. Satu-satunya kepentingan yang diperhatikan adalah diri sendiri dan pastikan bahwa dirimu bisa makan sepuasnya mumpung berada di lantai dengan nomor bagus. Itulah yang mereka pikirkan. Setelah tahu pasti cara kerja sel itu, tidak ada upaya lain yang mesti dikerahkan selain upaya untuk bertahan hidup. Apa pun caranya, sekalipun itu mesti dilakukan dengan saling bunuh, bertahan hiduplah yang terpenting.
Bukankah semua itu terdengar tidak asing bagi kita? Ya, sel itu senyatanya gambaran kehidupan ini. Sementara pembagian nomor lantai itu merujuk kepada hierarki sosial yang ada di tengah-tengah kita. Perubahan dan pengacakan penghuni ruangan pun mengadopsi sistem nasib, apakah bulan depan kita beruntung, atau malah bernasib sebaliknya? Persis seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa hidup ini seperti roda pedati, kadang di bawah, kadang juga di atas.
Namun, renungan kita tidak berhenti sampai di situ saja. The Platform bukan film yang cukup dipandang sebagai gambaran atas kondisi kehidupan dengan serangkaian tafsir moral di dalamnya. Lebih dari itu, ia juga menjadikan tubuhnya sebagai sebentuk sindiran atas beragam sistem yang ada di dunia ini.
Di dunia nyata, kita bisa mendapati keadaan yang serupa benar-benar terjadi, bahkan terkadang keadaannya bisa lebih brutal dan kejam lagi. Kelaparan dan kemiskinan masih menjadi satu paket persoalan yang tak kunjung selesai ditangani dengan baik oleh negara.
Kendati kerap menafikannya, hierarki sosial sebetulnya masih hidup di tengah-tengah kita. Yang di atas dengan rakus menikmati beragam hal dari mulai uang, kedudukan, jabatan, sampai kemewahan. Sementara yang di bawah, masih bergelut dengan kelaparan dan beragam keterbatasan.
Sekalipun yang di atas peduli, toh wujud kepedulian itu tetap tidak selalu mencukupi. Lihat saja, bantuan berupa sembako yang setiap bulan diturunkan pemerintah, dalam periode tertentu jumlahnya kian menyusut. Bagaimana itu bisa terjadi? Mudah saja: Setiap cabang pemerintah yang mesti dilewati, potong bantuan itu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, bila analogikan dengan angka, dari pemerintah barang diturunkan senilai 5 buah, tapi yang sampai di masyarakat tinggal 1 buah saja.
Memang, sindiran itu tidak berlaku dalam hal pendistribusian barang makanan saja. Kita bisa juga mengaplikasikan dalam sekian hal yang ada di kehidupan kita. Semua itu pun erat kaitannya dengan ketidakadilan.
Namun, apakah semua orang mau pusing-pusing memikirkan beragam hal itu? Tidak semua orang akan peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini: Mengapa kita tidak membuat rata saja pembagian dan pendistribusian barang, karier, atau pendidikan? Mengapa harus ada perbedaan nilai, kualitas, dan mutu dalam sekian hal tadi?
Diakui atau tidak, inilah wujud terkejam dari hierarki sosial yang kita jalankan. Kita senyatanya tidak berbebas dari sisi egois diri sendiri. Sekalipun, kita mengerahkan usaha perubahan, jalannya toh tidak selalu mulus. Pada akhirnya, benar kata narator yang muncul kali pertama dalam film ini, bahwa ada tiga macam orang di dunia ini. Orang yang berada di atas, orang yang berada di bawah, dan orang yang terjatuh.
Tentu, kita tidak harus sepakat dengan anggapan itu. Katakanlah kita percaya akan perubahan, dan kita merangkak naik menuju tingkat atas. Sialnya, orang yang di atas dengan bengis menendang kita hingga jatuh tersungkur. Kita pun menjadi orang yang terjatuh. Namun, apa dengan begitu kita berhenti? Berhenti dan terpuruk di tingkat paling bawah? Tidak, saya tidak akan menjawabnya. Semua itu tergantung keyakinan diri masing-masing. Sebab bukankah kita sendirilah yang paling tahu terhadap apa yang dibutuhkan dan dicapai di dunia ini? Persoalannya, bila telah tercapai, kita memilih peduli dengan orang lain yang di bawah kita atau malah merawat ego diri sendiri? Lagi-lagi, bukan hak saya untuk menemukan jawabannya.