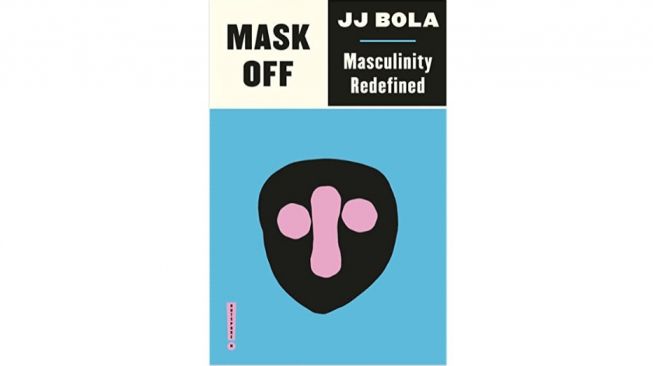Ada anggapan umum yang ada di sekitar kita terkait maskulinitas. Laki-laki, sebagai pihak yang mesti menyandang sisi maskulin, diharuskan memenuhi sejumlah norma dan standar tertentu. Kita tentu jamak mendengar ungkapan seperti laki-laki tidak boleh menangis, dituntut selalu kuat, dan sejumlah standar lain yang menekankan bahwa lelaki sejati mestilah mereka yang menyandang semua hal tersebut. Kalau kita perhatikan, menahun para lelaki diharuskan memakai topeng maskulinitas yang nilai dan norma-normanya sebenarnya, datang dari konstruksi sosial masyarakat itu sendiri. Ihwal melepaskan topeng inilah yang menjadi fokus dari JJ Bola dalam bukunya Mask Off - Masculinity Redefined (Pluto Press, 2020).
Mula-mula, Bola mengisahkan ceritanya sebagai warga pendatang di UK. Datang dari sebuah etnis di Afrika, Bola memiliki nilai budaya yang sedikit berbeda. Dalam budayanya, saat ada dua orang lelaki, baik sesama dewasa atau tidak, berjalan bergandengan tangan, pemandangan itu dianggap sesuatu yang biasa. Normal-normal saja. Namun, begitu ia mempraktikkanya di lingkungan yang berbeda, Bola justru mendapatkan pandangan kebencian dari orang di sekitarnya. Orang-orang tampak heran dengan apa yang ia lakukan.
Dari situ, Bola pun mengajukan pertanyaan, ada apa dengan keadaan tersebut? Mengapa menggandeng tangan sesama lekaki yang memiliki hubungan kekerabatan diperbolehkan di suatu budaya, sedangkan di budaya lain dipandang sebagai sesuatu yang aneh? Pertanyaan itu pulalah yang mengantarkan Bola ke pembahasan soal isu maskulinitas lainnya. Lebih jauh lagi, menurut Bola, maskulinitas laki-laki ada sebab terdapat kontruksi sosial yang menciptakannya. Kontruksi sosial itu juga yang menghadirkan sejumlah mitos-mitos seputar maskulinatas, seperti mitos “lelaki sejati” yang ada di masyarakat.
Mitos ini yang membuat kebanyakan laki-laki mengenakan topeng maskulinitas. Topeng itu yang mereka kenakan demi mendapatkan kesan sebagai lelaki sejati yang kuat, tidak cengeng, tangguh, dan sebagainya. Dan lagi, topeng ini tampak dipercayai banyak masyarakat di banyak tempat di muka bumi ini. Kepercayaan itu mengharuskan setiap laki-laki untuk menekan perasaannya, untuk tidak menunjukkan perasaaan kalau ia sedang jatuh, mengalami masa depresi, stres, yang membuatnya ingin menangis atau menceritakan semua itu pada orang lain, sebab itulah topeng yang dipaksakan pada diri mereka untuk dikenakan.
Lantas, apakah topeng itu sesuatu yang valid? Bola menyangsikannya. Bola mengajak pembacanya untuk melihat ke dalam diri kita dan sekitar kita, betapa topeng itu seperti dua sisi mata pisau yang berbeda.
Topeng maskulinitas ini tampak membuat laki-laki memiliki sejumlah keunggulan, seperti mereka bisa lebih sering diandalkan, tampak lebih logis, dan dipandang bisa mengontrol emosi atau mengesampingkan emosi di depan logika mereka. Namun, di sisi lain, ia juga mengandung paradoks bahwa topeng itu membatasi mereka untuk mengekspresikan diri secara lebih leluasa lagi. Masyarakat, khususnya masyarakat patriarki mengharuskan topeng maskulinitas itu dipakai, karena pusat atau gender utama yang memimpin adalah laki-laki. Inilah yang ingin direkonstruksi ulang oleh Bola.
Tentu, paparan Bola sedikit banyak bersinggungan dengan feminisme. Sebab, apa yang Bola suguhkan berkaitan dengan semangat feminisme itu sendiri, bahwa topeng maskulintas adalah buah dari masyarakat yang patriarki. Bahkan, dalam istilah Bola, kita dikenalkan dengan hegemoni maskulinitas, yaitu norma-norma tertentu yang ditetapkan masyarakat untuk dianut oleh para lelaki. Lantaran istilah itu mengacu pada hegemoni, atau kekuasaan yang diberikan secara halus dan luas, maka memang, kebanyakan lelaki tidak menyadari kalau mereka sedang terhegemoni oleh masyarakat di sekitarnya.
Mereka tidak sadar kalau ada nilai atau norma tertentu yang ditanamkan dalam diri mereka. Dan, dalam kasus ini, norma itu berhubungan dengan kontruksi sosial tertentu untuk menetapkan maskulintas dalam diri laki-laki sebagai hal yang sewajarnya dimiliki oleh mereka. Maka, kalau kita melihat di sekitar kita, norma yang mewujud sebagai stigma bahwa lelaki sejati tidak boleh menangis, masih dianggap menjadi kewajaran dan memang begitulah adanya.
Padahal, kalau menurut pandangan Bola, itu menjadi hal yang perlu direnungkan ulang oleh kita. Inilah pesan Bola dalam bukunya, bahwa topeng maskulinitas itu tidak semestinya dikenakan selamanya oleh kita. Lebih-lebih, kita pun mesti yakin kalau buah dari masyarakat patriarki itu bisa kita rekonstruksi ulang. Sebab, itu bukan lagi sesuatu yang valid dan relevan dengan zaman ini. Apakah itu mungkin dilakukan? Bola meyakinkan kita, bahwa masyarakat bergerak secara dinamis, dan itu artinya, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya selama setiap anggota masyarakatnya memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Begitu.