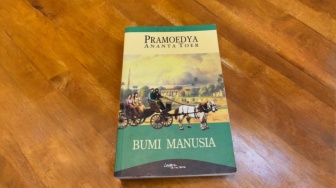Membaca novel Basirah sedikit banyak mengingatkan saya pada novel Yetti A.KA lainnya, yaitu Pirgi dan Misota. Keduanya memiliki kesamaan dengan adanya tokoh-tokoh perempuan lintas generasi, yang penuh kesedihan dan sarat beban kehidupan.
Seperti ciri khasnya Mbak Yetti dalam setiap cerpen maupun novelnya, saya pun menjumpai tokoh-tokoh bernama unik dengan karakter kuat, alur dinamis, struktur cerita yang rapi, gaya penceritaan yang absurd dengan selipan bumbu-bumbu surealisme, dan ending yang mencengangkan.
Novel Basirah sendiri bercerita tentang tiga orang perempuan dari tiga generasi, yaitu Imi, Mama Imi, dan Nenek Wu. Mereka tinggal di kota Basirah, kota kecil yang sama sekali tidak gemerlap dan dahulu ramai dengan perdagangan sampai dibangun pasar rempah-rempah. (Hal. 81) Namun, bagi Mama Imi, Basirah memiliki makna lain.
Basirah itu apa? tanya Imi.
Inti perasaan terdalam, timpal Mama. (Hal. 84)
Karakter-karakter setiap tokohnya sangat menonjol, seperti Imi, anak perempuan berusia delapan tahun, tanpa ayah, dan memiliki jalan pikiran bak orang dewasa. Saat membacanya, saya langsung teringat tokoh Suki dalam novel Jakarta Sebelum Pagi karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, yang memiliki karakter serupa.
Karakter lainnya yang menonjol adalah tokoh perempuan tak bernama yang dipanggil Imi dengan sebutan Nenek Wu. Dia seorang perempuan setengah manusia setengah hantu, berusia lebih dari seratus tahun. Nenek Wu kerap bercakap-cakap dengan hantu suami dan anak-anaknya, walau yang terdengar dari bibirnya hanyalah suara seperti wu-wu-wu.
Ada suatu peristiwa kelam yang dialami Nenek Wu di masa muda, yang membuatnya memilih membisu. Kejadian pahit yang mencabik habis segala harga dirinya sebagai perempuan dan menorehkan luka mendalam.
Aku sudah sama sekali tidak bicara. Aku ingin bicara, tapi tidak bisa. Tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku mulai mengenali lagi orang-orang di kampung kami. Namun, bila ada yang menanyaiku, apa yang sebenarnya terjadi hari itu, kepalaku langsung sakit kembali dan pikiranku menjadi kosong, tak menyisakan apa pun selain sosok adikku dengan kaki pincangnya. (Hal. 149)
Karakter berikutnya yang sama menonjolnya dengan Imi dan Nenek Wu adalah Mama Imi. Dia berprofesi sebagai pembaca kartu tarot. Tak kalah muram dengan kisah Nenek Wu, Mama Imi pun menyimpan kisah masa lalu yang pedih. Kisah yang membawanya pindah ke kota Basirah dalam keadaan hamil, dengan bantuan temannya yang kerap disapa Imi, Om Pohon.
Konflik cerita sangat beragam meskipun tak ada yang paling mendominasi. Mulai dari kematian mengenaskan Bolok, anjing milik Imi, hubungan antara Mama Imi dan Om Pohon, masa lalu kelam para tokoh, serta menghilangnya Imi, semuanya memperoleh porsi yang seimbang.
Sedikit berbeda dari buku-buku Yetti A.KA lainnya, dalam novel Basirah terbitan DIVA Press, Oktober 2018 ini, banyak sekali dialog yang sepertinya ‘disengajakan’ tak menggunakan tanda petik, terutama dalam dialog antara Imi dan mamanya.
Dalam novel ini banyak pula paragraf-paragraf teramat panjang, yang bisa mencapai satu halaman bahkan lebih. Ini sungguh di luar kelaziman.
Saya sendiri sama sekali tidak terganggu dengan adanya paragraf-paragraf panjang tersebut. Saat membacanya lebih terasa seperti storytelling, karena kehadiran paragraf-paragraf panjang tadi memang ada di bagian-bagian yang ‘berkisah’.
Namun, bagi sebagian pembaca yang terbiasa dengan paragraf-paragraf pendek, mungkin akan sulit menerima dan bisa jadi merasa lelah, dengan adanya paragraf-paragraf teramat panjang tersebut.
Mengakhiri ulasan saya kali ini, saya sangat merekomendasikan novel ini kepada siapa saja, karena kita bisa belajar banyak teknik penulisan melalui novel Basirah.
Selain itu, novel ini menyajikan banyak hal, seperti perdagangan manusia, kekerasan, penculikan, pemerkosaan, pengkhianatan, dan itu dialami oleh para tokoh perempuannya.