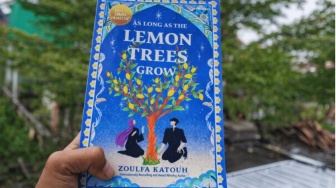Kekecewaan publik jarang datang dalam satu ledakan besar. Ia tumbuh perlahan, menumpuk dari pengalaman-pengalaman kecil yang terus berulang: janji yang menguap, hukum yang terasa pilih kasih, dan skandal yang silih berganti tanpa pernah benar-benar tuntas. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang tidak lagi memilih berteriak. Mereka memilih diam—bukan karena menerima, melainkan karena lelah.
Kelelahan itulah yang menjadi bahan bakar utama monolog Hanya Orang Gila yang Bilang Negeri Ini Baik-Baik Saja, sebuah karya teater yang diproduksi Ketika Teater Indonesia di bawah arahan Abror Y. Prabowo. Pertunjukan ini tidak hadir sebagai hiburan ringan, melainkan sebagai ruang permenungan yang mengajak penonton menengok ulang realitas yang kerap disamarkan.
Ketika Teater Indonesia merupakan komunitas seni independen yang berbasis di Yogyakarta. Komunitas ini menempatkan sastra dan teater sebagai medium refleksi sosial—sebuah keyakinan bahwa seni pertunjukan dapat berbicara ketika bahasa-bahasa resmi terasa kehilangan makna. Diprakarsai oleh Abror Y. Prabowo, Ketika Teater Indonesia tumbuh dari hasrat menjadikan panggung sebagai ruang kejujuran.
Repertoar monolog ini akan dipentaskan pada Rabu, 4 Februari 2025, di Gedung Militaire Societeit, Yogyakarta. Produksi ini merupakan hasil kolaborasi antara Ketika Teater Indonesia, Family Merdeka Production, dan UKM Teater Sentir Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kolaborasi lintas komunitas ini menegaskan bahwa kegelisahan sosial bukan milik satu generasi atau kelompok tertentu.
Dalam monolog tersebut, negara tidak digambarkan sebagai pelindung yang hadir penuh wibawa. Ia justru muncul sebagai entitas yang terasa jauh—hadir melalui kebijakan, jargon, dan citra, tetapi absen dalam kehidupan nyata warga. Para pejabat ditampilkan sibuk merawat penampilan, sementara persoalan mendasar seperti korupsi, ketimpangan hukum, dan kemiskinan struktural dibiarkan berlarut-larut.
Satire menjadi pendekatan utama naskah ini. Dengan humor yang getir dan bahasa yang sesekali puitis, monolog ini mempertanyakan apa yang selama ini dianggap wajar. Skandal tidak lagi mengejutkan, kritik dianggap gangguan, dan kejujuran sering diposisikan sebagai sikap yang berlebihan.
Dalam lanskap semacam itu, makna kewarasan mengalami pembalikan. Mereka yang bersuara kritis dicap tidak stabil, bahkan berbahaya. Sebaliknya, kepura-puraan yang tersusun rapi justru diterima sebagai bagian dari tatanan sosial. Monolog ini tidak menunjuk siapa yang benar atau salah, melainkan mengajak penonton menyusuri logika terbalik tersebut dengan kesadaran penuh.
Dari sisi artistik, pementasan ini mengandalkan kesederhanaan bentuk dan kekuatan aktor. Monolog dimainkan tanpa jarak, menciptakan suasana intim yang mempertemukan langsung aktor dengan penonton. Ritme bahasa, pengolahan suara, dan gestur menjadi elemen penting yang menjaga intensitas emosi sepanjang pertunjukan.
Abror Y. Prabowo, selaku penulis naskah dan sutradara, menjelaskan bahwa pementasan ini dirancang sebagai ruang kreatif yang memungkinkan seni berbicara jujur tanpa berubah menjadi khotbah moral.
“Pertunjukan ini lahir dari kegelisahan terhadap narasi publik yang terus memaksa kita percaya bahwa keadaan baik-baik saja,” ujar Abror. “Padahal, ada banyak luka yang tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk disembuhkan.”
Abror, yang juga telah menerbitkan buku kumpulan naskah drama Karikatur dari Negeri Retak, menegaskan bahwa istilah “orang gila” dalam judul monolog ini bersifat metaforis. Yang dipersoalkan bukan kondisi kejiwaan, melainkan bagaimana kewarasan sering dimanipulasi untuk membenarkan praktik yang merugikan kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, kegilaan justru tampil sebagai simbol perlawanan sunyi—sebuah cara untuk menolak kepatuhan buta terhadap sistem yang tidak adil. Ketika suara rasional tidak lagi didengar, ironi dan satire menjadi bahasa yang tersisa.
Pimpinan produksi, Fian Khairil Mizan, memandang pementasan ini sebagai upaya membangun ruang temu yang setara. Keterlibatan mahasiswa dan berbagai komunitas seni, menurutnya, bukan sekadar kebutuhan produksi, melainkan bagian dari proses belajar bersama.
“Teater masih relevan sebagai ruang publik alternatif,” kata Fian. “Panggung memungkinkan pertemuan antara kegelisahan kreator, energi generasi muda, dan pengalaman penonton tanpa sekat.”
Ia menambahkan bahwa pertunjukan ini tidak diniatkan berhenti sebagai tontonan. Harapannya, penonton pulang membawa pertanyaan yang terus hidup—tentang kejujuran, keberanian untuk bersikap kritis, dan tanggung jawab sosial sebagai warga.
Pada akhirnya, Hanya Orang Gila yang Bilang Negeri Ini Baik-Baik Saja tidak menawarkan pelarian dari kenyataan. Ia justru mengajak publik berkaca, meski pantulan yang muncul terasa tidak nyaman. Di ruang gelap panggung, teater menghadirkan pengakuan sederhana namun penting: bahwa keberanian mengakui luka adalah langkah awal untuk tetap waras.