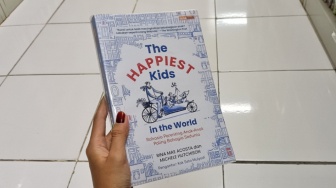Kuteringat semasa aku masih di bangku SD. Hubungankulah satu-satunya yang paling awet di antara teman-temanku. Semenjak duduk di kelas 4 hingga beranjak ke kelas 6, tak pernah sekalipun aku berpindah hati. Hatiku tetap kupautkan kepada Ema Sulistiana, yang kata teman-teman, ia gadis yang menjadi ratu bagi gadis-gadis cantik lain di SDN Garahan III Silo, Jember.
Memang kusadari, putri ibu guru agama kelas 5 dan 6 itu kecantikannya memang tak lagi diragukan. Dan tak kupungkiri, itulah salah satu alasanku tetap bertahan teguh memegang cintanya, selain ia memang taat beragama dan patuh kepada orang tua.
Jika terus kukeruk ingatan tentang awal detik-detik terbitnya cintaku semasa bau kencur itu, perut ini seakan digelitik oleh puluhan jemari. Bagaimana tidak, semula ia musuhku, tetapi lama-kelamaan justru menjelma orang yang paling kusayangi. Ia orang yang paling menjengkelkan ketika ranking 1 yang biasa kuraih jatuh ke tangannya. Paling aku benci ketika lomba gerak jalan yang aku pimpin semasa Agustusan kalah telak kepada grup yang ia komando.
Namun, setelah itu, di saat kupandangi ia dengan sepenuh kebencianku sedang tertawa berduaan bersama seorang cowok, hatiku seolah bergetar. Aku tidak hanya marah, benci, dan jengkel, tetapi rasa cemburu itu juga diam-diam bercokol dalam hati. Anehnya, semakin ia kubenci, bayangan wajahnya tak mau jauh dari pelupuk mataku.
Dengan bergulirnya sang waktu, rasa itu tercium oleh indra teman-teman cowok sekelasku. Mereka mulai mengolok-olokku. Mereka semangat sekali menjodohkanku dengannya. Pernah, ketika habis istirahat tasku hilang, saat kucari dan kutanya, tasku ternyata mereka ikat erat dengan tas milik Ema Sulistiana.
“Zi, jangan kau sangka kami yang mengikat tasmu. Tasmu sendiri yang mencari pasangannya,” kata Misrai selaku ketua kelas 4.
Masih tetap kuingat, sungguh saat itu Ema seperti kepiting rebus, mukanya langsung merah padam. Ia berusaha melepas ikatan itu sekuat tenaga. Tetapi, ia tak bisa. Lalu, minta bantuan teman-teman, namun mereka sengaja mempermainkannya. Bukan hanya tidak mau, malah menertawakannya.
Aku yang berdiri di depan tempat dudukku sebenarnya ingin sekali menghampiri Ema, kemudian melepaskan ikatan tersebut. Tetapi, aku juga mikir takut ledekan teman-teman makin membuncah.
Akhirnya, Ema menangis. Sebagian teman cowokku mendekati untuk melepas dan mengambil tasku.
Dasar anak ingusan, ketika ikatan terlepas, Ema tertawa seraya berkata, “Aku hanya akting.”
Suasana seketika menjadi gempar. Berbaur rasa sedih, jengkel, senang, dan salut. Semuanya larut jadi satu di ruang kelas saat itu.
Rupanya bukan itu saja yang mereka lakukan dalam rangka main perjodohan antara aku dan Ema. Sempat pula kulihat tulisan “Rozi dan Ema” di jalan beraspal menuju sekolah dan tembok belakang sekolah yang mereka gores dengan pecahan genting dalam bingkai sebongkah hati.
Bertambah hari, bulan demi bulan, aku yang selama ini memendam rasa dan diam-diam setuju dengan permainan ala mereka, akhirnya benar-benar menjalin hubungan asmara dengan pujaan hati: Ema Sulistiana.
Hubungan yang berjalan mulus itu beberapa tahun kemudian bernasib sial. Ema yang kuyakini akan menjadi belahan jiwa, separuh napasku, ternyata lenyap seiring musnahnya harapan yang tertanam kokoh dalam sudut hati.
Semenjak kelulusan dan aku meneruskan sekolah sekaligus tinggal di Pulau Garam Madura, tak kusangka setelah kupulang ke kampung halaman, rupanya Ema telah resmi menjadi istri Dedi, kakak kelasku yang dulu kupercayakan untuk menjaganya. Dasar, pagar makan tanaman.
Seketika belati terasa menghunjam ulu hatiku. Dendam bercampur amarah menguasai pikiran dan jiwaku. Ingin rasanya Dedi saat itu kutemui lalu menghajarnya. Tapi, segera aku tersadar, ke pulau seberang aku tak hanya mengantongi ilmu dunia, ilmu akhirat tak luput juga dari pencarianku. Aku telah paham ilmu agama. Aku begitu mengerti sesungguhnya dendam amarah adalah sifat tidak terpuji. Aku pun juga telah tahu orang menerima takdir dan tawakal akan disayang Tuhan.
Benar memang, cinta pertama tak mudah dilupakan. Aku terus berupaya membunuh rasa sayangku terhadap Ema.
Akhirnya, aku bertemu dengan seorang gadis yang sungguh dari wajah dan gerak-geriknya mirip Ema, bahkan Ema banget. Namanya Evi Wulandari. Gadis jelita itu selalu mengirim sebagian hasil kiriman dari rumahnya kepadaku. Ternyata ia tahu bahwa aku jauh dari keluarga. Ia pun juga paham kalau jauh dari keluarga, seperti biasa, tak lepas dari kekurangan.
Aku merasa diperhatikan Wulan. Lambat laun Wulan begitu dekat denganku. Sering bertukar cerita ini dan itu, dari masalah pendidikan hingga hal yang paling pribadi. Akhirnya, aku merasa cocok menaruh cinta kepada Wulan. Syukurlah, ternyata ia pun menyambut cintaku.
Namun, entahlah apa kehendak takdir kepadaku, aku sama sekali tak paham. Setiap kali aku merasa nyaman, tenteram, dan damai bersama gadis yang kurasa sangat sesuai dengan keinginanku, takdir selalu berkata lain. Di pertengahan terjalinnya hubunganku dengan Wulan, percaya atau tidak, Wulan segera diambil oleh-Nya. Ia menghadap Sang Pencipta di saat keterjalinan kami mulai beranjak serius. Ya, tapi apa boleh dikata, ini adalah semata suratan dari-Nya.
Sungguh sangat tak mudah mencari pengganti Wulan. Perjuangan berdarah-darah yang telah kutempuh. Mencari mutiara di antara tumpukan pepasir sangatlah menguras keringat. Kuakui kebenaran itu. Bertahun-tahun hidupku sepi. Jiwaku sunyi. Hati tak ada bisikan yang juga disuarakan dari kedalaman hati. Jenuh hidup ini. Bosan. Muak. Hidup segan, mati tak mau. Aku bingung sebingung-bingungnya ke mana hendak kucari tulang rusukku. Aku terus berdoa. Bermunajat di malam yang sepi dan rutin seusai menyembah-Nya.
Selang beberapa hari kemudian, doaku terjawab. Diyah, lengkapnya Zakiyatus Sa’diyah, gadis yang tak kalah ayu ketimbang Ema dan Wulan, diciptakan Tuhan untuk menerima persembahan cinta tulusku. Diyah, putri juragan tambak ikan di Pulau Madura itu sedemikian rela membuka pintu hatinya untuk kumasuki. Bukan hanya masuk, aku pun melabuhkan cintaku dalam relung hatinya. Ruang kosong hatinya ia ikhlaskan untuk kuisi dengan sepenuh cinta, kasih, dan sayangku. Lantaran kecerdasan dan keayuannya, hatiku terperangkap dalam jebakan cintanya.
Aku begitu yakin dan sangat memastikan bahwa inilah kiriman Tuhan yang sengaja digariskan untuk melengkapi bilangan tulang rusukku. Maka, segera kuangkat kaki. Dalam langkah, arahku mantap menuju rumah yang selama ini dihuni kedua orang tua dan adik laki-lakiku. Tak lupa, aku bawa beberapa lembar foto Diyah di dalam tas. Perjalanan yang agak jauh dan cukup melelahkan.
Ketika sampai di rumah, beberapa hari kemudian kuserahkan foto Diyah kepada bapakku. Kumintai pendapatnya. Kuserahkan keputusan ini kepada kedua orang tuaku.
Dan sungguh tak kusangka, jawaban yang memecahkan seisi dada itu pun terdengar dari mulut bapakku, “Adakah kau tak sadar diri, Zi? Macam apa ekonomi orang tuamu ini? Jarak sini ke Madura menghabiskan uang berapa? Harta mana yang mau dijual? Sawah mana yang mau digadaikan?”
Kemudian ibuku juga ambil bagian, “Wanita sini yang tahu agama dan pintar ngaji juga banyak. Kenapa repot sekali kau mencari jauh-jauh? Mau buang-buang harta? Iya, kalau kita berlimpahan harta. Untuk mengirimmu saja, kami harus pontang-panting.”
“Pokoknya, bapak dan ibu di sini tidak setuju kau mencari pasangan yang jauh. Jauh ekonominya, juga jauh jaraknya. Kita berkaca dengan keberadaan kita. Dan yang lebih penting lagi, ingatlah tujuanmu ke sana. Ingat pesan bapak dulu, banyak orang gagal menjadi ahli ilmu karena terhalang oleh godaan cinta. Camkan itu!” tambah bapak sekaligus menutup pembicaraan ketika itu.
Angin mendesir menyapu gerah tanah Jember. Tujuh bidadari bergerombol di bawah rindang pohon melinjo. Tepat di depan halaman Pondok Pesantren Nurul Qarnain Putri. Sesekali tawa ria mereka menyelingi lantunan nazam Alfiyah yang sedang mereka hafalkan. Terdengar jelas dibawa angin.
Sambil menenteng tempat sampah ke arah jurang di belakang pondok putri, tak sanggup kumelarang mataku melirik mereka. Tak mau aku berdusta, terus terang saja, ada satu di antara mereka yang menarik perhatianku. Santriwati yang berkerudung merah menyala bergamis merah kombinasi kotak-kotak hitam putih yang duduk menghadap ke barat. Begitu ia mendongak dengan terpejam, dengan mulut yang belum rampung melafazkan nazam, sewaktu itulah aku meliriknya.
Sungguh adegan yang sangat pas. Tanpa direkayasa. Itu detik-detik tempo kelemahanku menahan pandangan. Dan ternyata itu merupakan pemandangan terindah selama aku pindah nyantri sambil kuliah di pondok ini.
Aku menikmati keindahan tersebut. Hingga aku menyimpulkan, seandainya ini berdosa, mungkin sejajar dengan nikmat yang kurasakan. Tapi, segera kualihkan pandangan. Aku ingat kata Ustaz Abdurrahim Madura, laka al-‘ula wa ‘alaika as-tsani. Kalau tidak salah maksudnya, halal bagimu pandangan yang pertama dan haram bagimu pandangan yang kedua dan seterusnya. Sontak, kutepis nikmat yang menagih itu, kembali aku menatap tanah sembari hati beristigfar.
Sampai di kamar, kuceritakan kejadian tersebut kepada Sanusi, teman terdekatku selama tiga bulan aku berada di pondok ini. Darinya aku banyak dapat informasi. Antara lain: santri putri tadi bernama Fatna Harista, siswi Madrasah Aliyah paling berprestasi semasa angkatannya, dan yang membuat aku terhenyak, ia hafal Al-Qur’an 10 juz dan menguasai ilmu bahasa asing.
Semenjak itu, hari-hariku tidak sepi dari bayangan Rista. Pesona wajahnya senantiasa hadir dalam tiap sudut jiwa. Tak kupungkiri, bahkan saat kupejamkan mata dengan niat melenyapkan bayangannya, raut wajah indahnya makin tak kuasa kulepas.
Meski kali pertama kuedar lirikan, ternyata lirikan itu telah membekas di setiap relung sukma. Kembali terbayang wajah teduhnya. Ayu, indah, menawan di hati. Melirik satu kali, butuh waktu seribu hari untuk melupakannya. Sebab wajahnya betul-betul menenteramkan jiwa, elok, berseri-seri. Pesona yang tak pantas dinomorduakan.
Seiring bergulirnya waktu, sedikit demi sedikit hampir separuh aku berhasil membuang perasaan itu. Lantaran aku menyadarkan diri akan niat tujuanku nyantri ke pondok ini. Teringat pesan bapak ibu, takkan bisa meraih cita-cita kalau terjebak cinta. Maka akhirnya, segera kutepis hingga hilang bayangan dan perasaan tersebut.
Sekitar lima bulan setelahnya, saat hampir seluruh jamur-jamur rasa itu tercerabut beserta akarnya dari kedalaman hati, tiba-tiba secara tak terduga kembali tertancap, kokoh tertanam dalam jiwa. Seolah menyubur dan tumbuh kuat. Tampil begitu cantik, membuat mata kian terpana.
Minggu pagi yang cerah, ruang tamu pengasuh dipadati sekumpulan orang berkopiah dan berbusana rapi. Kedatangan mereka bermacam-macam kepentingan. Untuk menyerahkan putra-putrinya, hendak minta izin anaknya, bermaksud mengundang acara pengajian, dan lain sebagainya. Yang jelas banyak sekali tamu-tamu berkunjung. Abdi ndalem kewalahan. Tiga santri tidak mampu menyuguhkan minuman dan makanan kepada para tamu secara sempurna. Karena tiga abdi ndalem lainnya ditugaskan mengantarkan pupuk ke sawah dan dua yang lain disuruh ke pasar mengambil pesanan belanjaan.
“Zi, ikut aku ke ndalem. Aku mohon dibantu. Di sana banyak tamu. Kamu kan sudah selesai ngaji?” ajak Khairul salah satu abdi ndalem kiai yang berasal dari Sumberjambe.
“Iya, tunggu sebentar! Aku ganti baju,” jawabku sambil menuju lemari.
Aku masih ingat, saat itu aku mengenakan baju koko hijau lumut pemberian almarhum kakek dan sarung hitam serta kopiah hitam terbaru yang kubeli saat akhir Ramadan tahun lalu.
Kami berdua berlari-lari kecil menuju kediaman pengasuh. Benar-benar membeludak tamu kiai waktu itu. Mobil-mobil mewah terparkir di depan asrama putri. Sebagian dari mereka menemui dan mengirim putri-putrinya.
“Kamu langsung ke dapur, ngeluarin nasi! Saya yang bawa teh dan kue. Nih nampannya!” kata Khairul menyerahkan nampan motif kembang berwarna hitam dan ungu.
Tanpa banyak pikir, segera aku ke dapur ndalem. Saat itulah pertemuan kedua kali terjadi. Pertemuan yang meninggalkan bekas indah hingga detik ini. Rista, tak kusangka ia juga ada di dapur. Saat aku dengan terburu-buru mau masuk pintu dapur, Rista membawa nampan berisi teh dan semangkuk kue hendak keluar dari dapur, menjamu tamu muslimat di ruang Nyai Qamariyah. Hampir saja terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Untung Rista mengerem mendadak. Tak bisa kubayangkan apa yang terjadi jika kami sama-sama tergesa-gesa dan tak mampu menahan langkah.
Ah, tapi khayalku segera mengembara. Aku membayangkan; kami berjatuhan, lalu gelas-gelasnya berhamburan, kuenya berantakan. Aku hendak menolongnya. Membimbingnya bangkit lagi. Kedua mata kami bertumpu mesra. Senyum Rista merekah pertanda ikhlas atas perlakuanku padanya. Aku meraih gelas-gelas yang berserakan itu, tak kukira tangan Rista juga meraihnya. Giliran meraih gelas terakhir, tangan kami berebutan. Satu gelas dua tangan. Tak terasa, gelas terlepas dan tangan kami berpegangan. Erat sekali. Lembut tangannya mewakili kelembutan tingkah lakunya. Senyumnya kembali mengembang. Lama berpandangan mata, mengirim kata lewat rasa, lalu lirih kuungkap kejujuran yang telah berbulan-bulan terpendam dalam jiwa, ”Ana uhibbuki fillah, ya habibah.” Kemudian ia menanggapi, “Ana uhibbuka abadan, ya habib.” Akhirnya sama-sama bangkit. Tetap bergandengan tangan menuju kediaman kiai. Dengan keridaan hati dan restu orang tua, kami diakad menjadi sepasang kekasih; suami istri bermahar cinta dan kasih sayang.
Seandainya itu betul-betul terjadi, mungkin yang kurasa dunia milik berdua. Tak seorang pun hadir mengusik ketenangan dan kegembiraan kami. Takkan ada pihak lain yang merampas dan memisahkan kami. Sebab, kekuatan cinta telah begitu kokoh tertancap dalam ucap dan tingkah kami. Namun sayang, itu sebatas mimpi kosong. Mimpi seekor pungguk yang merindukan bulan. Mimpi yang menurutku jauh dari kenyataan.
Sekilas namun membekas. Dibalut jilbab hitam pekat, wajahnya sungguh semanis setangkup madu. Sorot mata yang teduh, bulu mata yang lentik, hidungnya yang mancung kearab-araban, dan bibirnya yang tersungging menebar pesona, tak bisa kuhindari untuk sejenak kutatap. Saat kutatap indah wajahnya, kian terus ia mengembangkan senyum termanisnya. Sungguh rangkaian diksi ini tak cukup mewakili keromantisan pertemuan yang nyata. Tak mampu dilukis dengan kata-kata. Dan tak pernah kurasakan adegan seromantis ini sebelumnya.
Saat tengah malam menjelang, ketika para santri beralas sajadah terbang ke alam mimpi, di saat tiada suara apa pun selain detak jarum jam dan binatang malam, aku terus dihalau bayang indah wajah Rista. Selalu teringat. Sulit dilupakan. Hingga terkadang dibawa mimpi. Efek buruknya, benar-benar tidak konsentrasi terhadap mata kuliah. Di kala malam, sulit terpejam. Saat pagi, susah sarapan. Siang, lupa nyuci. Ngaji tak konsentrasi.
Walhasil, aktivitas terbengkalai. Yang tak pernah absen hanya meluangkan waktu mengabadikan perasaan terhadap Rista di lembaran catatan harian. Karena menulis dengan ditemani bayangan wajah cantik Rista merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Seakan hari-hariku menjadi senang tak kepalang. Hati tetap bersinar meski cuaca sedang mendung. Sejauh mata memandang seolah beribu-ribu jenis bunga indah sedang bertaburan. Itu yang kurasakan meski kegiatan rutinitasku tertinggal.
Di malam yang lain, saat suasana sunyi. Terkadang aku merasa bodoh. Mengutuk diri orang terbodoh sedunia. Hatiku tiba-tiba menggurui pikiran. Seolah ia berbisik: kamu bodoh, Zi! Lantaran cinta kau menjadi lupa segala. Lupa makan, lupa belajar, lupa zikir, lupa nyuci dan semacamnya. Kau telah dikuasai hawa nafsu. Kau selalu ingat dan memikirkan Rista, padahal belum tentu Rista juga ingat dan memikirkanmu.
Bukankah selama ini kau telah lupa kepada Tuhan yang menciptakanmu, sehingga tiada waktu demi baca Al-Qur’an dan zikir? Bukankah kau sudah tidak ingat lagi kepada cita-cita kedua orang tuamu agar kau menjadi anak saleh yang alim ilmu? Jika demikian, kau celaka! Kau terbuai dalam cinta terhadap Rista. Padahal selama ini, sebab cinta kepada Allah dan cinta kepada orang tuamu, kau tak semabuk ini. Allah yang menciptakanmu. Orang tua yang melahirkanmu. Tapi, kau tak hiraukan mereka. Kau lebih memilih nikmat sesaat dan sengsara selamanya. Kembalilah ke jalan yang lurus! Tobatlah sebelum terlambat!
Jujur, sumpah demi Tuhan, perasaan seperti itu kerap kali menyusup dalam pikiran. Tak kupungkiri, ini betul-betul terjadi. Entah bisikan malaikat, atau hati kecilku yang bicara. Entahlah!
Selepas itu, aku berulang-ulang, bahkan jatuh bangun menata tekad untuk menghapus nama Rista dari ingatan. Membuang bayangan wajahnya dari pikiran. Tapi, sungguh tidak bisa. Aku bukan diam. Aku sudah berusaha, namun tak bisa. Kembali perasaan itu muncul saat Rista duduk di kelas XII dan menjalani ujian praktik. Dia minta tolong padaku lewat perantara Khairul untuk membuatkan cerpen bahasa Indonesia, sebagaimana yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran tersebut.
“Tema tentang apa, Rul?” tanyaku pada Khairul di serambi masjid usai salat jemaah Isya.
“Terserah kamu, katanya. Yang penting dibuatkan. Disuruh bikin yang bagus. Kalau bisa setting-nya di pondok ini, biar ketahuan kalau itu karangan asli siswi sini, bukan hasil plagiat,” jawab Khairul setengah berbisik, khawatir ketahuan santri lain.
“Eh ya, kenapa kok dia tidak buat sendiri? Katanya siswi teladan?” tanyaku lagi sambil mengedar pandangan mencari sepasang sandal.
Sebenarnya basa-basi aku tanya demikian. Jujur, aku tidak keberatan menerima permintaan tolong darinya. Hitung-hitung, cari perhatian ke dia.
“Ia sibuk, banyak sekali yang harus dikerjakan. Pidato bahasa Arabnya belum lancar. Artikel bahasa Inggris belum buat. Makanya, untuk yang satu ini ia percayakan padamu. Asal kamu tahu, si cantik itu mengagumi karya-karyamu,” imbuhnya. Spontan, telinga seolah melebar dan kepala bertambah besar.
Aku tidak mau menutup-nutupi kenakalanku waktu itu. Dan aku yakin, kenakalanku saat ini adalah kenakalan yang terakhir kali. Setelah ini aku mau betul-betul bertobat dan bertekad melepas diri sebagai budak hawa nafsu.
Ditemani cahaya lampu ruang kelas Madrasah Aliyah putra, kupasang penuh kekonsentrasian dalam otak. Telah tertulis beberapa halaman cerpen yang kubuat. Sebelum menyudahi, aku baca kembali. Cerpen tersebut berjudul Jodoh Takkan Ke Mana. Isinya tentang pertemuanku dengan Rista. Tokoh utamanya bernama Rama dan Sinta. Dari cerpen ini sedikit telah kusentil bahwa Rama sebagai wakil diriku yang sudah sejak lama menaruh hati kepada Sinta. Aku yakin jika Rista baca cerpen garapanku tersebut pasti mafhum kepada isi tersirat di balik kisahnya.
Hujan deras menghiasi bumi Pesantren Nurul Qarnain.
Bapak dan ibuku datang mengirim saat hujan belum begitu reda. Sebagaimana biasa mereka tanya kesehatan, sisa uang, perkembangan kuliah, dan tak lupa bertanya soal ibadah. Ketika hendak pulang, entah kenapa, mulutku begitu berani bertanya dengan nada agak memerintah kepada mereka.
“Tidak mau ngirim calon menantu bapak?” tanyaku. Sungguh seakan mulut ini ada yang menggerakkan. Tak pernah aku berpikir untuk melakukan hal ini.
Bapak ibuku serta-merta kaget. Bapak menatapku seolah menyemburatkan amarah. Hatiku bergetar. Degup jantungku kian keras. Aku khawatir terkena damprat.
“Memangnya sudah ada santri sini yang cocok?” bapakku balik tanya. Hatiku tiba-tiba tenang. Ternyata bapak tidak marah. Tidak sama dengan tahun-tahun lalu.
“Insyaallah ada, Pak.”
“Jangan keburu. Istikharah dulu! Minta petunjuk kepada Allah. Libatkan Allah dalam tiap urusanmu, biar diberi kemudahan.”
“Benar-benar sudah cocok, Zi?” kali ini ibuku yang bertanya. Setelah kuanggukkan kepala tiga kali, ibuku meneruskan, “Kalau memang demikian, bapak sama ibu mau tahu siapa namanya. Bapak dan ibu biar bisa bantu istikharah.”
Langsung saja nama Fatna Harista kutuliskan di atas kertas dengan tulisan Arab, sebab kedua orang tuaku lebih mengerti tulisan Arab. Setelah kuserahkan kepada ibu, keduanya lalu pamit pulang.
Keesokan harinya bapakku menelepon ke kantor pesantren. Beliau bercerita, sepulangnya dari pondok kemarin beliau sempat ke rumah nenek di Sumberjambe, dan untuk ke Garahan beliau memilih jalur timur. Hujan cukup deras. Karena terjebak hujan, akhirnya beliau berteduh di depan rumah salah satu warga Desa Ledokombo. Yang punya rumah kemudian menyuruh beliau dan ibu untuk masuk ke ruang tamu. Sebab hujan deras berlangsung lama, bapak tidak bisa menolak tawaran pemilik rumah tersebut.
Saat berbincang, pemilik rumah tanya ke bapak dari mana, hendak ke mana. Bapak menjawab bahwa baru saja mengirim putranya di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan hendak pulang ke Garahan. Pemilik rumah itu juga bercerita tentang putrinya yang juga nyantri di pondok tersebut.
Setelah bercerita, sontak bapak dan ibuku takjub setelah tahu ternyata nama putri pemilik rumah tersebut adalah Fatna Harista. Di akhir cerita bapak di pesawat telepon, beliau sangat setuju untuk diteruskan. Selain karena beliau sudah tahu sendiri kedua orang tua Rista, beliau juga mengungkapkan hasil istikharahnya semalam yang mengisyaratkan sangat baik untuk dilanjutkan. Tak lupa beliau berkisah pula, ibuku sempat terpana dikala melihat foto besar Rista yang terpajang di ruang tamu.
Seketika itu, hatiku sangat gembira tiada terbilang. Senang tak berujung. Serasa mimpi tapi nyata. Mungkin inilah isyarat istikharahku tadi malam yang kemudian mimpi berhasil menangkap ikan hias berwarna indah di air yang sangat jernih. Aku langsung sujud syukur sehabis menutup telepon. Lalu ke kamar menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman terdekat.
Tujuh hari dari itu, orang tuaku betul-betul melamar Rista. Disambut baik oleh keluarga besarnya. Sangat ramah memberi penghormatan terhadap keluargaku.
Dan, adalah Rista yang begitu senang memakai cincin pertunangan itu. Rona kebahagiaan yang terpancar dari raut wajahnya pun tak bisa disembunyikan.