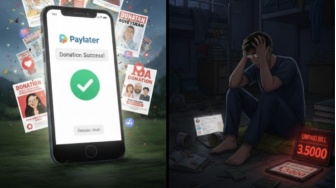"Apa kamu akan meleleh kalau hujan menimpamu?"
Orang yang berdiri di samping Kania menoleh dengan wajah melongo. Mungkin karena kalimat itu terdengar janggal, jadi Kania mengulang kembali pertanyaannya.
"Apakah hujan bisa melunturkan cat di seluruh tubuhmu?" Jemari Kania menunjuk ke arah badan si pemuda yang masih menatapnya.
"Oh... ini."
Lelaki itu tersenyum kecil. Menunduk, menatap dadanya yang telanjang sambil kemudian mengangkat tangan kanannya yang keperakan.
Sebenarnya, seluruh tubuh lelaki itu keperakan hingga ke sela-sela rambut yang berpotongan crew cut. Yah, hampir semua. Kania toh tidak tahu, apakah pemuda itu juga mengecat bagian tubuh di balik celana pendek hitam yang dikenakannya.
"Pastinya bisa, Kak. Ini, kan, cuma cat sablon yang dicampur minyak goreng. Nih, yang di kaki sudah ada yang ilang-ilang kena percikan hujan pas nyebrang kemari."
Kania manggut-manggut sambil melirik tungkai kurus berwarna keperakan yang ditunjukkan pemuda itu. Jika diperhatikan lebih jelas, Kania memperkirakan usia lelaki itu masih belasan tahun. Mungkin tujuh belas, seusia adiknya.
"Nanti kalau mau mandi tinggal pakai sunlight. Cuma itu doang juga bersih,” lanjut lelaki itu.
"Buat mandi?" Kania membelalak sambil menaikkan alis hitam lebatnya. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum tipis.
"Kalau catnya? Mahal?"
"Lumayan. Seratus ribu lebih. Tapi kan, bisa untuk seminggu. Kecuali beli patungan, sekali pakai untuk lima orang langsung habis.”
Kania membulatkan mulutnya. Ia memang sering melihat para manusia silver berkerumun di sebuah taman yang sering dilewatinya. Mungkin untuk melepas lelah setelah bekerja di bawah terik matahari.
"Kamu kerja berapa jam sehari? Kalau pakai cat begitu ada efek sampingnya nggak, sih?” tanya Kania lagi.
"Kalau saya biasanya baru keluar jam tiga sore, nanti balik ke kosan jam sepuluh malam. Bisa juga kayak sekarang, saya keluar jam sebelas siang terus pulangnya abis Isya. Soal efek samping, ya pasti ada, Kak. Itu kan bahan kimia. Kulit saya juga sensitif jadi gampang iritasi. Kayak gini, Kak."
Pemuda itu mengangkat tangan kirinya. Kania bisa melihat bentol-bentol kecil, beruntusan, yang mungkin akan terlihat kemerahan andai saja tidak tertutupi oleh cat silver.
"Terus diobati apa?" Kania penasaran.
"Nggak diapa-apain, Kak. Pernah dulu diobatin pakai minyak zaitun. Tapi, harganya lumayan. Pas udah abis nggak beli lagi. Sayang uangnya."
Lelaki itu sudah menarik kembali tangannya. Matanya kembali menatap hujan yang terus runtuh seakan tak sudah-sudah. Mereka berdiri dalam diam cukup lama, sampai pemuda itu kemudian memutar tubuhnya ke arah Kania sambil mengulurkan tangan.
"Eh, iya. Kenalan dulu, Kak. Nama saya Rama. Kakak siapa?"
Kania melirik telapak tangan si pemuda yang menggantung di udara, lalu ia membalas dengan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sambil mengulas senyum, "Kania."
Rama menarik kembali tangannya. Kikuk.
"Itu vespa Kakak?" tanya Rama.
Rama bertanya tiba-tiba. Sepertinya dalam usaha untuk melenturkan kekikukan atas insiden salaman tadi. Ia menunjuk dengan dagunya ke vespa biru pudar dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian, yang di parkir di depan toko tempat mereka berteduh.
"Bukan. Punya bapak saya. Saya pinjam karena motor saya masih di bengkel,” jelas Kania.
“Vespanya tahun lama ya, Kak? Kelihatan klasik.”
"Tua, iya. Klasik, enggaklah. Antik lebih tepat." Kania tersenyum tipis.
"Tapi pasti masih mahal kalau dijual, Kak," sahut Rama.
"Kata bapak saya, pernah ada temannya nawar vespa itu seharga sepuluh juta."
"Wah, lumayan tuh, Kak. Tapi ditolak, ya?" Mengingat vespa tua itu masih dikendarai Kania, Rama langsung berpikir demikian.
"Iya, sama Bapak ditolak. Sebenarnya ada tiga sampai empat orang pernah menawar motor itu, tapi Bapak merasa nilai kenangannya lebih besar dari uang sebanyak apa pun," balas Kania.
Rama menerawang. Tiba-tiba teringat tukang martabak depan kosannya yang pernah cerita vespa bapaknya—dengan keluaran tahun yang lebih tua dan kondisi yang lebih bagus dan terawat dari milik Kania—ditawar dua puluh juta, tapi tidak dilepas karena nilai kenangan itu tadi. Sama seperti yang dituturkan Kania tentang bapaknya.
"Motor vespa ini dulu dipakai bapak antar jemput anak-anaknya sekolah. Saya waktu itu masih kelas satu SD," lanjut Kania. Menyentakkan pikiran Rama untuk kembali fokus pada perempuan berjilbab ungu muda di sebelahnya.
"Dulu setiap kali antar kami, motor ini bisa muat enam orang," sambung Kania.
"Ah, yang benar, Kak?"
"Iya, serius. Jadi saya di depan berdua adik. Sebenarnya dia belum sekolah, tapi suka pengen ikut Bapak antar kakak-kakaknya sekolah." Kania memutar matanya jenaka membuat Rama tertawa kecil.
"Lalu Bapak dan kakak laki-laki saya di jok depan. Di belakangnya dua kakak perempuan saya."
"Wahh, vespazilla," cetus Rama.
"Apa?" Kania menelengkan kepala. Beberapa kerutan tampak di keningnya.
"Vespazilla. Besar. Muat banyak. Kayak Godzilla di film itu loh, Kak." Rama nyengir, memperlihatkan deretan gigi kekuningan.
"Oh... iya ya." Kania ikut tertawa. Ingat pada keponakannya yang belum lama melahirkan bayi seberat empat kilo lebih dan ia menyebut bayi itu, babyzilla."
"Pernah mogok nggak vespanya?" tanya Rama lagi.
"Bukan pernah lagi. Seriing...!"
Mereka berdua tertawa tergelak-gelak. Untuk dua orang yang belum lama berkenalan, mereka tampak bagai orang yang sudah saling mengenal bertahun-tahun. Begitu lepas. Begitu santai. Sampai lupa pada kekikukan dan kekakuan yang muncul di awal-awal percakapan.
"Rama ...." Kania menyebut nama lelaki itu ragu-ragu setelah tawanya usai. "Kamu sudah pernah cek ke dokter perihal gatal kamu itu?"
"Belum pernah, Kak. Biar ajalah, Kak. Risiko pekerjaan. Cuma saya juga nggak tahu sih, cat sablon atau sunlight yang bikin kulit saya iritasi," jawab Rama.
"Bisa jadi dua-duanya."
"Mungkin, Kak."
Keduanya kembali terdiam. Kembali menekuri hujan yang telah reda. Kania melirik Rama yang mendongakkan kepalanya ke langit, seakan memastikan bahwa hujan memang sudah benar-benar berhenti.
"Mulai kerja lagi?" tanya Kania.
Rama mengangguk kecil. "Iya, Kak. Kakak juga pulang, kan? Hujannya sudah berhenti."
"Iya," sahut Kania pelan.
"Makasih ngobrol-ngobrolnya ya, Kak. Sampai ketemu lagi."
Kali ini Rama tidak mengulurkan tangan. Sebagai perpisahan ia menangkupkan telapak tangannya di depan dada seperti yang tadi dilakukan Kania. Perempuan itu melakukan hal yang sama.
Rama berlari-lari kecil menuju perempatan. Lampu merah menyala. Kendaraan-kendaraan bermotor yang berlalu lalang sudah menghentikan laju kendaraan mereka. Nanti saat lampu berubah menjadi hijau itulah saatnya Rama beraksi.
Kania menuju ke vespa tua. Ia mengengkol kick stater beberapa kali sebelum akhirnya suara khas vespa berderam. Langit masih sedikit kelabu ketika vespa tua itu melaju.