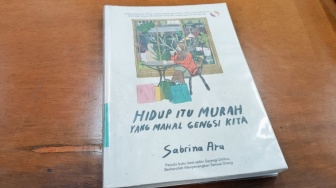Aku anak bungsu. Itu status yang di atas kertas terdengar manja, tapi di dapur keluarga kami artinya sederhana. Mengalah.
Aku tidak tahu darimana asal muasal bungsu diartikan atau identik dengan kata "manja". Karena kenyataan di kehidupanku justru sangat berkebalikan. Padahal bungsu juga kerap diartikan anak buntut. Ekor.
Dikira sudah selesai, eh ternyata masih ada yang ngikut di belakang. Dan sebenarnya mungkin definisi ini lebih cocok. Anak yang mungkin sebenarnya tak pernah diharapkan atau dinantikan.
Sejak kecil aku hafal bunyi sendok beradu piring seperti hafal doa makan. Bukan karena lapar, tapi karena tegang.
Lauk selalu sedikit, orangnya banyak, dan aturan tak tertulisnya jelas: yang paling kecil harus paling paham keadaan. Kakak butuh ini, kakak suka itu, kakak capek. Aku? Aku bisa nanti. Atau besok. Atau ya sudah.
“Ambil tempe satu aja,” kata ibuku suatu siang, sambil menggeser ayam goreng ke arah kakakku.
Aku mengangguk. Mengangguk itu keahlianku. Tempe satu aku kunyah pelan-pelan, seolah kalau kunyahnya pelan, rasanya bisa bertambah. Padahal tidak. Tempe tetap tempe. Tapi mengunyah pelan memberi ilusi: seolah aku sedang memilih, bukan menerima sisa.
Lucunya, sampai sekarang orang tuaku tidak tahu makanan kesukaanku apa.
“Kesukaan kamu apa sih?” tanya ibuku suatu kali, bertahun-tahun kemudian, di usia yang seharusnya sudah mapan untuk tahu diri sendiri.
Aku terdiam. Bukan karena tak mau menjawab, tapi karena benar-benar kosong. Seperti rak supermarket yang habis diserbu sebelum aku datang. Aku mau bilang apa? Ayam? Ikan? Sambal? Semua pernah kumakan, tapi tak pernah kupilih.
Yang benar adalah: aku tidak pernah diberi kesempatan untuk punya kesukaan.
Karena yang mengurusku sejak kecil bukan sepenuhnya orang tua, tapi kakak perempuanku. Kakak yang juga anak perempuan. Kakak yang sama-sama sering dipaksa mengalah. Bedanya, dia lebih dulu. Lebih lama. Lebih lelah.
“Udah, kamu aja yang makan,” katanya sering, sambil mendorong piring ke arahku, padahal aku tahu dia juga lapar.
Kami tumbuh dengan solidaritas sunyi. Dua anak perempuan di dapur yang sama, sama-sama belajar mengalah, tapi diam-diam saling menjaga. Kami tak pernah berantem soal lauk. Yang ada hanya saling tatap dan senyum kecil yang artinya: aku ngerti.
Waktu berlalu. Aku kuliah. Jauh dari dapur itu. Jauh dari piring-piring yang harus dibagi rata dengan rasa bersalah. Di kota baru, aku belajar hal yang revolusioner: memilih makanan sendiri.
Dan aku nekat nyambi kerja.
Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk satu hal penting: aku bisa beli apa pun yang aku mau.
Hari pertama gajian, aku tidak beli baju. Tidak beli sepatu. Aku masuk minimarket dan berdiri lama di depan rak makanan seperti orang baru keluar dari penjara rasa. Ada ayam crispy, ada beef burger, ada es krim rasa aneh-aneh yang dulu kupikir hanya mitos.
Aku ambil satu. Lalu dua. Lalu berhenti.
Aku ketawa sendiri.
“Pelan-pelan,” kataku ke diri sendiri. “Kamu aman sekarang.”
Di kosanku yang sempit, aku makan sendirian. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang perlu dikalahkan. Tidak ada suara, “Bagi kakak ya.” Hanya aku, makanan, dan rasa asing yang tiba-tiba muncul: senang tanpa rasa bersalah.
Ternyata begitu rasanya.
Sejak itu, aku jadi orang yang sedikit lebay soal makan. Kalau mau ayam, aku beli ayam. Kalau mau sambal, aku tambah sambal. Kalau mau dua lauk, ya dua. Dunia tidak runtuh. Langit tidak marah. Tidak ada yang kelaparan karenaku.
Yang ada justru aku mulai mengenal diriku sendiri.
Aku mulai tahu: aku suka pedas. Aku suka asin-manis. Aku tidak terlalu suka makanan yang hambar, mungkin karena seumur hidup rasaku dituntut netral. Aku suka makan dengan tenang, tanpa harus cepat-cepat supaya kebagian.
Suatu kali pulang ke rumah, ibuku masak seperti biasa. Ayam lagi. Tempe lagi. Piring dibagi seperti dulu. Refleks tanganku hampir mengambil tempe, tapi berhenti di udara.
Aku tersenyum, agak gugup.
“Bu,” kataku pelan, “aku mau ayam ya.”
Ibuku menoleh. Sedikit kaget. Lalu mengangguk.
“Oh ya? Ya ambil aja.”
Sesederhana itu.
Aku hampir nangis karena kalimat yang begitu ringan.
Di meja makan, kakakku menatapku dan tersenyum. Senyum yang penuh arti. Seolah berkata: akhirnya.
Aku sadar, menjadi anak bungsu yang selalu mengalah bukan cuma soal lauk. Itu soal kebiasaan mengecilkan diri. Soal belajar merasa cukup dengan sisa. Soal takut merepotkan.
Dan bekerja sambil kuliah, membeli makanan dengan uang sendiri, itu bukan soal gaya hidup. Itu proses belajar mengatakan: aku juga boleh.
Sekarang, kalau ada yang bertanya makanan kesukaanku apa, aku bisa menjawab. Dengan yakin. Dengan tawa kecil.
“Banyak,” kataku.
“Tergantung hari. Tergantung mood. Dan itu hak aku.”
Anak bungsu yang dulu hanya tahu mengangguk, kini belajar memilih. Di dapur, di hidup, dan di piringnya sendiri.
Kini aku punya sepotong cinta yang baru. Untuk diriku.