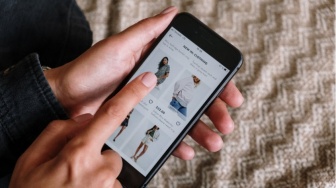Pukul tiga sakit, dan kepalaku rasanya ingin pecah. Menjadi terapis dengan kemampuan "mendengar" pikiran adalah kutukan yang dibungkus dengan ijazah kedokteran. Bagiku, setiap orang adalah radio yang rusak, mereka berbicara tentang cuaca, tapi di kepalanya, mereka berteriak tentang ketakutan akan kematian atau kegagalan. Aku mendengar semua itu. Aku menerjemahkan bahasa hening mereka menjadi solusi klinis.
Namun, sayangnya, radio itu mati total.
Di depanku duduk seorang pria bernama Elias. Usianya sekitar tiga puluh tahun, berpakaian rapi, mata yang tidak kosong, tapi juga tidak berisi. Hanya saja... ada. Masalahnya bukan pada apa yang ia katakan—karena ia belum mengucapkan kata pun sejak masuk, tapi pada apa yang tidak kudengar dari kepalanya.
Biasanya, saat seseorang diam, pikiran mereka riuh. "Apakah dokter ini bisa membantuku?" atau "Aku benci bau ruangan ini." Tapi dari Elias? Tidak ada gema. Tidak ada bisikan batin. Tidak ada warna emosi. Hanya ada keheningan yang begitu pekat, begitu absolut, hingga telingaku berdenging seolah-olah aku sedang berdiri di ruang hampa udara di luar angkasa.
"Elias," aku memulai, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. "Istrimu membawamu ke sini karena kau berhenti bicara selama satu bulan. Dia bilang kau berfungsi normal, kau bekerja, kau makan, tapi kau seperti... kehilangan dirimu."
Elias hanya melihat. Tangannya tertumpu tenang di pangkuannya. Tidak ada kecemasan di sana. Tidak ada ketegangan otot.
Aku mencoba menyelam lebih dalam. Aku memejamkan mata, memfokuskan seluruh indra keenamku untuk menangkap getaran neuron di otaknya. Biasanya, aku bisa melihat kilasan memori atau mendengar penggalan kalimat. Namun, yang kutemukan justru membuatku merinding. Di dalam kepala Elias, tidak ada suara batin. Ia tidak memiliki "narator" di dalam kepalanya.
Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa yang seluruh bukunya memiliki halaman putih bersih. Itulah Elias.
"Apa yang kau pikirkan saat ini, Elias?" tanyaku, kali ini dengan nada yang sedikit mendesak. Aku mulai merasa terancam oleh kekurangan ini.
Elias akhirnya membuka mulut. Suaranya datar, tanpa intonasi. "Saya tidak berpikir, Dok. Saya hanya melihat."
"Melihat apa?"
"Melihat Anda sedang berusaha mencari sesuatu yang tidak ada."
Jantungku berpacu. Kalimat itu bukan sekedar observasi, itu adalah serangan balik yang presisi. Bagaimana mungkin seseorang tanpa suara batin bisa melakukan analisis setajam itu? Aku kembali mencoba "mendengarkan". Tetap saja, hening yang mematikan. Aku mulai berkeringat. Sebagai terapis yang mengandalkan intuisi metafisika, Elias adalah anomali yang menghancurkan seluruh logikaku.
"Setiap manusia punya percakapan batin, Elias. Itulah yang membuat kita manusia. Itu adalah moral kita, memori kita, jati diri kita," kataku, berusaha tetap profesional meski menerima rasa gemetar di bawah meja.
Elias menutup kepalanya sedikit. "Apakah suara di kepalamu itu benar-benar dirimu sendiri, Dok? Ataukah itu hanya kaset yang direkam oleh orang tuamu, lingkunganmu, dan ketakutanmu? Jika suara itu diam, apakah aku berhenti menjadi manusia?"
Pertanyaannya menghantamku seperti godam. Aku membayangkannya. Selama ini aku menganggap gangguan di kepala pasienku sebagai identitas mereka. Tapi bagaimana jika identitas yang sebenarnya berada di balik gangguan itu? Di dalam keheningan yang ditampilkan Elias?
Tiba-tiba, suasana ruangan berubah mencekam. Lampu di atas kami berkedip sekali. Aku merasakan keheningan dari kepala Elias mulai merembet keluar, memenuhi ruangan seperti gas yang tak terlihat. Suara detak jam dinding yang biasanya jelas, perlahan memudar. Suara bising kendaraan di luar sana hilang.
Aku mencoba memikirkan sesuatu, apa saja—pasienku berikutnya, makan malamku, teoriku—tapi kepalaku tiba-tiba terasa berat. Suara batinku sendiri, narator yang telah menemaniku selama tiga puluh lima tahun, perlahan mengecil. Sayup... dan kemudian hilang.
Aku panik. Aku mencoba berteriak di dalam hatiku sendiri, tapi tidak ada gema. Aku seperti orang tuli di dalam pikiranku sendiri.
Elias, apa yang kamu lakukan? tanyaku dengan suara yang kini gemetar hebat.
Elias bangkit dari kursinya. Ia melangkah mendekat, membungkuk hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Matanya yang datar kini tampak seperti lubang hitam yang siap menelan apa saja.
“Selamat datang di dunia yang jujur, Dok,” bisiknya. "Tanpa suara-suara itu. Sekarang, katakan padaku... jika kamu tidak bisa mendengar pikiranmu sendiri, siapakah kamu sebenarnya?"
Aku tergagap. Oksigen terasa ada, tapi kesadaranku seolah menguap. Aku menatap cermin di belakang Elias, dan untuk sesaat, aku merasa tidak mengenali pria yang ada di sana. Ruangan itu kini benar-benar senyap. Bukan senyap karena tidak ada suara, tapi senyap karena makna telah tercabut dari segalanya.
Elias berjalan menuju pintu. Ia membukanya, menoleh sekilas, dan memberikan senyuman kecil, senyum pertama yang kulihat, namun itu adalah senyuman yang paling mengerikan.
"Sesi selesai," ucapnya.
Elias keluar, menutup pintu dengan lembut. Aku duduk kaku di kursiku. Aku mencoba memanggil nama ibuku di dalam kepala, mencoba menyanyikan lagu masa kecil, mencoba memaki... tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada tirai yang putih, bersih, dan dingin.
Lalu, sebuah pemikiran—atau bukan, sebuah kesadaran muncul tanpa kata-kata.
Pintu ruanganku terbuka lagi. Perawatku masuk membawa catatan medis. Ia berbicara kepadaku, memberi isyarat kepadaku, tetapi aku tidak mendengar suara batin yang biasanya mengiringi pembicaraannya. Aku melihat ke arah perawat itu, lalu ke arah itu.
Keheningan itu tidak pergi. Ia menetap.
Apakah Elias yang sakit, atau dialah yang baru saja menyembuhkanku dari "penyakit" yang disebut pikiran? Dan yang lebih menakutkan... jika keheningan ini tidak kunjung hilang, apakah aku masih orang yang sama saat aku bangun besok pagi? Ataukah "aku" yang lama sudah mati bersama suara-suara itu?
Aku menatap pintu yang tertutup, menunggu suara batin itu kembali, namun yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri yang semakin menjauh.
Seringkali kita terlalu terjebak dalam "suara-suara" di kepala kita (opini orang lain, ekspektasi, ketakutan masa lalu) hingga kita lupa siapa diri kita sebenarnya dalam kenyamanan. Namun, mampukah manusia menghadapi jati diri mereka yang murni tanpa narasi yang mereka ciptakan sendiri?