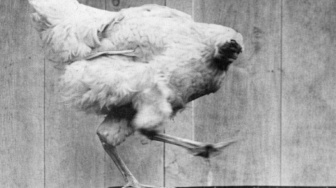Galih baru sadar mereka selalu duduk di bangku yang sama sejak kecil ketika dia melihat bekas ukiran di meja kelas lantai teratas. Hurufnya sudah pudar, digerogoti coretan lain, tetapi masih bisa dibaca jika didekati: Ga–Je.
Di dekatnya, Jeni berdiri membelakanginya di depan kaca jendela kelas. Rambut keritingnya mengembang, helai-helai di pelipis masih lembap oleh keringat. Dari balik kaca, bangunan-bangunan di distrik luar tampak pucat, seperti kelelahan di bawah matahari siang. Di kejauhan, Bukit Wadasgeni menjulang, kokoh dan diam, menyerupai punggung macan kumbang yang tidur.
“Ndak ada yang sempurna, Galih,” kata Jeni tanpa menoleh.
Galih mengangguk. Tangannya meremas uang kertas di saku celana berniat mentraktir. “Mau bakso?” katanya akhirnya. “Tenang wae, diriku yang bayar.”
Jeni berbalik. Senyum singgah di bibirnya, tipis dan ragu, lalu runtuh begitu saja. “Ndak usah sok baik. Aku wes capek!”
Galih cengengesan, gugup. Ujung sepatunya digesekkan ke lantai, berulang, seperti sedang menghapus sesuatu yang tak kelihatan.
“Piye?” Jeni melangkah mendekat. Kini jarak mereka tinggal satu langkah. Napasnya hangat. “Lih, sebenarnya aku cuma pengen jujur.”
Galih membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata berjejal di kepalanya, saling mendahului, dan tak satu pun berani dilontarkan.
“Maaf kalau aku suka kamu,” lanjut Jeni, “kalau kamu ndak, ya ndak apa-apa. Kita masih bisa—”
“Putri,” potong Galih. Nama itu terlontar sekenanya. Di kepalanya kini muncul bayang rambut hitam panjang dengan ujung bergelombang, juga tawa yang selama ini hanya dia dengar lewat pesan suara. Detak jantungnya mendadak berpacu.
Jeni terlihat terkejut. “Apa?”
“Aku sukanya sama Putri, Jen ….”
“Bukannya Pertiwi?” Jeni refleks menarik lengannya. Tak keras, tetapi cukup memaksa Galih menoleh. “Kamu sering cerita soal Pertiwi. Dan meski aku tahu kamu suka Pertiwi, aku tetap nekat ngomongin perasaanku yang sebenarnya.”
“Ngaco.” Galih melepaskan diri. Tatapannya mengeras.
Mereka saling pandang. Mata Jeni berkaca-kaca. Ada kecewa yang jatuh dan tidak sanggup dia tahan.
“Kalau aku bilang aku suka kamu, itu salah?” Suara Jeni nyaris datar. “Aku ada di sini. Aku nyata.”
Galih tak menjawab. Dia meraih tasnya, lalu melangkah pergi. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak, seolah-olah hendak menoleh, tetapi kembali menjauh. Pintu menutup pelan, tetapi bunyinya terasa keras.
***
Hari-hari setelahnya, bangku di sebelah Galih kosong. Beberapa kali dia melirik kursi itu, lalu berpura-pura sibuk. Dosen berbicara, tetapi pikirannya masih tertinggal di jendela kelas. Ya, Jeni tidak masuk kuliah.
Siang itu, Galih duduk di halte universitas yang di sekitarnya tumbuh pohon rindang. Dia menunggu Putri. Bangku besi terasa hangat di pantatnya. Dia mengecek jam, lalu ponsel. Pesan terakhir dari Putri masih terbaca: [Nanti aku ke halte, ya.]
Dua jam berlalu. Putri tak datang. Karena bosan dan merasa perlu curhat, Galih pun membuka laman media sosialnya. Jari-jarinya otomatis mengetik nama yang sering dia ajak curhat: Pertiwi. Layar memuat daftar pertemanan, tetapi tak ada nama itu. Merasa belum yakin, ia mencobanya lagi. Tetap tak ada Pertiwi di daftar itu.
“Njiiir, diblokir?” gumamnya, lebih pada diri sendiri.
***
Di kamar yang lain, ponsel hitam melayang sebelum akhirnya jatuh ke atas nakas. Bunyi benturannya kering. Layarnya masih menyala, menampilkan akun Pertiwi dengan foto profil yang disunting rapi. Belum lama Jeni memblokir Galih.
“Bikin akun Pertiwi pun percuma! Galih cuma butuh Pertiwi buat curhat. Ngomong suka, ini-itu. Lah, semuanya bacot tok! Aku ngaku suka dia juga … ujung-ujungnya sukanya sama Putri, keturunannya Keluarga Ibu Sumi, yang jadi cerita setan penunggu pohon trembesi yang mati disantap binatang buas di Hutan Sandekala. Najis!”
Selepas mengumpat, Jeni berdiri di depan cermin. Kali ini perhatiannya tertuju pada benda di sebelah ponsel itu—dompet. Dia mengeluarkan lipatan kertas kecil yang terselip di sela-selanya. Terlipat rapi, tetapi sudut-sudutnya sudah lembek. Barisan kata di atasnya miring. Jeni menelan ludah.
Bibirnya bergerak membaca mantra. Suaranya nyaris tak terdengar. Di sela-sela kata yang diucapkan, ada ingatan mendadak menyusup. Jeni teringat sesuatu.
***
Halte universitas di siang kala itu. Angin lewat sebentar, lalu pergi, menyisakan bau aspal dan besi. Jeni duduk di bangku besi paling ujung. Permukaannya hangat, menembus kain celananya. Bahunya jatuh. Punggungnya membungkuk sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Tangis menumpuk di dadanya, menyesakkan.
Di kepalanya, suara Galih masih berputar. Bukan kalimat panjang, bukan penjelasan. Hanya potongan-potongan pendek yang menyakitkan, salah satunya perasaannya yang ditolak.
Orang-orang lalu-lalang. Pemuda-pemudi tertawa, mengeluh soal tugas. Jeni tidak termasuk di situ. Dia seperti tertinggal satu langkah di belakang semuanya. Bahkan, orang-orang yang mengenalnya pun tampak tidak ingin mengganggu ataupun kepo banyak hal terkait apa yang terjadi padanya.
Waktu yang bergulir kala itu terasa aneh. Jam di ponselnya bergerak, tetapi perasaannya tidak. Dia menunduk, menatap lantai halte yang kusam. Di situlah dia menyadari perubahan kecil yang membuat tengkuknya meremang. Ada sepasang sepatu berhenti tepat di depannya. Bukan dari langkah yang tergesa, bukan pula langkah ragu. Sepatu hitam, bersih, berdiri seolah-olah memang sejak awal berniat berhenti di sana.
“Kamu ndak perlu cerita,” kata pemuda itu. Suaranya datar, tetapi juga tak lembut maupun keras. “Wajahmu sudah bercerita, kok.”
Jeni mendongak. Dadanya mendadak terasa kosong.
Pemuda itu berambut lurus, jatuh rapi di dahi. Bibirnya tipis, warnanya pucat. Matanya bening yang membuat orang sulit membaca maksud di baliknya. Kulitnya putih seputih mutiara, dingin, seperti tidak disentuh teriknya matahari.
“Kamu siapa?” tanya Jeni.
Pertanyaannya meluncur begitu saja, tanpa nada curiga. Lebih mirip kelelahan yang akhirnya menyerah.
Pemuda itu tidak langsung menjawab. Dia berdiri terlalu dekat, lebih dekat dari jarak wajar dengan orang asing. Jeni tidak mundur. Entah kenapa, tubuhnya terasa berat, seperti tertahan di bangku itu.
Pemuda itu tak membawa tas. Tak memegang ponsel. Bahkan tidak tampak sedang menunggu siapa pun. Wajahnya membuat Jeni sulit menebak usia. Terlalu tenang untuk mahasiswa, terlalu asing untuk dosen, dan terlalu muda untuk disebut lelaki seusia ayahnya. Seperti berhenti di satu usia yang tidak bergerak ke mana-mana.
“Haru,” kata pemuda itu akhirnya memperkenalkan diri. Nama itu jatuh pendek, tanpa penekanan, bak tidak penting apakah Jeni akan mengingatnya atau tidak.
Haru mengulurkan selembar kertas. Gerakannya pelan. Ujung jarinya pucat. “Ini cuma uji coba,” katanya. “Kalau ragu, simpan saja.”
Jeni menatap kertas itu. Tulisan tangan, miring, tak sepenuhnya rapi. Dia tidak membacanya. Hanya menatap.
“Hah, apaan nih?” tanyanya, refleks. Ada nada kesal, tetapi juga bingung. Tangannya sedikit menjauh, meski kertas itu belum menyentuhnya.
Haru tersenyum tipis. Senyum itu singkat. Tidak sampai ke mata. “Sesuatu yang dipindah,” katanya pelan, nyaris seperti bisikan, “ndak pernah kembali utuh.”
Jeni membuka mulut. Ada begitu banyak pertanyaan yang mendesak keluar. Tentang apa yang dipindah, ke mana perginya, dan kenapa harus dia. Kata-kata itu berdesakan di ujung lidah, tetapi tak satu pun sempat lolos.
“Alih Rupa,” kata Haru lebih dulu. Nada suaranya tetap datar. “Itu mantranya, Jen.”
Jeni tersentak. “Kenapa kamu—” Suaranya terputus. Jeni menatap Haru. Dia yakin belum pernah menyebutkan namanya. Bahkan belum memperkenalkan diri.
Haru hanya memandangnya, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyingkap sesuatu yang seharusnya tak diketahui. “Rapalkan mantra itu.”
“Kon sopo nyuruh-nyuruh aku?”
Haru tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti tadi. “Ya ndak apa-apa kalau ndak mau. Ujung-ujungnya kekecewaan bakal mencari jalan sendiri.”
Jeni menunduk. Ketika dia kembali mendongak, Haru sudah melangkah pergi. Tidak tergesa, tidak pula menoleh.
Lama-lama, ingatan itu memudar. Suara di halte menghilang. Bau aspal luruh. Hangat bangku besi tergantikan kesunyian yang lebih akrab. Kini kesadaran Jeni di dalam kamar lagi. Tangannya masih memegang kertas itu, yang baru saja membaca Mantra Alih Rupa.
Jeni melipat kertas itu, rapi seperti semula, lalu memasukkannya kembali ke dalam dompet. Kini, dadanya terasa ringan. Terlalu ringan. Jeni kini lekat-lekat menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Tak ada perubahan yang tampak. Belum.
***
Di kota lain, pada waktu yang lain, Haru duduk di serambi bangunan ibadah berdinding lembap. Catnya mengelupas. Di sampingnya, lelaki berjubah putih yang dipanggil Ustaz Mentari berbicara panjang tentang iman dan dosa, tentang godaan yang katanya datang dari luar diri manusia. Haru mendengarkan.
Dahulu, di tempat yang kini jadi universitas, dia pernah duduk di sisi orang-orang yang dipercaya, disucikan, bahkan di dekat yang paling pandai menyembunyikan busuk. Wajah-wajah berganti. Bangunan runtuh dan dibangun ulang. Haru tetap sama. Dia hanya menyesuaikan bahasa dan pakaian, seperti air yang tahu cara mengisi wadah.
Pernah pula dia berdiri di balik kerumunan manusia yang terlibat proses syuting di studio besar berisi replika dataran bulan. Namanya tak tercatat di mana pun. Ketika sorak-sorai pecah dan manusia merasa telah menaklukkan bulan, Haru terpingkal-pingkal.
Jauh sebelum itu, di tanah yang lebih tua di suatu negeri, Haru menyaksikan bulan terbelah sementara waktu yang kemudian merapat kembali. Manusia menafsirkan, memperdebatkan, lalu mewariskannya sebagai kisah mukjizat.
Dan di masa lain lagi, dia berdiri di tepi kota yang perlahan ditelan bumi. Menara-menara tenggelam satu per satu. Doa naik bersama teriakan. Sebagian menyebutnya azab sebagian menyebutnya takdir.
Haru tahu, apa pun namanya, manusia selalu membutuhkan sesuatu untuk disalahkan, disucikan, atau dipuja. Dan dia selalu tahu caranya menyesuaikan diri.
***
Suatu pagi yang cerah, Jeni berdiri di halte universitas. Rambutnya ditata rapi, terlalu rapi untuk hari kuliah biasa. Bajunya mulus kayak baru saja dipilih dengan hati-hati. Dia menatap layar ponsel beberapa detik, lalu mematikannya dan memasukkannya ke dalam tas. Perasaannya jadi begitu ceria. Jeni bahkan tidak tahu apa yang membuatnya sebahagia itu.
“Galih,” panggil Jeni ketika pemuda itu datang dari arah parkiran. Senyumnya merekah.
Galih berhenti mendadak. Detak jantungnya melonjak. Di hadapannya berdiri sosok yang dia kenali sebagai Putri. Senyum itu dan cara tubuhnya condong sedikit ke depan saat memanggil namanya. Bahkan jeda napas sebelum memanggil, semuanya tepat. Terlalu tepat. Seperti tiruan yang dibuat dari ingatan paling intim.
Tanpa berpikir panjang, Galih meraih lengan Jeni, “Ngopi bareng dulu, Put!" dan menariknya pergi.
Mereka berjalan melewati Putri begitu saja, nyaris beradu bahu. Galih tak menoleh lagi. Langkah mereka cepat. Jeni tak bertanya, tetapi dia mulai paham. Di mata Galih, wajahnya beralih jadi wajah Putri, bahkan keseluruhan yang ada di tubuh masing-masing.
Di bawah pohon seberang halte, Haru berdiri. Bayangannya memanjang, menyentuh aspal yang retak. Dia mengamati sepasang anak muda itu tanpa ekspresi. Angin pagi berembus dan Haru melebur menjadi debu.