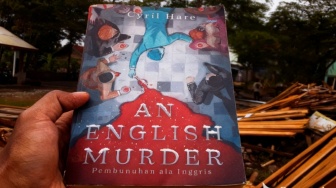Urwaz berdiri di balkon apartemen, membiarkan angin malam mengelus tengkuknya yang bertato kupu-kupu. Sayap serangga itu tampak bergetar samar ketika cahaya bulan merayap pelan.
Di atas kota, cahaya bulan mulai kehilangan putihnya. Berubah tembaga, menghangat pelan, seolah-olah sebentar lagi akan sepenuhnya memerah.
Di kejauhan, kota masih hidup. Lampu-lampu apartemen lain menyala, sebagian balkon dipenuhi bayang orang-orang yang menengadah, sebagian lagi sibuk dengan layar di genggaman. Urwaz tidak ikut apa-apa. Dia hanya berdiri, tangan menyandar pada besi balkon yang dingin.
Ponselnya bergetar. Dia melirik sekilas, lalu tersenyum tipis sebelum membalas singkat. Langkah kaki terdengar dari dalam. Aroma sabun dan keringat bercampur menyusup ke udara. Dua tangan melingkar dari belakang, menyelinap ke sela ketiaknya, meraba dada yang kurus tapi hangat. Pipinya disentuhkan ke punggung Urwaz.
“Kamu selalu begini,” ujar Erza lirih. “Sendiri dan menyendiri.”
Urwaz tidak langsung menjawab.
“Aku pulang telat,” lanjut Erza. “Ada tambahan jam kerja.”
“Dan kau selalu lupa memberi kabar,” kata Urwaz akhirnya. Nada suaranya datar, nyaris seperti catatan kaki. “Kadang saya bertanya-tanya, apakah itu bentuk cinta.”
Erza tersenyum, bibirnya menekan punggung Urwaz sebentar, seolah-olah mencari posisi nyaman.
“Aku mencintaimu seperti kamu mencintai dunia sepi milikmu.”
Urwaz terkekeh kecil. “Dunia sepi yang penuh barang?” Dia menoleh sedikit seraya menaikkan alis kanan. “Buku-buku, kemeja warna-warni, parfum mawar, kacamata tanpa minus, dan—”
“Justru itu,” potong Erza. “Semua yang kamu rawat dengan sabar.”
Urwaz berbalik. Tangannya menahan pergelangan Erza, ibu jarinya mengusap kulit yang mulai dingin oleh angin malam. Dia menunduk, lalu mencium bibir istrinya singkat.
Erza mengembuskan napas di bawah dagu Urwaz.
“Manusia macam dirimu memang aneh. Suka menyendiri, tapi suka banget disentuh.”
“Introvert romantis,” gumam Urwaz.
Erza tertawa pelan.
Mereka kini berdiri berdampingan, bahu bersentuhan. Bulan kian gelap, merahnya semakin pekat. Di bawah sana, terdengar sorak kecil dari balkon lain. Entah kagum, entah hanya ingin terdengar ikut serta.
“Lihat,” kata Erza. “Semua orang menunggu hal yang sama malam ini.”
Urwaz mengangguk.“Dan besok, semuanya akan bilang ‘malam ini indah banget’.”
Lantas dia merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel, menekan layar sampai menyala, kemudian menekan aplikasi kamera, lalu mengangkat ponsel. Layar menyala, wajah mereka pun masuk dalam bingkai. “Tersenyumlah, Beb.”
Erza menurut. Jepretan terdengar. Dalam foto itu, bibir Urwaz mendarat di pipinya. Potret kecil yang tampak manis, nyaris seperti iklan kebahagiaan.
Erza mengambil ponsel itu. Jarinya sudah bersiap di layar. “Aku unggah, ya.”
Urwaz menahan pergelangan tangan Erza. “Tidak perlu.”
Erza menatapnya. “Kenapa?”
Urwaz menarik ponsel itu, memasukkannya ke saku celana. Dia melangkah ke sudut balkon, memunggungi Erza. Di sana, besi balkon terasa lebih dingin.
“Dulu,” kata Urwaz perlahan, tanpa menoleh, “orang-orang menulis untuk mengingat. Mereka duduk, mengingat kembali detik demi detik, lalu menuangkannya. Ada jarak, ada permenungan.
Entahlah. Dulu, menulis pun buat mendeskripsikan peristiwa, memanifestasikan perasaan dalam bentuk tulisan. Surat-menyurat menjadi budaya wilayah. Segalanya diejawantahkan sesuai perspektif masing-masing. Sekarang, kecenderungan dari kemudahan yang ditawarkan teknologi menggerus semua itu.
Kita dapat langsung melihat peristiwa melalui foto. Kemudahan yang ditawarkan malah mematikan sensitivitas. Yang masih peka dan mampu merangkai kalimat-kalimat indah dapat dengan mudah menuliskannya.
Namun, bagi yang tidak, bisanya cuma jepret ini jepret itu, lalu dibagikan. Sedangkan, bagi saya, kemudahan itu sangat mengurangi rasa yang sesungguhnya dapat lebih intim.”
Erza diam saja. Dia paham betul suaminya. Angin menggerakkan ujung rambutnya. Erza pun memeluk Urwaz dari samping, lebih erat dari sebelumnya.
“Mas,” katanya lembut. “Kapan terakhir kali kita main petak umpat?”
Urwaz tersenyum tipis. “Yaelah ….” Tatapannya tertuju pada langit.
Gerhana kini sempurna. Bulan seperti luka tua yang dibuka kembali. Eklips yang Indah, tapi ganjil.
Mereka berdua kini terdiam, saling merengkuh. Di bawah pendar merah itu, dunia terasa sejenak berhenti. Lalu, sesuatu berubah.
Cahaya di tepi bulan bergerak dengan arah yang tidak semestinya. Terlalu cepat. Terlalu pasti.
Ponsel di saku Urwaz bergetar keras. Notifikasi beruntun masuk. Dia lantas mengeceknya. Judul-judul berita berloncatan. Esoknya, matahari terbit dari barat. []