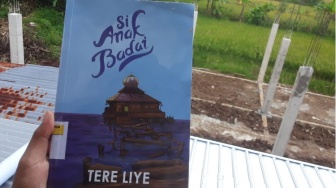Di tengah dunia yang semakin menuntut kepastian dan kestabilan, profesi penulis kerap dianggap sebagai pilihan terakhir. Sebuah alternatif yang diambil ketika segala pintu lain terasa tertutup. Banyak orang melihat penulis sebagai sosok yang hidup di pinggir arus utama, yang tak sanggup bersaing di dunia kerja formal, dan akhirnya "menyepi" dalam kata-kata.
Stigma ini terus berulang, bahkan dari lingkungan paling dekat. Ketika seseorang memutuskan untuk menulis, komentar seperti “kenapa nggak cari kerja tetap saja?” atau “kalau memang serius, kenapa nggak jadi dosen sekalian?” muncul begitu mudah. Seolah menulis hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Seolah seseorang tidak bisa menjadikan menulis sebagai jalan hidup, kecuali karena gagal di jalur lain.
Padahal, bagi banyak penulis, menulis bukanlah bentuk pelarian. Ia adalah pilihan yang sadar dan dalam banyak hal, justru merupakan keputusan paling berani. Menjadi penulis berarti berani hidup dalam ketidakpastian, mengandalkan ketekunan alih-alih gaji tetap, dan menggantungkan masa depan pada kepercayaan bahwa kata-kata punya kuasa untuk mengubah sesuatu.
Menulis bukanlah kerja yang bisa disambi sambil menunggu "hidup yang sesungguhnya" dimulai. Ia membutuhkan disiplin, ketahanan mental, dan proses panjang yang kadang tak terlihat. Di balik sebuah artikel yang viral, puisi yang menyentuh, atau cerpen yang masuk kurasi media, ada proses revisi berkali-kali, ada malam-malam panjang yang dihabiskan dalam kesunyian, ada rasa ragu yang datang lebih sering daripada apresiasi.
Namun dunia sering kali tidak melihat itu. Tulisan dikonsumsi cepat, seperti kopi instan_dinikmati seperlunya, lalu dilupakan. Penulis pun dianggap seperti bayangan: ada, tapi tak benar-benar dilihat. Mereka yang memilih jalan ini kerap harus berhadapan dengan pertanyaan eksistensial: apakah yang dilakukan ini cukup penting? Apakah tulisannya benar-benar berdampak? Apakah semua upaya ini layak?
Jawabannya, tentu, tak selalu jelas. Tapi bagi mereka yang menjalaninya, menulis adalah bentuk keberadaan. Saat dunia terasa terlalu bising, tulisan menjadi ruang paling jujur untuk menyuarakan keresahan. Saat tidak ada yang mau mendengar, tulisan menjadi tempat bagi suara-suara kecil untuk hidup dan mengakar. Penulis bukan melarikan diri dari dunia_mereka justru mencoba mengolah dunia dengan cara yang lebih halus, lebih pelan, namun tetap menggugah.
Yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa penulis memiliki peran penting dalam membentuk budaya, menyuarakan yang tak terdengar, dan membukakan ruang dialog di masyarakat. Dalam sejarah pun, suara-suara perubahan tak jarang lahir dari pena, bukan podium. Kata-kata punya daya jangkau yang kadang lebih tajam dari pidato atau kebijakan.
Sayangnya, karena proses ini tidak selalu berwujud uang atau jabatan, profesi menulis sering kali dianggap “belum mapan.” Padahal, kemapanan sejati bukan hanya soal pendapatan atau status sosial. Ia juga soal kebermaknaan. Dan bagi banyak penulis, menulis memberi makna yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.
Bukan berarti semua penulis menolak kerja formal atau hidup ideal versi masyarakat. Tapi ketika seseorang memilih untuk menulis secara konsisten, tetap bertahan meski tulisannya ditolak berkali-kali, dan masih percaya bahwa tulisannya layak dibaca_itu adalah bentuk keseriusan. Sebuah komitmen jangka panjang yang tak bisa disamakan dengan pelarian.
Menjadi penulis memang berarti menghadapi kemungkinan ditolak, diabaikan, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi di sisi lain, itu juga berarti menjadi orang yang bersedia terus belajar, terus menyimak, dan terus mencoba. Penulis adalah pendengar yang baik dan pengamat yang tekun. Mereka tidak hanya menulis apa yang ada di kepala mereka sendiri, tetapi juga mencoba memahami realitas orang lain_dan itu adalah bentuk empati yang paling dalam.
Bagi sebagian orang, mungkin menulis tidak akan pernah membawa kekayaan materi. Tapi bagi yang memilihnya, menulis memberi kekayaan lain: kemampuan untuk memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, kesempatan untuk membentuk makna dari kekacauan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri dalam setiap paragraf yang ditulis.
Jadi ketika seseorang memilih menjadi penulis, seharusnya itu tidak dianggap sebagai kegagalan menjalani hidup yang “normal.” Justru itu adalah langkah berani untuk menciptakan normalitas baru_yang tidak selalu diukur dari pendapatan tetap, jenjang karier, atau status sosial, tapi dari ketulusan dan konsistensi dalam berkarya.
Karena sejatinya, menulis bukan tentang seberapa banyak yang membaca, tapi tentang keberanian untuk terus mengatakan sesuatu, bahkan saat dunia terlalu bising untuk mendengar.