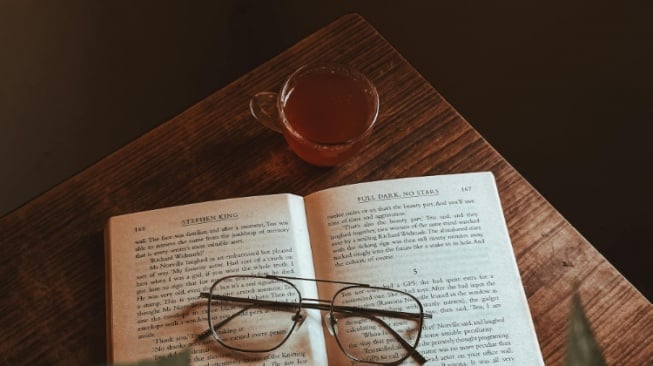Kedai itu kurang lebih bisa menampung lima puluh hingga tujuh puluh orang, dan di sanalah bekerja seorang barista pemula bernama Hen. Tempat itu tidak pernah benar-benar punya wajah yang tetap, dan entah kebetulan atau tidak, Hen pun tumbuh dengan watak yang serupa.
Di jam-jam tertentu, kedai itu dipenuhi orang-orang yang datang membawa laptop, obrolan setengah serius, serta tawa yang terdengar lebih keras daripada isinya. Di jam lain, kedai itu berubah menjadi ruang paling sunyi yang hanya dihuni suara mesin kopi dan langkah Hen sendiri yang berulang-ulang tanpa tujuan jelas.
Di tengah keramaian, Hen belajar bersikap ramah tanpa harus terlibat, menyapa tanpa benar-benar hadir; sementara dalam kesepian, ia belajar bertahan dengan caranya sendiri (membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih, merapikan cangkir yang tak perlu dirapikan), sekadar membuka ilusi bahwa masih ada sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ia terbiasa berdiri sedikit lebih lama di balik meja bar, menunda pulang tanpa alasan yang sungguh ia pahami, seolah kedai itu menawarkan perlindungan sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang menunggunya di luar.
Di ruang yang kadang ramai kadang sepi itulah Hen perlahan membentuk dirinya: seseorang yang mahir membaca suasana, tetapi gagap membaca isi hatinya sendiri; seseorang yang tampak sibuk bergerak, padahal sesungguhnya hanya sedang belajar diam.
Hen menemukannya lagi di balik meja bar kopi itu, bukan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, melainkan sebagai kehadiran ganjil yang muncul dari celah ingatan yang tak pernah ia kunci rapat. Di antara bunyi mesin espresso yang mendesis dan aroma biji kopi yang dipanggang terlalu gelap, wajah Kelana hadir sebagai senyum yang terlalu rapi untuk disebut jujur—senyum yang lebih mirip basa-basi orang dewasa ketimbang ungkapan rindu yang tulus. Hen tahu betul senyum itu tidak membawa maksud apa pun, tidak menjanjikan kelanjutan, apalagi kepulangan. Namun, tubuhnya bereaksi seolah ada sesuatu yang lama tertinggal kini disentuh kembali.
Di titik itu, Hen sadar bahwa rindu tidak bekerja dengan logika; ia tidak peduli pada jarak, waktu, atau kesepakatan tak tertulis untuk saling melanjutkan hidup. Ia hanya datang, menyalakan sesuatu yang seharusnya sudah padam, lalu membiarkan Hen menanggung akibatnya sendirian di balik meja bar yang dingin dan berjarak.
Sebagai barista, Hen terbiasa hidup di ruang antara: tidak sepenuhnya masuk dalam hidup pelanggan, tetapi juga tidak benar-benar di luar dari cerita mereka. Ia hanya penyaji, pengantar, figur netral yang keberadaannya dibutuhkan, namun jarang diingat. Tangannya bergerak otomatis—menggiling biji kopi, merapikan alat seduh, menuang air panas dengan takaran yang telah melekat di ingatan otot. Namun, pikirannya sering melayang ke tempat lain, ke percakapan-percakapan yang tak pernah benar-benar terjadi antara dirinya dan Kelana, ke kalimat-kalimat yang dulu terlalu takut ia ucapkan.
Di tempat ini, Hen tidak diizinkan untuk berpura-pura merayu, bahkan untuk sekadar mengakui bahwa ada perasaan yang belum selesai. Rokok yang tak pernah ia nyalakan menjadi simbol keinginan-keinginan kecil yang terus ia tekan, sementara nikotin imajiner memenuhi kepalanya dengan rasa nyaru yang membuat dunia seolah berjalan setengah langkah lebih lambat.
Rindu, ketika tidak diberi jalan keluar, berubah menjadi sesuatu yang kasar. Bagi Hen, ia tak lagi romantis atau melankolis, melainkan brutal dan menuntut, seperti utang lama yang tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Ia telah berusaha menutup pintu hatinya rapat-rapat, menguncinya dengan kesibukan, rutinitas, dan dalih kedewasaan, namun rupanya pintu itu lapuk dari dalam.
Setiap kali Hen merasa telah berhasil melupakan Kelana, selalu ada celah kecil yang terbuka, dan dari sanalah rindu menyelinap masuk, duduk santai, lalu bertingkah seolah memang berhak tinggal di sana. Hen kerap marah pada rindu, tetapi kemarahan itu perlahan berbelok menjadi amarah pada dirinya sendiri—pada ketidakmampuannya mengambil keputusan tegas sejak awal.
Kelana pernah berkata bahwa ia nyaman tinggal di Kota Kembang, dan Hen tidak pernah meragukan itu. Cara Kelana bercerita selalu terdengar ringan, seolah hidup adalah sesuatu yang bisa dilipat rapi dan dipindahkan kapan saja. Dari potongan kisah yang kadang muncul di layar ponsel, hidup Kelana tampak bergerak maju, penuh kemungkinan dan perjumpaan baru. Sementara Hen terjebak di Kota Pelajar yang bimbang—kota yang katanya penuh mimpi, tetapi diam-diam menguras keberanian.
Setiap sore ia seperti berjudi dengan Tuhan, berharap hari ini sedikit lebih ramah daripada kemarin, sambil menyajikan kopi pada manusia-manusia yang tampak tenang di luar, tetapi mungkin sama rapuhnya di dalam. Hen belajar bahwa sebagian orang bertahan dengan bergerak, sementara sebagian lain bertahan dengan tetap tinggal, meski tidak selalu tahu apa yang sebenarnya mereka tunggu.
Hen sering tertawa ketika melayani pelanggan, tawa profesional yang telah ia kuasai dengan baik, padahal di dalam dadanya ada retakan panjang yang tak pernah benar-benar sembuh. Dalam ingatannya, Kelana juga kerap tersenyum, namun senyum itu kini terasa ambigu—seolah ia tak mau paham, atau sengaja memilih untuk tidak menjejak terlalu jauh ke wilayah yang berisiko menyakitkan.
Hen tidak sepenuhnya menyalahkan Kelana sebab ia tahu Kelana memang diciptakan untuk berjalan, bukan menetap. Yang tak pernah ia akui dengan jujur adalah kenyataan bahwa dirinya sendiri memilih untuk tetap tinggal, terus bergerak di tempat yang sama sambil berharap sesuatu berubah dengan sendirinya. Ia menggiling kenangan seperti menggiling biji kopi yang terlalu lama disimpan, berharap rasa pahitnya bisa diatur ulang dengan teknik dan takaran yang tepat.
Ada saat-saat ketika pikiran Hen menjadi sangat kekanak-kanakan. Ia membayangkan rindu sebagai sosok nyata dengan wajah sok berkuasa, berdiri di hadapannya tanpa rasa bersalah, dan ia ingin meninju wajah itu sekali atau dua kali—sekadar membuktikan bahwa dirinya masih punya kendali atas hidupnya sendiri.
Bukan karena ia sepenuhnya membenci rindu, melainkan karena ia lelah terus-menerus diatur olehnya. Ia ingin rindu tahu bahwa ia tidak selalu menang, bahwa ada batas yang seharusnya tidak ia lewati. Namun, setiap kali imajinasi itu usai, Hen kembali pada kesadaran yang sama: rindu tidak bisa disentuh, tidak bisa dipukul, dan tidak akan pergi hanya karena ia menginginkannya.
Pada akhirnya, rindu tetap tinggal di sudut hati Hen seperti penghuni gelap yang tak pernah membayar sewa, tetapi enggan angkat kaki. Ia diam, namun kehadirannya terasa, tumbuh perlahan tanpa izin, semakin hari semakin tak tahu diri. Dan mungkin pengakuan paling jujur yang akhirnya mampu Hen terima adalah kenyataan bahwa ia sendirilah yang memberi rindu ruang untuk menetap. Ia tak pernah benar-benar mengusirnya karena jauh di dalam dirinya ada ketakutan akan kekosongan setelah rindu itu pergi.
Maka Hen kembali berdiri di balik meja bar kopi, menyajikan basa-basi demi basa-basi, sambil belajar hidup dengan kesadaran pahit bahwa tidak semua luka ingin disembuhkan; sebagian hanya ingin diakui keberadaannya. Asu sekali, memang—tetapi mungkin di situlah Hen akhirnya mulai berdamai, bukan dengan Kelana, melainkan dengan dirinya sendiri.