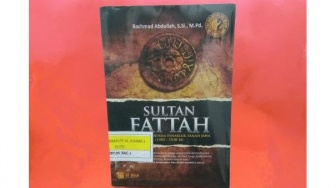Sebulanan terakhir, di skala global grafik terinfeksi Covid-19 justru meninggi. Di negeri kita, meski jumlah terkena virus ini perharinya jauh menurun dibanding di akhir 2020 dan awal 2021, namun kewaspadaan tetap dibutuhkan mengingat momen Lebaran sebentar lagi menitipkan segudang potensi risiko. Ada pun hal yang cukup melegakan adalah meningkatnya persentase warga yang sudah divaksinasi, bahkan usaha mempercepat vaksinasi sudah dilakukan sejak sekitar Maret lalu.
Di tengah pro-kontra larangan mudik serta ‘kreativitas’ pemudik untuk tetap pulang kampung, rasanya tidak salah kita periksa kembali efektivitas komunikasi multi-arah yang dilancarkan dari berbagai komunikator sekaligus komunikan.
Ini semakin penting dipertanyakan kembali, mengingat keberhasilan kita untuk melepaskan diri dari musibah multidimensi ini sejatinya berpangkal juga dari kelihaian kita berkomunikasi. Efektivitas komunikasilah yang akhirnya membuat kita mau mengubah perilaku agar tidak rentan terkena Covid-19.
Faktor Komunikasi
Selanjutnya, perubahan perilaku hanya akan bermula dari berterima atau tidaknya (resepsi) kita terhadap pesan dan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak berkompeten. Dalam konteks ini, para ahli epidemiologi mungkin bisa dikatakan paling harus didengarkan pendapat dan rekomendasinya.
Ini masuk akal, mereka adalah pakar yang selama ini memang bertungkus-lumus dalam kajian dan perumusan teori mengenai epidemi, bahayanya, cara menangkalnya, pengambilan kebijakannya, dan lain sebagainya. Berikutnya, selain pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kita tidak bisa mengabaikan peran media. Melalui medialah semua pesan kita akses, pilih dan pilah.
Ironisnya, beberapa temuan penelitian di ramah komunikasi, baik komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi politik bahkan komunikasi kesehatan menunjukkan fenomena ‘menyedihkan’ mengenai “rapor’ pola dan efektivitas komunikasi kita sekaitan pandemi.
Salah satu yang paling menarik sekaligus ‘mengenaskan’ adalah hasil penelitian Hywel Coleman (2020). Dari penelitian Coleman ditemukan fakta, separuh orang Indonesia yang menjadi informannya mengaku belum pernah mendengar istilah-istilah seperti PSBB, ODP, PDP dan new normal atau pernah mendengar tetapi tidak memahami maknanya. Beberapa orang menafsirkan new normal sebagai “kembali normal seperti biasa” dan kehidupan seperti biasa sebelum ada virus bebas bersosialisasi (Kompas, 26/8/2020).
Fakta ini menyiratkan ada kesalahan dan kekurangcermatan kita dalam berkomunikasi. Berpijak salah satu pendekatan Psikologi Komunikasi, dikenal teori dasar mengenai pentingnya persepsi dalam tindak komunikasi. Persepsi membutuhkan kesamaan pandangan, pengertian dan pengetahuan mengenai pesan yang disampaikan sehingga menyumbang kepada efektivitas komunikasi.
Jika penerima pesan tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai sebuah atau beberapa konsep kunci yang terkandung dalam informasi keseluruhan, maka dipastikan komunikasi tidak akan memberi efek yang diharapkan, dengan kata lain, komunikasi tidak efektif.
Pengaruh Sosio-Kultural
Hal lain yang tak kalah urgen adalah, tidak banyak penentu kebijakan yang mencoba memahami pentingnya pemahaman aspek kultural dari kelompok masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak di antara kita yang berperilaku abai dan tidak peduli terhadap Protokol Kesehatan disebabkan oleh pandangan atau paradigma yang apriori terhadap pandemi Covid-19. Di beberapa tempat di nusantara bahkan ditemukan ketidakpercayaan masyarakat setempat mengenai eksistensi pandemi ini. Mereka meyakini bahwa pandemi Corona tidak nyata, bahkan yang lebih ekstrim meyakini berita pandemi hanyalah rekayasa dan isapan jempol penguasa beserta media belaka.
Berangkat dari hal ini, dalam perspektif ilmu sosial ada perspektif konstuksi sosial (khususnya dalam konteks kesehatan) yang mengasumsikan bahwa pengetahuan tentang sehat, sakit, sebab sakit, dan pengobatannya ditafsirkan dan dinegosiasikan. Mereka memproduksi dan mereproduksi makna kondisi sakit mereka yang boleh jadi berkaitan dengan kondisi keluarga pasien, kehidupan sosial, profesi, budaya, politik dan keagamaannya (Mulyana & Ganiem,. 2021). Ini berarti, persepsi tentang sakit, penyakit, dan segala konstuksi makna yang mengelilinginya sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural. Sebegitu kuatnya pengaruh tersebut hingga memengaruhi pula sikap dan perilaku mereka merespons lingkungan, termasuk lingkungan yang dipenuhi oleh epidemi Covid-19.
Temuan lainnya yang memperkuat perspektif konstruksi sosial adalah dalam hal pandangan masyarakat mengenai vaksinasi. Hasil penelitian dari Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia (PAEKI) di awal 2021 mengenai tingkat kesediaan menerima vaksinasi di Indonesia di 34 provinsi, ternyata dua provinsi terendah persentase penerimaannya adalah Daerah Istimewa Aceh dan Sumatra Barat. Di Aceh, hanya 46% masyarakatnya yang menerima dan yakin akan vaksinasi. Sementara di Sumatra Barat angka itu tak jauh berbeda, 47%. Ini lumayan jauh di bawah angka tertinggi sebanyak 74% di Papua Barat. Sementara di DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebagai perbandingan, angka itu berada di kisaran 66% dan 65%.
Revitalisasi Komunikasi Kesehatan
Usaha revitalisasi dan pengarusutamaan komunikasi kesehatan yang efektif sampai ke akar rumput amat mendesak dilakukan sesegara mungkin. Media juga perlu diberi kesadaran untuk semakin selektif dan persuasif memilih bahasa dan redaksi pembingkaian pemberitaan serta sosialiasi informasi yang bergerak dalam arus konteks minimalisasi dampak pandemi Covid-19. Salah dalam penyampaian informasi, atau informasi dikemas dalam bahasa yang tidak membumi akan menghasilkan kebingungan bahkan apriori yang semakin nyata di tataran masyarakat kalangan bawah. Bahasa yang sederhana namun padat informasi dan mudah dipahami adalah kunci agar kampanye melawan bahaya pandemi dapat terus efektif digencarkan.
Revitalisasi pola komunikasi kesehatan mendesak segera digencarkan, apalagi realitas buram potret tidak efektifnya komunikasi di tanah air seolah mengikuti fenomena global. Dalam survey di 35 negara yang paling tinggi tingkat infeksi Covid-19 di bulan Juni 2020 ditemukan fakta, hanya nyaris separuh (46,8%) yang meyakini vaksinasi akan efektif mengurangi dampak Covid-19 (Jurnal Nature, Juni 2020). Sementara selebihnya cenderung tidak yakin, tergabung ke dalam sub-pandangan negatif yang beragam. Mulai dari setengah menyetujui (24,7%), ragu-ragu/netral (14,2%), sedikit setuju (8.1%), dan benar-benar menolak (6,1%).
Penelitian di dalam negeri semakin memperkuat data itu. Terbukti di awal 2021, ketika ditanyakan alasan menolak vaksin, responden menyebutkan beberapa alasan. Sebanyak 30% masyarakat tidak yakin dengan keamanannya. Sementara, 22% Tidak yakin vaksinasi efektif. Di lain pihak, ada 12% takut efek samping, 13% tidak percaya, dan sebanyak 8% tidak percaya vaksin disebabkan alasan agama (PAEKI, awal 2021).
Rentetan data di atas merupakan Pekerjaan Rumah bersama antar seluruh stake-holders yang terlibat langsung maupun tak langsung sebagai upaya masif segera keluar dari jerat pandemi Covid-19. Sudah bukan waktunya beretorika dan sekadar menghimbau atau bertindak represif berupa larangan mudik dan berkumpul lengkap dengan sanksi hukum. Yang lebih urgen adalah reorientasi, revitalisasi dan pengarusutamaan komunikasi kesehatan yang efektif dan efisien ke jantung terdalam struktur masyarakat. Itu semua belum terlambat jika dilakukan mulai dari sekarang.
MOHAMMAD ISA GAUTAMA / Pengajar Sosiologi Media dan Sosiologi Komunikasi di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.