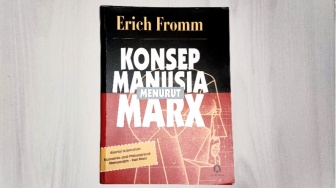Beberapa waktu lalu, saya mengikuti sebuah seminar penelitian disertasi mahasiswa S3 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, sebuah kampus dengan popularitas yang cukup tinggi di kancah mahasiswa Indonesia. Seminar yang saya ikuti ini cukup menarik, pasalnya tema yang diangkat cukup menampar kehidupan kita yakni mengenai Googling Culture, atau budaya Googling yang dilakukan masyarakat modern saat ini demi mendapatkan informasi secara cepat dan instan.
Kebetulan judul seminarnya itu “Budaya Googling: Paradox Mesin Pencarian dalam Ekosistem Pendidikan”. Ya, memang penelitian disertasi yang dilakukan oleh mas Grendi Hendrastomo ini berkutat dalam dunia pendidikan, lebih tepatnya budaya googling oleh para siswa ketika mereka sedang menempuh pendidikannya.
Ketika mendengar judulnya saja saya sudah berekspektasi tinggi perihal isi seminarnya yang pasti isinya daging semua, tanpa kuah ataupun nasi. Apalagi ditambah beberapa hari sebelum mengikut seminar ini, saya mendapatkan bocoran mengenai isi penelitian mas Grendi dari Promotonya yakni pak Supraja (seorang dosen S3 Sosiologi UGM) yang menjelaskan bahwa mas Grendi ini menemukan fakta menarik mengenai teknologi saat ini yang justru menjadi dehumanisasi teknologi bagi manusia.
Menurut pak Supraja, teknologi, Google, dan kawan-kawannya pada mulanya dihadirkan untuk membantu manusia, membantu kebutuhan manusia, membantu segala aktivitas manusia. Namun, nyatanya semakin kesini, semakin mendominasi, semakin modern untuk saat ini, justru teknologi mengontrol manusia, membuat ketergantungan pada manusia.
Inilah yang mas Grendi sebut sebagai paradox mesin pencarian. Dengan meminjam istilah dari Neil Postman (seorang pemikir sekaligus kritikus media teknologi dan pendidikan asal Amerika), bahwa teknologi itu ibarat koin mata uang yang memiliki dua sisi. Salah satu sisinya ia dapat menjadi berkah, sedangkan salah satu sisi lainnya justru menjadi petaka.
Ketika saya mengikut seminar mas Grendi, justru saya merasa tercerahkan, mengenai betapa berangusnya, betapa mengerikannya teknologi saat ini, yang kalau menurut Prof. Heru (seorang Profesor Sosiologi UGM) bahwa teknologi itu seperti Deus Ex Machina, Tuhan yang lahir dari kecerdasan buatan manusia.
Misalnya begini, ketika kita mengetikkan suatu kata kunci dalam kolom pencarian Google, maka algoritma Google dalam hitungan detik akan mengarahkan kita kepada beberapa website atau beberapa laman yang menurutnya itu cocok buat kita.
Mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok Google tahu apa yang cocok buat kita? Ya, karena data-data kita sudah dikuasai oleh Google. Misalnya data histori pencarian, data lokasi kita, data intensitas kita membuka internet, data pendidikan kita, minat maupun hobi kita dan data-data lainnya, yang mana melalui data tersebut algoritma Google berusaha melacak apa yang kita minati.
Nah, dari sini secara tidak langsung kita itu ibarat hamba yang nurut pada Tuhannya, gitu. Kita cenderung akan memilih website yang paling atas, atau setidaknya deretannya berada pada barisan pertama hingga ketika. Apalagi ketika website tersebut menonjolkan kata kunci yang sesuai dengan apa yang kita cari. Padahal, barisan-barisan tersebut sangat sarat akan komersialisasi dengan mengandalkan Search Engine Optimizer.
Melalui realitas demikian, secara tidak langsung kita itu dikontrol oleh si Google ini, meskipun kita sering berdalih bahwa apa yang kita klik itu sesuai kehendak kita pribadi, tapi sebenarnya kehendak kita untuk mengklik itulah yang dikontrol oleh Google.
Bahwa menurut Google, ini loh yang cocok buat kamu, ini loh yang kamu butuhkan, ini loh yang seharusnya kamu klik. Sedangkan kita hanya mengangguk dan mengiyakannya perintahnya.
Hingga semakin ke sini, semakin modern, semakin besar arus digitalisasi, maka semakin bergantungnya kita dengan teknologi. Kalau menurut temuannya mas Grendi, seorang siswa cenderung mencari jawaban dari internet dibandingkan mencari jawaban dari buku atas tugas gurunya, misalnya seperti mencari jawaban di Brainly.
Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa teknologi itu menawarkan kecepatan dan pragmatisme, seorang siswa akan lebih memilih tugasnya cepat selesai dan dengan cara yang nggak ribet. Dan, semua itu sudah disediakan oleh Google untuk memudahkan para siswa untuk mencari jawaban atas tugas-tugas sekolah mereka.
Lebih memprihatinkannya lagi yakni siswa ketika sudah menemukan jawabannya di internet maka saat itu juga dia akan berhenti menelusuri, dia akan stagnan di situ dan nggak mau membaca secara lengkap apa yang dimuat dalam laman web yang ditelusurinya. Padahal, jika siswa itu mau membaca lebih lengkap, maka pengetahuannya akan lebih berkembang dan lebih luas.
Inilah budaya baru yang diciptakan oleh teknologi yang memprioritaskan kecepatan, bukan ketepatan, yang penting selesai, yang penting apa yang saya cari ditemukan. Misalnya kita sendiri ketika mencari sebuah berita, maka kita biasanya membaca sekilas-sekilas doang, nggak sampai lengkap dan panjang bahkan sampai menelusuri berita tersebut secara kronologis.
Kita cenderung menggunakan suggestion/predictive text yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan dalam kolom pencarian Google. Kita cenderung menggunakan algoritma Google yang sesuai dengan kata kunci kita, ketika kita sedang berselancar di dalamnya. Sehingga kita hanya mengunjungi laman yang ada kata kunci yang kita cari saja, bahkan kita hanya akan membaca bagian yang ada kata kuncinya saja, nggak sampai artikel lengkapnya.
Kalau kata mas Grendi, kita semua adalah manusia-manusia algoritma, yang mengandalkan algoritma Google untuk menuntun segala tindak laku kita dalam kehidupan digital. Atau kalau kata Marcuse (seorang sosiolog teori kritis mazhab Frankfurt) bahwa kita adalah manusia satu dimensi, yang mana kesadaran kita dimanipulasi oleh teknologi, nalar-nalar teknologi kita menjadi kesadaran semu yang justru menjadi dehumanisasi bagi diri kita sendiri.