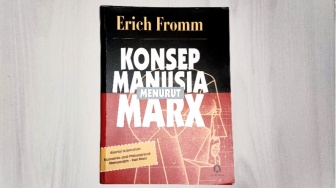Kita sering menyebut masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural, namun amat jarang kita memikirkan ulang pernyataan tersebut secara reflektif. Emang iya masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat multikultural? Atau mungkin hanya masyarakat pluralitas? Atau bahkan hanya masyarakat majemuk alias beragam saja?
Masyarakat Majemuk
Wasino (2013) dalam artikelnya Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism yang diterbitkan Paramita Historical Studies Journal, menerangkan bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat dengan sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Oleh karenanya, masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan, bahkan kurang memiliki kesadaran saling memahami di antara mereka.
Misalnya aja seperti masyarakat Nusantara di era pra-kolonialisme. Masyarakat Nusantara kala itu terdiri dari berbagai bangsa, berbagai kerajaan, berbagai kebudayaan, suku dan lain sebagainya yang tidak memiliki integritas sosial atau kesatuan sosial secara menyeluruh. Bahkan beberapa dari mereka, tidak dapat menghindari suatu konflik sosial.
Namun, itu semua merupakan masyarakat tempo lalu. Justru yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah apakah masyarakat Indonesia kontemporer merupakan masyarakat majemuk? Kalau menurut Wasino (2013), Indonesia kontemporer tidaklah cukup hanya disebut “majemuk”, pasalnya Indonesia hari ini memiliki integrasi, atau kesatuan sosial diantara keberagaman yang hari ini disebut sebagai “negara”. Oleh karenanya, perlu kita menaikkan levelnya dalam khasanah dari masyarakat majemuk menjadi masyarakat pluralitas.
Masyarakat Pluralitas
Nah, Budirahayu, Wijayanti, dan Baskoro (2018) dalam artikelnya Understanding the multiculturalism values through social media among Indonesian youths dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik menerangkan bahwa pluralisme sebagai suatu paham bahwa masyarakat dari berbagai ras, agama, budaya, bahasa atau ideologi politik dapat hidup damai dalam masyarakat yang sama. Maknanya konflik sosial di sini dalam masyarakat pluralitas sudah mulai disisihkan dalam rangka hidup di sebuah masyarakat yang damai.
Pertanyaannya kembali, bahwa apakah masyarakat Indonesia kontemporer merupakan masyarakat pluralistik? Saya sendiri tidak bisa mengeneralisir bahwa masyarakat Indonesia secara kesuluruhan merupakan masyarakat pluralistik. Pasalnya, itu merupakan sebuah pola pikir yang fallacy, yang secara sembarangan overgeneralization.
Beberapa masyarakat Indonesia bisa saja dapat dikatakan sebagai masyarakat pluralistik dalam artian dapat hidup damai di tengah keberagaman. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menutup mata dan telinga bahwa masih banyak juga konflik sosial terjadi dikarenakan keberagaman itu sendiri.
Misalnya, banyaknya pemberitaan mengenai penolakan pendirian rumah ibadah, adapula konflik etnisitas seperti sampit, dan banyak konfliknya yang masih menimbulkan pertanyaan dan diskusi panjang bahwa apakah benar masyarakat Indonesia itu pluralistik?
Di level yang tertinggi, Budirahayu, Wijayanti, and Baskoro (2018) menjelaskan bahwa di level ini masyarakat tidak hanya hidup damai dalam keberagaman, melainkan juga ada unsur yang juga disebut oleh Honneth (1995) dalam bukunya “The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict” sebagai “politik rekognisi” di tengah keberagaman. Maknanya masyarakat multikultural juga menghargai, mengakui, dan menerima perbedaan yang ada.
Dan, pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah Indonesia sudah mencapai pada titik ini? Apakah masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan masyarakat multikultural? Yang di sisi lain, sebagai masyarakat pluralistik saja masih menjadi tanda tanya yang besar.
Secara konstitusi, regulasi, maupun intitusi negara bisa dikatakan bahwa Indonesia, khususnya era reformasi, sudah mengakui, menerima, dan menghargai segala bentuk keberagaman di masyarakatnya, mulai dari etnis, agama, suku, kepercayaan, kelompok dan lain sebagainya.
Namun, itu semua hanyalah formalitas belaka, yang pada kenyataannya, kita masih banyak menemui penolakan di level masyarakat, bahkan tidak adanya kesadaran pengakuan pada kelompok yang “berbeda”, “asing” atau the stranger, out grup yang berarti sebuah kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka atau antipati.
Misalnya, di Surabaya sendiri, tepatnya di Lakarsantri, pada tahun 2021 yang lalu terjadi penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) oleh masyarakat setempat yang mayoritas Muslim dengan alasan bangunan tersebut dekat dengan pemukiman warga. Meskipun ketika di wawancarai oleh media bahwa masyarakat Lakarsantri mengaku toleran, namun dalam kenyataannya mereka tetap menolak pendirian Gereja semenjak 201.
Pertanyaan yang sangat mendasar bahwa mengapa penolakan pendirian rumah ibadah ini bisa terjadi? Jika perspektif warga, mereka akan menjawab karena berdekatan dengan pemukiman warga.
Namun, jika kita mau menelusuri, bahkan menggali makna-makna tersembunyi, bahwa terdapat “prasangka sosial” yakni pengambilan keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai sesuatu, atau bahkan dititik yang paling ekstrem terdapat apa yang disebut Goffman (1963) dalam bukunya “Stigma: Notes on The Management of Spoiled Identity” sebagai “stigma sosial”. Ini lebih pada persoalan teologis keimanan, bahwa masyarakat mengalami ketakutan ketika keimanan mereka dapat terganggu karena kehadiran rumah ibadah dari agama yang berbeda dengan yang mereka anut.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih tertatih-tatih menuju masyarakat multikultural. Bhinneka Tunggal Ika mungkin sering digaungkan, regulasi-regulasi mungkin sering diproduksi oleh para pemangku kekuasaan, namun dalam kenyataannya semua itu hanyalah formalitas, dan di lapangan “kesadaran kolektif” mengenai multikulturalisme masih penuh tantangan.
Kalau saya boleh menyebut kondisi masyarakat Indonesia hari adalah sebagai “Pseudo-Multiculturalism”, bahwa multikulturalismenya masih semu dalam angan-angan yang belum tercapai. Masyarakat Indonesia secara realitas empirik memanglah masyarakat yang majemuk, namun kesadaran kolektif tidak mengiringi kemajemukan tersebut, yang tidak mengantarkan mereka pada masyarakat yang multikultural, melainkan hanya sebatas kesemuan multikulturalistik.
Masyarakat yang terlalu lama homogen, maka produksi nilai dan norma juga terikat dengan homogenitas. Sehingga ketika terdapat eksistensi di luar identitas mereka maka akan menuai konflik sosial. Nilai dan norma tersebut beriringan dengan sikap, perilaku dan tindakan sosial seseorang dalam sebuah kemajemukan.
Jika secara makro di Indonesia, kita akan melihat masyarakat heterogen, namun dalam skala mikrospkopik, dalam sebuah lokalitas desa, kita masih menemui homogenitas masyarakat yang menghasilkan nilai dan norma yang kuat tentang identitas tunggal dan berdampak pada sikap, perilau dan tindakan sosial yang negatif pada identitas asing.
Oleh karenanya, agar masyarakat Indonesia benar-benar menjadi masyarakat yang multikultural, tidak hanya sebagai Pseudo-Multiculturalism, yang hanya berkutat pada regulasi dan wacana, maka sekurang-kurangnya masyarakat Indonesia dalam skala lokalitas mikro harus mengalami sebuah heterogenitas, memiliki kesadaran kolektif bahwa mereka beragam, yang kemudian akan menghasilkan sebuah nilai dan norma yang berdampak pada tindakan sosial. Sehingga pada akhirnya melahirkan sebuah masyarakat multikulturalisme yang sesungguhnya.