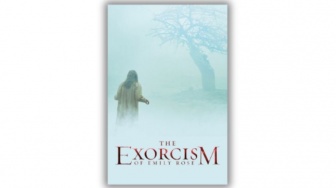Kolom
Seni dan Sastra sebagai Kebebasan Berekspresi serta Suara Demokrasi

Di tengah aksi Indonesia Gelap bergema, muncul sebuah band punk asal Purbalingga dengan video klarifikasi dan permintaan maaf mengenai lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Band ini sontak menjadi perhatian publik dan mendapat banyak dukungan dari berbagai lini masyarakat. Melalui tagar #KamiBersamaSukatani, publik memberi dukungan sekaligus menyuarakan keresahan mereka.
Klarifikasi tiba-tiba band Sukatani membuat publik akhirnya beranggapan bahwa telah terjadi pembungkaman seni. Anggapan ini bukan sekadar angin baru, sebab di akhir tahun 2024 kemarin publik lebih dulu dihebohkan dengan pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional.
Di waktu yang hampir bersamaan, gerakan literasi yang diprakarsai oleh Rumah Literasi pun mendapat kejadian tidak mengenakan. Sejumlah buku-buku koleksi mereka, yaitu tiga buku series tokoh Tempo, Soekarno, Tan Malaka, dan Sjahrir serta novel Animal Farm dan Gadis Kretek diduga dicuri.
Bergeser sedikit ke dunia film. Februari 2024 yang lalu, secara sepihak pihak bioskop kota Samarinda membatalkan pemutaran film dokumenter berjudul Eksil. Film yang bercerita tentang nasib WNI yang terbuang dan kehilangan status kewarganegaraan sejak peristiwa 30 September 1965 direncanakan akan tayang pada Kamis, 22 Februari 2024. Namun, sehari sebelumnya pihak bioskop membatalkan penayangan dan me-refund pembayaran tiket.
Kejadian ini memantik opini dan pertanyaan publik tentang kebebasan berekspresi. Di samping itu, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak kebebasan warga negara untuk berpendapat, yang mana di dalamnya merupakan hak untuk berekspresi.
Lalu bagaimana seni dan sastra bisa menjadi suara demokrasi?
Harmonisasi Seni dan Sastra
Seni dan sastra sama-sama kerap digunakan sebagai simbol berekspresi. Keduanya sangat dekat dengan kehidupan sosial-politik. Tak jarang karya yang lahir dari seni dan sastra merupakan representasi dari kejadian yang ada di dunia nyata. Maka tak heran kalau banyak seniman dan sastrawan yang menuangkan gagasan, ide, dan cerminan lingkungan sosial di karya mereka.
Seni dan sastra sebagai refleksi realitas sosial digunakan untuk menggambarkan persoalan yang dilalui masyarakat. Sejauh ini, telah banyak karya yang lahir dari representasi kondisi sosial-politik. Sebut saja puisi-puisi karya Wiji Thukul sebagai bentuk perlawanan yang tak lekang waktu.
Merekam Sejarah
Melalui seni dan sastra, refleksi keadaan sosial-politik dan persoalan lainnya akan tetap abadi. Keberadaannya tentu tak lekang waktu sebab karyanya merupakan bentuk rekaman sejarah. Tak jarang, seniman dan sastrawan modern akan mengingat kembali kejadian lampau dan kembali menghidupkannya dalam bentuk karya baru.
Jaminan Hak Asasi
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa seni dan sastra merupakan bentuk kebebasan berekspresi, maka keduanya dapat disebut sebagai alat untuk menjamin hak asasi. Sejalan dengan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia, pembatasan terhadap seni dan sastra merupakan langkah pelanggaran hak.
Seni dan sastra bukan sekadar karya yang lahir dari "kegilaan" pembuatnya. Karya-karya terbaik dan fenomenal lahir dari tangan dingin yang terus mengharapkan kebebasan berekspresi, kepedulian terhadap hak asasi, dan kecintaan antarsesama manusia. Keduanya dapat digunakan oleh seluruh kalangan warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya mereka.