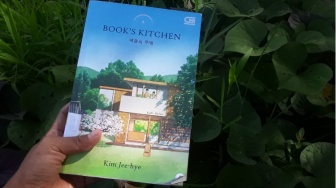Di banyak ruang kerja, ruang publik, bahkan ruang imajinasi masyarakat, kepemimpinan masih dibayangi oleh satu wajah, yaitu laki-laki. Meski dunia bergerak menuju kesetaraan, angka dan sikap tidak pernah berbohong, masih banyak orang, laki-laki maupun perempuan, yang merasa resah jika harus tunduk pada pemimpin perempuan.
Alasannya pun beragam, mulai dari dianggap terlalu emosional, tidak tegas, hingga klaim samar bahwa "mereka terlalu sering pamer tubuh di media sosial." Tapi mari kita bertanya lebih dalam bahwa ini tentang kompetensi, atau tentang ketakutan kolektif akan hilangnya dominasi lama?
Seksualitas perempuan sering dijadikan alasan diam-diam untuk mendiskreditkan kapabilitasnya. Perempuan yang tampil “terlihat menarik” dianggap tidak serius. Yang berpakaian seksi dianggap haus perhatian, dan karenanya tidak layak memimpin. Namun, siapa yang menciptakan standar ini? Siapa yang mengajarkan bahwa tubuh perempuan harus dijadikan komoditas visual, lalu menghukumnya ketika ia menggunakan tubuh itu untuk eksistensinya?
Dalam masyarakat tontonan seperti kata Jean Baudrillard, tubuh bukan lagi milik pribadi, tapi milik mata yang memandang. Ia menulis, "Di dunia yang dikuasai oleh penampilan, maka penampilan itu menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri."
Maka tak heran jika perempuan, yang sejak awal dikonstruksikan sebagai kesenangan mata bagi mata laki-laki, akhirnya dipandang hanya dari tubuhnya. Ketika ia berani bersuara, apalagi memimpin, resistensinya justru datang dari budaya yang membentuknya. Yaitu masyarakat patriarkal yang takut kehilangan kontrol atas objek yang selama ini ia miliki secara diam-diam.
Stereotip Perempuan dan Budaya Patriarki
Penelitian oleh Alice Eagly dan Blair T. Johnson (1990) dalam Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis menunjukkan bahwa meski perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif. Namun, gaya ini justru dianggap lemah dalam budaya organisasi yang maskulin. Ketika perempuan mencoba menjadi lebih otoriter untuk disetarakan, mereka malah dilabeli kasar, tidak feminin, bahkan “bos galak.”
Inilah jebakan epistemik yang menjebak perempuan, terlalu lembut dianggap tidak tegas, terlalu tegas dianggap tidak layak. Mereka dinilai bukan berdasarkan hasil, tapi berdasarkan ekspektasi yang absurd tentang bagaimana seorang perempuan baik-baik seharusnya bersikap.
Warisan patriarki telah mengakar selama ribuan tahun. Dalam buku The Creation of Patriarchy oleh Gerda Lerner (1986) menjelaskan bahwa patriarki bukan sesuatu yang muncul secara alami, tetapi merupakan konstruksi sosial yang diciptakan untuk mengontrol kapasitas reproduktif perempuan. Lerner menulis, "Patriarki adalah perwujudan dan pelembagaan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak dalam keluarga, serta perluasan dominasi laki-laki atas perempuan di masyarakat secara umum."
Generalisasi dan Bias Gender
Masyarakat masih nyaman dengan generalisasi. Karena generalisasi adalah bentuk malas berpikir. Lebih mudah menganggap semua perempuan tidak cocok memimpin daripada mengakui bahwa sistem sosial kita dibangun untuk menjatuhkan siapa pun yang tidak sesuai norma patriarkal. Dalam psikologi sosial, ini disebut dengan confirmation bias kecenderungan memilih data yang mendukung keyakinan awal dan mengabaikan yang lain.
Plato pernah memisahkan antara doxa (opini) dan episteme (pengetahuan sejati). Dalam kerangka itu, kita bisa melihat bahwa perempuan selama ini dinilai dengan doxa tubuh, emosi, pakaian. Bukan dengan episteme kualitas kepemimpinan, strategi berpikir, atau kebijaksanaan mengambil keputusan.
Kritik Terhadap Evolusi Sosial
Muncul klaim dari sebagian orang yang merujuk pada “naluri evolusi.” Perempuan dianggap saling sikut karena bersaing mendapatkan pejantan terbaik. Maka ketika jadi bos, katanya, perempuan akan menghalangi sesama perempuan.
Klaim ini populer di kalangan yang terobsesi pada psikologi evolusi, seperti ditulis oleh Buss (1995) dalam Evolutionary Psychology, tapi gagal memahami bahwa manusia bukan makhluk liar di padang sabana. Kita punya budaya, sistem hukum, pendidikan, dan akal budi. Jika segala relasi kekuasaan hanya dilihat dari kacamata primitif, maka kita sedang membenarkan bahwa manusia tak pernah benar-benar berevolusi secara sosial.
Dan mari kita akui satu hal penting yaitu laki-laki pun bisa tidak layak memimpin. Banyak dari mereka yang gagal mengatur emosi, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan mengobjektifikasi bawahannya. Namun kegagalan mereka tidak pernah ditarik menjadi stereotip kolektif. Mereka gagal sebagai individu, bukan sebagai laki-laki. Sementara ketika satu perempuan gagal memimpin, seluruh jenis kelaminnya dipertaruhkan.
Kepemimpinan Bukan Soal Gender
Jika ada laki-laki yang menolak dipimpin perempuan karena alasan terlalu pamer di medsos, maka sejatinya ia sedang menolak melihat bahwa tubuh yang ia tuding itu adalah tubuh yang selama ini ia konsumsi diam-diam. Dan jika ia tetap bersikeras memegang kendali, maka bisa jadi itu bukan karena perempuan tidak layak memimpin, tapi karena laki-laki takut kehilangan posisi dominan yang selama ini ia warisi tanpa ditantang.
Kepemimpinan, pada akhirnya bukan tentang jenis kelamin. Tapi tentang siapa yang berani mengambil tanggung jawab, berpikir jernih, dan bersikap adil. Jika kita masih takut pada pemimpin yang memiliki rahim, maka mungkin yang perlu kita koreksi bukan perempuan itu tapi keberanian kita untuk keluar dari bayang-bayang sejarah.