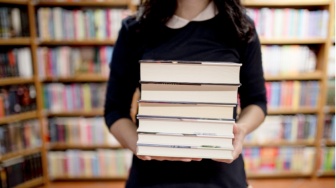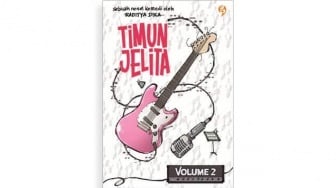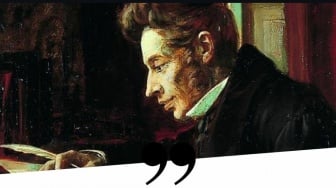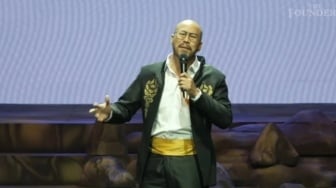Ki Hadjar Dewantara merupakan sosok sentral dalam sejarah pendidikan Indonesia yang terkenal tidak hanya karena mendirikan Taman Siswa, tetapi juga karena gagasan-gagasannya yang visioner tentang pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan bangsa. Ia memandang bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, melainkan untuk membentuk individu yang merdeka, memiliki kepribadian yang utuh, dan menjunjung tinggi nilai budaya.
Namun, delapan dekade setelah kemerdekaan, pertanyaan yang mengemuka adalah: Apakah cita-cita itu sudah terwujud? Apakah sistem pendidikan Indonesia hari ini benar-benar membebaskan?
Pendidikan Sebagai Alat Emansipasi
Ki Hadjar Dewantara menggarisbawahi bahwa "pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak," bukan sekadar proses mengisi kepala dengan pengetahuan (Dewantara, 2004). Ia menolak model pendidikan kolonial yang represif dan menjadikan murid sebagai objek. Dalam Taman Siswa, ia menciptakan lingkungan yang merdeka, humanis, dan sarat akan nilai-nilai kebudayaan nasional.
Gagasan "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" menjadi prinsip kepemimpinan pendidikan yang menempatkan guru sebagai fasilitator perkembangan karakter, bukan penguasa di ruang kelas. Gagasan ini sangat progresif dan sejalan dengan semangat pendidikan abad ke-21.
Merdeka Belajar dalam Bingkai Ketimpangan
Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek saat ini mengusung kebijakan Merdeka Belajar, yang secara retoris terdengar sangat selaras dengan semangat Ki Hadjar Dewantara. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: merdeka untuk siapa? Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa disparitas akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Siswa di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan menghadapi kekurangan guru, infrastruktur buruk, hingga minimnya akses internet.
Fenomena komersialisasi pendidikan juga menjadi tantangan serius. Pendidikan tinggi semakin menjadi komoditas, bukan hak. Bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi terbatas akan mendapati kesulitan dalam menempuh suatu pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat Taman Siswa yang membuka ruang belajar untuk anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.
Pendidikan dan Politik Kebangsaan yang Melemah
Ki Hadjar Dewantara juga memandang pendidikan sebagai sarana menanamkan kesadaran kebangsaan. Dalam tulisannya ia menyatakan, “Tujuan pendidikan adalah menjadikan anak-anak menjadi manusia yang merdeka, baik secara pikir, jiwa, dan raga” (Dewantara, 2004: 85). Pendidikan idealnya berperan dalam menanamkan rasa tanggung jawab dan keterikatan individu terhadap bangsa dan negaranya. Sayangnya, orientasi pendidikan hari ini lebih banyak terjebak pada capaian kognitif dan pencitraan angka statistik, seperti skor PISA yang tandus dari nilai-nilai kebangsaan dan sosial.
Kondisi ini menciptakan generasi yang cerdas secara teknis namun dangkal dalam pemahaman kebangsaan. Sementara itu, praktik politik identitas dan polarisasi sosial yang makin tajam di media sosial justru tidak banyak ditanggapi secara kritis dalam ruang pendidikan. Di sinilah urgensinya membumikan kembali pendidikan politik dan kebudayaan yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara.
Kembali pada Akar: Humanisasi Pendidikan
Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. S. Nasution dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia Modern (2005), pendidikan nasional haruslah bercorak nasional, berdasar pada kebudayaan sendiri, dan membangun karakter bangsa. Perlu ada upaya untuk menghidupkan kembali konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif yang diberi ruang untuk tumbuh secara bebas dalam lingkungan yang mendukung sikap kritis, etis, dan inovatif.
Perubahan fundamental dalam pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan struktural atau administratif saja. Sudah saatnya pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses penyampaian materi semata, melainkan sebagai usaha membentuk manusia yang utuh dan berintegritas dalam segala aspek kehidupannya. Kurikulum, guru, dan penilaian akademik harus difungsikan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar mengorientasikan peserta didik sebagai alat pemenuhan kebutuhan pasar kerja.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan masih sangat relevan. Sayangnya, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa belajar secara bebas dan setara belum menjadi kenyataan menyeluruh bagi semua kalangan. Pendidikan masih terasa berat sebelah, bahkan terasa jauh dari semangat pembebasan. Dengan demikian, yang dibutuhkan kini bukan hanya perayaan seremonial atas jasa Ki Hadjar Dewantara, melainkan penerapan konkret atas gagasan-gagasannya dalam kebijakan dan praktik pendidikan.
Daftar Referensi
- Dewantara, Ki Hajar. (2004). Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Nasution, S. (2005). Sejarah Pendidikan Indonesia Modern. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Kemendikbudristek. (2022). Kebijakan Merdeka Belajar: Transformasi Pendidikan Indonesia. Jakarta: Kemendikbud.