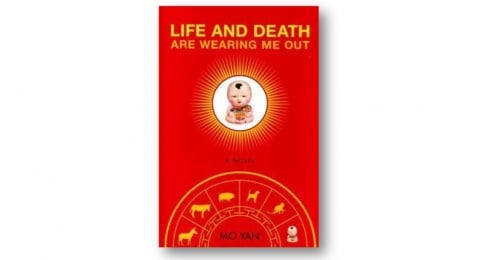Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapat kecaman publik akibat penyataannya yang cukup menyentil. Beliau mengakui bahwa penghargaan finansial terhadap guru dan dosen terbilang rendah.
Namun bukannya memberikan solusi, Sri Mulyani justru melontarkan pertanyaan, apakah semua pembiayaan profesi guru dan dosen harus ditanggung negara, atau bisa dibantu partisipasi masyarakat?
Di titik inilah, publik berhenti mendengarkan dan mulai mengepalkan tangan.
Sebab, pajak yang dibayar masyarakat tiap bulan—dari pekerja kantoran, buruh pabrik, hingga warteg kecil—itu apa bukan bentuk partisipasi juga? Bukankah pajak sudah menjadi “patungan” nasional yang dibungkus dengan kewajiban? Jadi ketika negara bilang butuh partisipasi masyarakat untuk menggaji guru, lalu selama ini duit pajak kita buat apa?
Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan memang terlihat besar—sekitar 20% dari total belanja negara. Tapi jangan dulu terkecoh oleh angka.
Karena faktanya, alokasi itu bukan semata-mata untuk guru. Ia terbagi untuk program BOS, infrastruktur sekolah, beasiswa, dan lainnya. Ketika sampai ke tangan guru, apalagi honorer, seringnya hanya berupa upah seadanya, bahkan tak layak jika disebut gaji.
Di banyak daerah apalagi, guru honorer masih menerima bayaran Rp300.000–Rp500.000 per bulan. Jumlah yang bahkan kalah dari uang jajan anak SMA di kota besar.
Dosen muda pun tak lebih baik. Sementara mereka dituntut punya S2, menulis jurnal internasional, mengajar pagi sampai malam, mereka masih harus menghadapi birokrasi ribet untuk sekadar mencairkan insentif tambahan. Kita jadi bertanya-tanya, mengapa profesi yang membentuk masa depan justru digaji semurah ini?
Hal yang membuat telinga semakin panas adalah ketika di waktu bersamaan, kita menyaksikan para pejabat dan anggota dewan menikmati tunjangan fantastis, mulai dari mobil dinas mewah, perjalanan dinas luar negeri, dana reses, bahkan uang pensiun seumur hidup.
Tahun 2024, misalnya, anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR RI mencapai lebih dari Rp500 miliar. Belum termasuk biaya operasional per orang yang bisa menyentuh Rp150 juta per bulan. Dan jangan lupakan proyek-proyek mercusuar negara yang menelan ratusan triliun tapi tak jelas hasilnya.
Jadi, ketika seorang guru honorer yang mengabdi 20 tahun masih harus menunggu kabar pengangkatan PNS, sementara anggota dewan baru dilantik langsung dapat semua fasilitas, siapa yang lebih pantas kita sebut sebagai beban negara?
Di negeri ini, mereka yang memanjakan diri dengan uang rakyat sering disebut wakil rakyat. Tapi yang benar-benar bekerja untuk mencerdaskan rakyat, yaitu para guru dan dosen, malah dianggap tanggungan berat.
Dan kita semua tahu, tidak semua pejabat bergaji tinggi hidup dari gaji saja. Banyak yang punya usaha, saham, tanah, dan jaringan bisnis. Bahkan laporan LHKPN menunjukkan, sejumlah pejabat punya kekayaan puluhan hingga ratusan miliar.
Maka ketika ada suara yang bertanya apakah negara harus terus membiayai profesi guru? Pantas rasanya kita balik bertanya, apakah pejabat-pejabat itu harus terus digaji negara, padahal mereka sudah kaya?
Kalau negara tak lagi sanggup menjamin kesejahteraan profesi pendidik, maka jelas ada yang salah dengan arah pembangunan kita. Kita terlalu sibuk membangun jalan tol, bandara, dan proyek prestisius, tapi lupa bahwa semua itu tak akan bertahan lama kalau manusianya bodoh, frustrasi, dan putus asa karena pendidik mereka tak dihargai.
Ironisnya, di setiap pidato kenegaraan, kita selalu dengar frasa “sumber daya manusia unggul.” Tapi siapa yang membentuk SDM unggul kalau bukan guru dan dosen? Apakah kita kira mesin AI bisa menggantikan mereka semua? Atau kita memang sudah siap menyerahkan pendidikan bangsa kepada YouTube dan TikTok?
Rasa-rasanya kita sudah muak melihat guru terus dipuja tapi tak pernah dimuliakan secara nyata. Kita pun muak karena pajak yang kita bayarkan malah lebih banyak menghidupi birokrasi, bukan memberi napas pada pendidikan.
Negara seharusnya hadir sebagai pihak pertama yang berdiri paling depan untuk melindungi profesi guru dan dosen. Kalau tidak, negeri ini tak perlu repot-repot merancang visi Indonesia Emas 2045. Karena tanpa pendidikan yang dihargai, tak ada masa depan yang bisa dibanggakan.