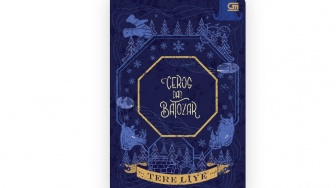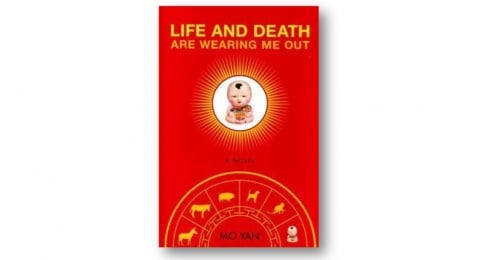Di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, terlihat tanah masih merah, hutan masih lebat, dan kadal raksasa terakhir di dunia masih berkeliaran bebas. Tapi sayangnya tak lama lagi, mungkin pemandangan itu hanya akan jadi wallpaper hotel.
Karena rencana pembangunan 448 vila wisata premium sudah di depan mata, lengkap dengan janji pengawasan ketat dari pemerintah dan setumpuk kecemasan dari warga lokal.
Salah satu hal yang menarik dari proyek ini yaitu istilah pengawasan ketat pemerintah. Kita sudah sering mendengarnya, setiap kali ada proyek besar yang menabrak nalar dan alam, pemerintah selalu datang membawa janji pengawasan, seolah itu cukup untuk menenangkan warga, komodo, dan ekosistem yang terancam. Padahal, di negeri ini, kata pengawasan kadang hanya sebatas formalitas di atas podium.
Proyek vila-vila ini akan dibangun di Pulau Padar, salah satu kawasan yang selama ini jadi ikon wisata alam di NTT. Letaknya di Taman Nasional Komodo, rumah bagi spesies langka yang tak ada duanya di planet ini. Iya, komodo yang jadi kebanggaan di brosur pariwisata, dan yang katanya dilindungi penuh oleh negara.
Tapi kenyataannya? Komodo-komodo itu kini terancam berbagi ruang hidup dengan tamu-tamu eksklusif yang datang untuk tidur di vila ber-AC dan menikmati matahari tenggelam dari infinity pool.
Lebih gawat lagi, proyek ini mengakibatkan sederet potensi kerusakan. Dari gangguan terhadap sarang komodo, pergeseran pola makan akibat limbah dapur vila, sampai perubahan perilaku karena aktivitas manusia yang padat.
Komodo yang biasanya berburu di alam bisa jadi malah menunggu sisa ayam panggang dari restoran hotel. Bukan cuma kehilangan habitat, mereka juga perlahan kehilangan naluri alaminya.
Bagi kita yang tinggal jauh dari NTT, ancaman terhadap komodo mungkin terasa seperti cerita fiksi yang bukan menjadi urusan sehari-hari. Tapi bagi warga lokal, ini sudah masalah hidup dan mati.
Banyak pelaku wisata di sekitar Pulau Komodo sudah lama menggantungkan hidup dari pariwisata berbasis alam. Mereka jadi pemandu, pengemudi kapal, penyewa alat snorkeling, dan pemilik homestay kecil-kecilan. Komodo adalah daya tarik mereka. Kalau habitat rusak, kalau hewan langka itu terusik dan menjauh, siapa yang masih mau datang?
Itulah kenapa mereka ramai-ramai menolak pembangunan ini. Bahkan saat konsultasi publik dibuka, warga memilih tidak hadir sebagai bentuk penolakan keras. Mereka tahu, menghadiri forum itu bisa disalahartikan sebagai legitimasi. Dan mereka sudah terlalu sering kecewa pada janji-janji pembangunan ramah lingkungan yang akhirnya cuma ramah pada pemodal.
Pemerintah berdalih proyek ini akan membawa devisa, lapangan kerja, dan kemajuan pariwisata. Tapi kita tahu, narasi semacam ini sudah jadi lagu lama.
Di balik semua ini, yang mengganggu adalah pola pikir bahwa segala sesuatu harus bisa dijual, bahkan warisan alam sekalipun. Bahwa wisata alam yang autentik dan lestari dianggap kurang menguntungkan dibanding vila mewah dan pengunjung berduit.
Dan yang paling menyedihkan adalah bagaimana suara warga lokal terus-menerus diabaikan. Mereka yang tinggal, bekerja, dan hidup dari tanah itu justru tidak dilibatkan secara adil. Padahal mereka lah yang selama ini paling memahami ritme alam, tahu di mana komodo biasa bersarang, dan tahu apa yang terjadi ketika musim kering datang terlalu cepat.
Pembangunan tak selamanya salah. Tapi pembangunan yang menginjak hak hidup orang kecil, yang mengusir satwa langka dari rumahnya, dan yang membungkus kepentingan ekonomi dalam nama wisata premium, itu serakah namanya.
Lalu, siapa yang benar-benar akan diuntungkan dari semua ini? Dan siapa yang akan membayar harganya, dalam bentuk habitat yang hilang, suara lokal yang dibungkam, dan warisan alam yang dikorbankan?
Kalau kita terus-menerus menukar alam dengan kenyamanan jangka pendek, suatu hari nanti kita mungkin masih bisa liburan, tapi tidak ada lagi yang benar-benar bisa kita lihat. Dan komodo, seperti banyak hal lain yang pernah kita abaikan, hanya tinggal kenangan.