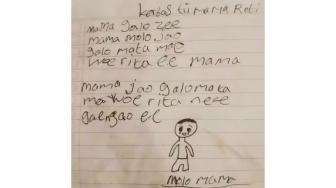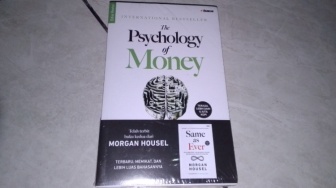Pada Sabtu, 26 April 2025, kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL menjadi panggung diskusi yang menggugah. Dedi Mulyadi, dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, merespons kritik seorang remaja tentang larangan perpisahan atau wisuda sekolah.
Remaja tersebut merasa larangan itu tidak adil, seolah merampas momen berharga dalam hidupnya. Namun, Dedi dengan tajam membalikkan pertanyaan: “Tidak adil buat siapa?” Jawabannya membuka tabir permasalahan yang lebih dalam—mentalitas jangka pendek yang terjebak pada gengsi sesaat, mengorbankan prioritas yang jauh lebih esensial.
Dedi tidak sekadar menjawab, ia menggali akar masalah dengan cerdas. Ia menyoroti bagaimana perpisahan sekolah, yang seharusnya menjadi momen sederhana, telah bermutasi menjadi ajang pungutan yang membebani. Biaya perpisahan yang mencapai sekitar 1,2 juta rupiah, seperti yang diungkap remaja tersebut, bukan angka kecil bagi keluarga dengan ayah pedagang botol kaca dan ibu rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai. Ironisnya, ibu remaja itu justru membela tradisi ini, menyebutnya penting untuk “mental anak”. Di sinilah letak paradoks: mengapa kita rela mengorbankan stabilitas ekonomi demi euforia sesaat?
Pemikiran jangka pendek ini, seperti yang Dedi sindir, mencerminkan kegagalan kita dalam memprioritaskan masa depan. Alih-alih menabung untuk biaya kuliah atau memperbaiki kondisi hidup, banyak keluarga terjebak dalam budaya gengsi. Perpisahan sekolah yang semestinya menjadi ajang silaturahmi malah menjadi panggung konsumsi berlebihan—dari sewa baju, dekorasi, hingga biaya venue.
Dedi dengan tepat menyinggung realitas pahit: “Ibu aja tinggal di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini?” Pertanyaan ini bukan sekadar sindiran, melainkan tamparan untuk kita semua yang sering kali terlena oleh ilusi status sosial.
Lebih jauh, Dedi mengarahkan kritiknya pada sistem yang membiarkan praktik pungutan ini merajalela. Ia menegaskan bahwa remaja seharusnya tidak hanya mengeluh tentang larangan perpisahan, tetapi mengkritik pemerintah yang gagal menjaga integritas pendidikan. Pungutan di sekolah, menurutnya, adalah buah dari kelemahan sistem yang tidak tegas melarang praktik ini. Kepala sekolah dan guru, yang sering menjadi kambing hitam, hanyalah korban dari tekanan budaya yang menormalisasi pungutan. Di sinilah Dedi menunjukkan visi yang lebih luas: kritik yang tajam harus diarahkan pada kebijakan, bukan hanya pada pelaksana di lapangan.
Namun, respons ibu remaja itu mengungkap realitas yang lebih pelik: budaya “demi anak” yang sering kali salah kaprah. Ia rela membayar mahal demi perpisahan, meski hidup dalam keterbatasan. Sikap ini, meski tulus, mencerminkan betapa kuatnya tekanan sosial dalam membentuk prioritas kita.
Dedi dengan cerdik mempertanyakan, “Pilih uang itu untuk kuliah atau untuk perpisahan?” Jawaban ibu yang ragu-ragu menunjukkan betapa sulitnya melepaskan diri dari jerat gaya hidup yang bertentangan dengan logika ekonomi. Ini bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan masyarakat yang terpaku pada kepuasan instan.
Polemik ini juga menggambarkan kesenjangan yang mencolok antara idealisme pendidikan dan realitas di lapangan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana pemberdayaan, bukan ajang memperdalam jurang ekonomi. Ketika perpisahan sekolah menjadi beban finansial, kita kehilangan esensi pendidikan itu sendiri. Dedi, dengan gayanya yang provokatif, mengajak kita untuk berpikir ulang: apakah momen perpisahan benar-benar sepadan dengan pengorbanan yang ditanggung? Ataukah kita hanya terjebak dalam lingkaran gengsi yang sia-sia?
Diskusi ini bukan hanya tentang perpisahan sekolah, tetapi tentang bagaimana kita mendefinisikan nilai dan prioritas. Dedi Mulyadi, lewat kritiknya, mengingatkan kita untuk keluar dari jebakan pemikiran jangka pendek. Kita perlu membangun budaya yang menghargai investasi jangka panjang—baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga. Sebab, seperti yang Dedi katakan dengan nada setengah bercanda namun penuh makna, “Kalau demi anak, jangan tinggal di bantaran sungai.” Pertanyaan yang tersisa adalah: maukah kita belajar dari sindiran ini, atau terus terlena dalam euforia sesaat?