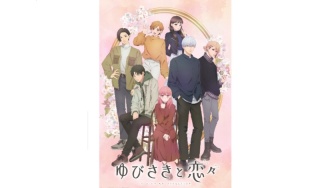Rapot merah bisa diperbaiki, tapi luka batin butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi saya dan banyak teman seangkatan dari generasi Z—kalimat ini menyimpan makna yang dalam.
Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa menjaga kesehatan mental bukanlah bentuk kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan pokok yang setara pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, bahkan lebih penting dari nilai akademik itu sendiri.
Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh di tengah keterbukaan informasi dan kesadaran sosial yang tinggi, saya merasa beruntung bisa lebih memahami konsep “self-awareness” dan “emotional resiliency” sejak dini.
Namun, saya juga menyadari bahwa sikap ini sering kali dianggap aneh oleh generasi sebelumnya yang menganggap nilai akademik sebagai tolok ukur kesuksesan utama.
Bagi mereka, menangis karena stres ujian dianggap cengeng, dan konsultasi ke psikolog dianggap berlebihan. Padahal menurut saya, mengutamakan kesehatan mental justru langkah-langkah yang sangat rasional.
Saya pernah mengalami masa-masa ketika tekanan akademik membuat saya kehilangan motivasi dan bahkan identitas diri. Tidur saya tidak teratur, kecemasan terus menghantui, dan saya tidak lagi merasakan kepuasan dari hasil belajar.
Di saat seperti itu, saya mulai menyimpulkan, untuk apa nilai A jika saya sendiri merasa hampa? Maka dari itu, saya mulai mencari bantuan profesional. Saat itulah saya menyadari bahwa perawatan kesehatan mental—termasuk sesi konseling, journaling, hingga mindfulness—harusnya bukan solusi terakhir, tetapi langkah preventif pertama.
Sebuah studi dalam Journal of Adolescent Health berjudul Academic Stress and Mental Well-being in College Students menguatkan pengalaman pribadi saya.
Penelitian ini menyebutkan bahwa stres akademik yang tidak tertangani emosional berkontribusi terhadap peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi pada mahasiswa. Studi ini juga menekankan pentingnya dukungan psikologis dalam sistem pendidikan agar siswa tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga sehat secara emosional.
Sayangnya, hingga kini, masih banyak institusi pendidikan yang menjadikan kesehatan mental sebagai program sampingan, bukan prioritas utama.
Padahal, kemampuan siswa dalam mengelola stres, mengenali emosi, dan menyadari batas diri sangat berkaitan dengan kinerja akademik jangka panjang.
Sudah saatnya sekolah dan universitas tidak hanya fokus pada kurikulum, tetapi juga menyediakan ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan dan memproses tekanan yang alami.
Sebagai individu dari Gen Z, saya tidak menolak pentingnya nilai akademik. Saya hanya menjadikannya satu-satunya tolok ukur hidup.
Kesehatan mental bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi fondasi agar kita bisa belajar, bekerja, dan berkarya dengan lebih optimal. Lagi pula, belajar bukan hanya soal angka di rapor, tapi juga tentang mengenal diri, bertumbuh, dan menyadari bahwa kita punya hak untuk merasa tenang.
Kini saya percaya bahwa prestasi terbaik bukanlah juara satu di kelas, tetapi ketika kita bisa membangun pagi dengan hati yang ringan, kepala yang jernih, dan semangat belajar yang tulus.
Saya tidak ingin mengorbankan kesehatan mental saya demi hanya mengejar angka sempurna yang tidak bisa menjamin ketenangan batin.
Dalam dunia yang semakin kompetitif, tekanan akan selalu ada. Namun, kita punya pilihan, apakah ingin terus memaksakan diri sampai runtuh, atau memberi jeda agar bisa kembali melangkah dengan sadar dan utuh?
Saya belajar bahwa memelihara kesehatan mental bukan berarti menjadi lemah. Justru, keberanian untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan, butuh istirahat, dan butuh ruang aman adalah bentuk kekuatan sejati.
Sebab, sehat mental bukan tentang selalu bahagia, namun tentang mampu menghadapi luka dan tekanan tanpa kehilangan jati diri. Dan jika suatu saat nilai akademik saya tidak sebaik yang diharapkan, saya akan tetap merasa cukup—karena saya tahu, saya menjaga diri saya dengan baik.