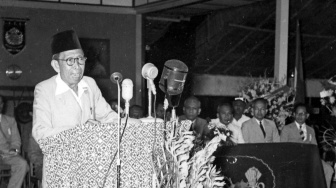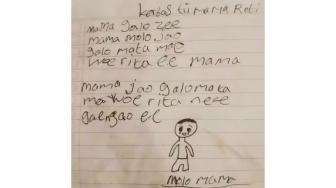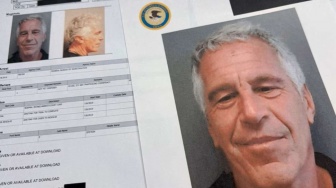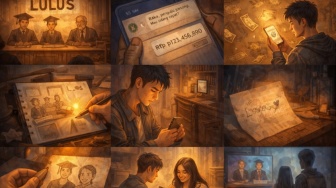Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan kecukupan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Badan Pusat Statistik, prevalensi gizi kurang telah menurun secara signifikan, dari 16,5 persen pada tahun 2011 menjadi 7,9 persen pada tahun 2018. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan dan pangan di tingkat nasional.
Akan tetapi, di tengah kemajuan tersebut, krisis stunting tetap menjadi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Dilansir dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting mencapai 27,7 persen pada tahun 2019, menjadikannya salah satu isu kesehatan masyarakat yang paling mendesak.
Krisis ini diperparah oleh pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, yang tidak hanya memicu kontraksi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kerawanan pangan dan kemiskinan.
Krisis Stunting: Dimensi Multidisiplin dari Malnutrisi
Stunting, yang didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis pada periode seribu hari pertama kehidupan, merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan sosial anak.
Mengutip Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Meskipun tren ini menggembirakan, angka tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menetapkan ambang batas 14 persen pada tahun 2024.
Menurut UNICEF Indonesia, lebih dari empat setengah juta balita di Indonesia mengalami stunting, menjadikannya bentuk malnutrisi yang paling umum di negara ini.
Dampak jangka panjang stunting meliputi penurunan kapasitas intelektual, peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa, dan perpetuasi siklus kemiskinan antargenerasi, yang menghambat pembangunan nasional.
Pandemi Covid-19 telah memperburuk krisis stunting dengan menciptakan guncangan ekonomi yang signifikan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan nasional meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, menambah sekitar dua juta orang ke dalam kelompok miskin.
Penurunan daya beli, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah, telah membatasi akses terhadap pangan bergizi, seperti protein hewani dan sayuran kaya mikronutrien.
Laporan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesejahteraan anak, mengungkapkan bahwa pandemi menyebabkan peningkatan kerawanan pangan di daerah pedesaan, dengan tiga puluh persen keluarga melaporkan kesulitan memperoleh sumber protein pada tahun 2021.
Situasi ini sangat kritis bagi anak usia enam sampai dua puluh tiga bulan, yang berada pada fase penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, telah mengalokasikan sekitar sepertiga dari anggaran penanganan pandemi sebesar 700 triliun rupiah untuk program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai, menurut Kementerian Sosial.
Program-program ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Akan tetapi, tantangan utama bukan hanya ketersediaan pangan, melainkan juga kualitas gizi.
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan seimbang, ditambah dengan kecenderungan mengonsumsi makanan olahan yang rendah gizi, menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan stunting.
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG): Antara Desain dan Implementasi
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, merupakan inisiatif lintas sektor yang bertujuan untuk memantau dan mengintervensi masalah gizi buruk serta kerawanan pangan.
SKPG melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, puskesmas, kader Posyandu, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan ketersediaan pangan, status gizi yang memadai, serta intervensi kesehatan yang tepat waktu.
Namun, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, efektivitas SKPG masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarsektor, minimnya sumber daya di tingkat lokal, dan rendahnya fokus pada perubahan perilaku masyarakat.
SKPG cenderung berorientasi pada pengumpulan data ketimbang implementasi program yang langsung menangani akar permasalahan, seperti pola konsumsi yang tidak seimbang.
Melansir Studi Diet Total oleh Kementerian Kesehatan, konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia mencapai 243 gram per orang per hari, sedangkan asupan protein hanya 52 gram. Ketimpangan ini diperparah oleh pergeseran pola konsumsi ke makanan olahan, seperti mi instan dan makanan ringan, yang kaya gula dan lemak, tetapi miskin mikronutrien.
Data dari Yayasan Dompet Dhuafa menunjukkan bahwa enam puluh persen keluarga di daerah miskin perkotaan mengandalkan makanan berbasis karbohidrat, dengan akses terbatas terhadap sumber protein hewani, seperti ikan, telur, atau daging.
Pola konsumsi ini tidak hanya meningkatkan risiko stunting, tetapi juga obesitas, yang kini menjadi ancaman ganda bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Kendala utama SKPG adalah lemahnya komponen edukasi gizi di tingkat komunitas. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berupaya mengatasi masalah ini melalui kampanye perubahan perilaku.
Namun, menurut Koalisi Organisasi Nirlaba untuk Gizi, kampanye ini sering kali gagal menjangkau komunitas terpencil, dengan hanya empat puluh persen desa di wilayah timur Indonesia yang terlibat dalam program edukasi gizi pada tahun 2022.
Selain itu, minimnya pelatihan bagi kader Posyandu dan kurangnya dukungan logistik di daerah terpencil menghambat kemampuan SKPG untuk memberikan dampak signifikan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi sistemik yang menempatkan edukasi dan intervensi berbasis komunitas sebagai prioritas utama.
Pergeseran Fokus Kebijakan: Dari Gizi Kurang ke Stunting
Fokus kebijakan gizi di Indonesia telah bergeser dari gizi kurang ke stunting, sejalan dengan pengakuan global akan dampak jangka panjang stunting terhadap pembangunan manusia.
Gizi kurang, yang mencakup status gizi sangat kurus (wasting) dan kurus (underweight), memiliki prevalensi yang relatif lebih rendah, yakni 17,1 persen untuk underweight dan 10,2 persen untuk wasting pada tahun 2022, melansir Kementerian Kesehatan.
Sebaliknya, stunting memengaruhi lebih dari satu dari lima balita Indonesia, menjadikannya prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, menurut Sekretariat Wakil Presiden.
Pergeseran ini didorong oleh fakta bahwa stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga mengurangi potensi ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, fokus yang berlebihan pada stunting berisiko mengabaikan aspek lain dari malnutrisi, seperti wasting dan obesitas. Menurut UNICEF Indonesia, sekitar empat setengah juta balita mengalami wasting, dengan 460.000 di antaranya dalam kondisi parah yang meningkatkan risiko kematian dan stunting.
Wasting, yang sering kali terjadi akibat kekurangan gizi akut, memerlukan intervensi cepat yang berbeda dari pendekatan jangka panjang untuk stunting.
Di sisi lain, obesitas pada anak dan remaja semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan. Melansir Kementerian Kesehatan, satu dari lima anak usia lima sampai dua belas tahun mengalami kelebihan berat badan, didorong oleh konsumsi makanan olahan dan gaya hidup sedentari.
Laporan dari Wahana Visi Indonesia mengungkapkan bahwa dua puluh lima persen anak di Jakarta mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari tiga kali seminggu pada tahun 2023, yang berkontribusi pada kenaikan prevalensi obesitas.
Pergeseran fokus ke stunting juga menyoroti tantangan dalam pengukuran dan pelaporan data gizi. Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS), yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Wakil Presiden, mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan dimensi kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Menurut Badan Pusat Statistik, cakupan imunisasi dan pemberian ASI eksklusif telah mencapai lebih dari delapan puluh persen, tetapi cakupan keluarga berencana modern hanya enam puluh tujuh persen, yang menghambat upaya pencegahan Stunting.
Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam satu aspek, seperti imunisasi, tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas stunting tanpa kemajuan seragam di semua dimensi.
Menuju Solusi Holistik: Strategi Komprehensif untuk Generasi Sehat
Untuk mengatasi krisis stunting dan gizi buruk secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan intervensi spesifik (seperti suplementasi gizi) dan sensitif (seperti peningkatan sanitasi dan pendidikan). Berikut adalah strategi yang direkomendasikan, yang didukung oleh data dari organisasi nirlaba dan badan pemerintah:
- Reformasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG): SKPG harus diarahkan untuk menjadi platform intervensi aktif, bukan hanya alat pemantauan. Menurut Kementerian Kesehatan, pelatihan kader Posyandu di 514 kabupaten/kota pada tahun 2022 meningkatkan deteksi dini stunting sebesar lima belas persen. Reformasi ini dapat diperluas melalui kolaborasi dengan organisasi seperti Yayasan Plan International Indonesia, yang telah melatih seribu lima ratus kader di Nusa Tenggara Timur untuk edukasi gizi, melansir Yayasan Plan International Indonesia. Peningkatan kapasitas kader dan penyediaan alat antropometri yang memadai di Posyandu akan memperkuat deteksi dan intervensi dini.
- Kampanye Edukasi Gizi Berbasis Komunitas: Stranas Stunting perlu memperluas jangkauan kampanye perubahan perilaku melalui saluran lokal, seperti kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penyuluhan agama, dan media sosial. Menurut Save the Children Indonesia, program edukasi gizi berbasis komunitas di Sulawesi Selatan meningkatkan konsumsi protein hewani sebesar dua puluh persen pada tahun 2022. Pendekatan ini dapat direplikasi di daerah lain dengan melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pesan gizi sampai ke tingkat rumah tangga.
- Peningkatan Akses terhadap Pangan Bergizi: Program perlindungan sosial, seperti BPNT dan PKH, harus dioptimalkan untuk menyediakan pangan bergizi, seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran lokal. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, distribusi pangan bergizi melalui pasar tradisional di seratus kabupaten pada tahun 2021 menurunkan kerawanan pangan sebesar sepuluh persen. Kolaborasi dengan organisasi seperti Foodbank Indonesia dapat memperluas jangkauan distribusi pangan ke daerah terpencil, sekaligus memanfaatkan potensi pangan lokal, seperti ubi, pisang, dan ikan air tawar.
- Penanganan Kelebihan Gizi dan Obesitas: Ancaman ganda malnutrisi, yang mencakup stunting dan obesitas, memerlukan perhatian seimbang. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program kantin sekolah sehat di lima puluh kota pada tahun 2023 mengurangi konsumsi makanan olahan sebesar lima belas persen di kalangan siswa. Program ini dapat diperluas dengan dukungan dari organisasi nirlaba, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang aktif mengampanyekan pola makan sehat. Selain itu, kampanye sekolah untuk mempromosikan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi prevalensi obesitas di kalangan anak-anak.
- Optimalisasi Dana Desa untuk Infrastruktur Gizi: Dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti Posyandu, fasilitas sanitasi, dan akses air bersih. Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dana desa telah membiayai pembangunan 82.356 sarana mandi, cuci, kakus (MCK) dan 32.711 unit air bersih pada periode 2015–2017, yang berkontribusi pada penurunan stunting di desa-desa tertinggal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi dana desa diarahkan untuk mendukung intervensi sensitif terhadap stunting, seperti peningkatan sanitasi dan penyediaan air bersih.
- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor: Keberhasilan pencegahan stunting bergantung pada sinergi antarlembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Pembentukan satuan tugas stunting di tingkat kabupaten/kota, yang melibatkan dinas kesehatan, dinas pertanian, dan organisasi masyarakat sipil, dapat memperkuat koordinasi. Contohnya, program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kalimantan Barat berhasil meningkatkan cakupan pemeriksaan gizi anak sebesar dua puluh lima persen pada tahun 2022.
Krisis stunting dan gizi buruk di Indonesia merupakan tantangan multidimensi yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara ketersediaan pangan, perilaku masyarakat, dan ketimpangan ekonomi.
Meskipun prevalensi gizi kurang telah menurun secara signifikan, angka stunting yang masih tinggi—21,6 persen pada tahun 2022—dan dampak pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum mencapai hasil optimal, melansir Kementerian Kesehatan.
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, meskipun dirancang sebagai platform lintas sektor yang ambisius, masih menghadapi kendala dalam koordinasi, implementasi, dan penjangkauan ke komunitas terpencil.
Pergeseran fokus kebijakan ke stunting, meskipun strategis untuk pembangunan jangka panjang, tidak boleh mengesampingkan masalah wasting dan obesitas, yang juga mengancam kesehatan generasi mendatang.
Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi mendatang, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu mengatasi tantangan pembangunan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta—akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS