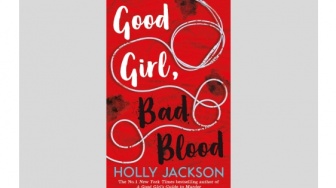Selama lebih dari tiga dekade, Indonesia hidup dalam bayang-bayang dwifungsi ABRI—sebuah rezim di mana militer tidak hanya mengemban tugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga ikut campur tangan dalam perumusan kebijakan politik, ekonomi, bahkan dalam aspek sosial dan budaya bangsa.
Reformasi 1998 muncul sebagai koreksi menyeluruh atas model kekuasaan yang koersif tersebut. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim dari Orde Baru ke era demokrasi, melainkan pergeseran paradigma: dari dominasi militer menuju supremasi sipil yang deliberatif dan partisipatif. Kala itu, semangat untuk mengembalikan militer ke baraknya dan meletakkan sipil sebagai pengendali kebijakan publik sempat menyala terang.
Namun, sejarah tidak selalu bergerak lurus. Dalam praktiknya, hasrat militeristik untuk kembali merambah ruang sipil tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya meredup, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dalam rupa baru. Kini, pengesahan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada akhir Maret lalu seolah menjadi pemantik bagi kekhawatiran lama yang kembali menemukan pijakannya.
Isyarat Menyusutnya Ruang Sipil
Revisi UU TNI membawa sejumlah perubahan signifikan: membuka peluang bagi prajurit aktif menempati jabatan sipil, memperpanjang batas usia pensiun, memperluas cakupan operasi militer non-perang, hingga memberikan kewenangan dalam urusan pendidikan anak-anak yang dikategorikan “nakal” di Jawa Barat.
Perubahan ini mengusik prinsip dasar dalam negara demokrasi: supremasi sipil atas militer. Ketika prajurit aktif diberi ruang untuk menduduki posisi sipil, maka meritokrasi birokrasi sipil terancam. Aparatur sipil yang membangun karier melalui prosedur ketat dan kualifikasi profesional kini harus bersaing dengan figur militer yang membawa kultur komando ke ruang yang semestinya dibangun atas asas deliberasi.
Lebih jauh, penempatan militer dalam jabatan sipil rawan menimbulkan loyalitas ganda—kepada negara melalui struktur birokrasi, sekaligus kepada institusi militer melalui rantai komando. Hal ini berisiko mengaburkan batas antara ruang sipil dan militer, menciptakan konflik kepentingan, dan pada akhirnya melemahkan otoritas pemerintahan sipil yang demokratis.
Perluasan kewenangan militer di luar konteks pertahanan negara juga menunjukkan kecenderungan kembalinya corak otoritarianisme yang pernah ditinggalkan pasca-Reformasi. Kini, militer bukan hanya diposisikan sebagai penjaga perbatasan dan kedaulatan negara, melainkan sebagai aktor yang turut campur dalam urusan domestik: mulai dari mengamankan kebijakan, mendidik anak-anak, hingga mengelola demonstrasi sipil.
Dengan rentang kewenangan seluas itu, tak dapat dihindari munculnya kesan bahwa negara tengah melangkah mundur—meromantisasi masa lalu yang kelam dan mengabaikan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
Meneguhkan Ruang Sipil, Menyalakan Kembali Api Reformasi
Adalah kekeliruan besar jika kita beranggapan bahwa demokrasi dapat tumbuh subur berdampingan dengan kekuasaan militeristik. Pengalaman sejarah, baik di Chile di bawah Pinochet maupun di Myanmar dengan junta militer, menunjukkan bahwa dominasi militer atas ruang sipil hampir selalu berujung pada represi dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara.
Indonesia telah membayar mahal untuk melepaskan diri dari jerat otoritarianisme Orde Baru. Reformasi 1998 adalah tonggak munculnya kesadaran bahwa militer profesional seharusnya berfokus pada pertahanan, sementara urusan sipil ditangani oleh aparatur yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada institusi bersenjata.
Pengesahan revisi UU TNI bukan hanya menjadi sinyal kemunduran, tetapi juga bentuk pembiaran atas semangat reformasi itu sendiri. Ruang sipil sejatinya bukan milik negara atau aparat, melainkan milik warga. Dalam sistem demokrasi yang sehat, ruang sipil menjadi syarat mutlak bagi hadirnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
Mengembalikan ruang sipil yang telah tergerus membutuhkan keberanian kolektif dari berbagai elemen: akademisi, mahasiswa, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga pengambil kebijakan yang berani mengambil sikap. Universitas harus berdiri sebagai garda terdepan dalam mempertahankan otonomi akademik, bukan sekadar dalam pernyataan simbolik, tetapi juga dalam tindakan nyata.
Pada akhirnya, kita harus kembali belajar dari pelajaran paling sederhana dalam sejarah: kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan akan bermuara pada penindasan. Jika ruang sipil terus dibiarkan menyempit, maka yang hilang bukan sekadar demokrasi, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih adil dan bermartabat.
BACA BERITA ATAU ARTIKEL LAINNYA DI SINI