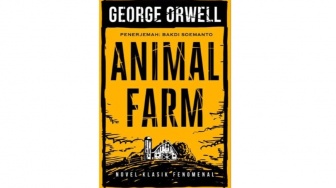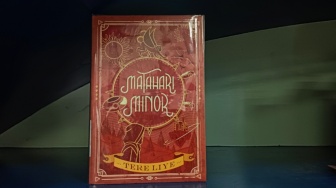Pernyataan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang menyebut bahwa sejarah Indonesia sebaiknya ditulis dengan tone positif demi menjaga persatuan bangsa, mengundang perdebatan luas.
Di satu sisi, keinginan untuk merawat kesatuan nasional memang mulia. Namun di sisi lain, menyederhanakan sejarah agar terdengar baik-baik saja justru berpotensi mengaburkan kebenaran masa lalu.
Sejarah adalah catatan faktual atas kejadian nyata. Sejarah bukan dongeng yang bisa dihias sesuai selera, atau cerita motivasi yang harus selalu membahagiakan.
Dalam sejarah terdapat luka, pengkhianatan, kekerasan, dan ketidakadilan. Meskipun pahit, semua itu adalah bagian dari perjalanan bangsa yang tak bisa dihapus atau disapu bersih demi kesan positif.
Generasi saat ini, terutama generasi muda berhak tahu sejarah apa adanya, bukan versi yang disterilkan dari konflik dan ketegangan.
Generasi sekarang justru semakin perlu memahami sejarah secara utuh. Bukan hanya dari buku pelajaran di sekolah yang sering kali terlalu singkat, terbatas, dan penuh penyederhanaan.
Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang tidak atau jarang disinggung dalam kurikulum formal, entah karena dianggap terlalu sensitif, terlalu rumit, atau terlalu gelap.
Padahal, sejarah yang kompleks justru menyimpan pelajaran paling berharga. Mengenal tragedi kemanusiaan, perjuangan kelompok marginal.
Selain itu, tentang suara-suara yang lama dibungkam bisa membentuk cara pandang yang lebih adil dan kritis terhadap masa kini. Literasi sejarah yang sehat tidak berhenti di ruang kelas, tapi justru bisa tumbuh dari rasa ingin tahu.
Karena itu, membatasi narasi sejarah hanya pada versi yang positif atau aman sama saja menutup kemungkinan generasi muda untuk memahami masa lalu bangsanya sendiri secara jujur.
Menutup-nutupi masa lalu demi persatuan adalah ilusi, karena tak akan ada rekonsiliasi tanpa pengakuan terhadap kenyataan. Justru dari pengakuan itulah, lahir kesadaran dan pembelajaran untuk tidak mengulang kesalahan di masa lalu.
Pertanyaannya, jika sejarah harus ditulis dengan tone positif, apa yang akan terjadi dengan buku-buku yang menyuarakan narasi kritis atau ideologi kiri?
Akankah buku-buku semacam itu dibatasi atau bahkan dilarang beredar? Ini bukan sekadar spekulasi. Di masa lalu, pelarangan buku-buku kiri atau yang dianggap subversif pernah terjadi dengan dalih menjaga stabilitas nasional.
Namun, konteks zaman kini sudah berubah. Teknologi informasi memberi ruang yang lebih luas dan demokratis terhadap pengetahuan.
Buku-buku yang dulunya dibungkam, kini bisa diakses secara digital, didiskusikan lewat forum daring, atau bahkan diulas secara terbuka di media sosial. Generasi pembaca saat ini pun lebih kritis dan tidak mudah dibatasi oleh narasi tunggal.
Bahkan, pelarangan atau sensor justru bisa menimbulkan efek sebaliknya, semakin dilarang, semakin dicari. Ini terbukti dari banyaknya generasi muda yang tertarik membaca buku-buku semacam itu.
Buku-buku yang dianggap terlarang seperti karya Pramoedya Ananta Toer atau Tan Malaka, bukan untuk memberontak, tapi untuk memahami sejarah bangsa dari sudut pandang lain.
Sejarah bukan untuk disucikan, melainkan untuk dipelajari. Dan belajar tidak selalu nyaman. Kadang harus melewati kenyataan pahit, pertanyaan sulit, bahkan kekecewaan terhadap tokoh atau sistem yang dulu diagungkan. Tapi dari situ, lahir pemahaman dan kedewasaan.
Menulis sejarah dengan tone positif mungkin harus dipertimbangkan ulang agar tidak salah perspektif. Justru, kejujuran sejarah adalah fondasi dari persatuan yang kuat.
Karena bangsa yang sehat adalah bukan bangsa yang melupakan masa lalunya begitu saja, tapi yang berani berdamai dengan masa lalunya sendiri.