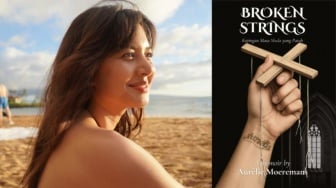Setelah makin lama mengarungi bahtera perkuliahan, tidak sedikit orang bilang organisasi itu tempatnya bertumbuh dan berkembang. Ya, saya rasa pun demikian. Namun, faktanya tidak sesederhana itu. Mahasiswa hari ini cenderung memilih sesuatu yang bisa mengasah keterampilan praktis dan menjaring relasi, ketimbang memperdalam pemahaman tentang suatu gerakan atau ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Makanya, tak heran kalau ruang diskusi tampak lebih sepi dan agaknya pun kurang diminati dibanding kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan tema profesi tertentu.
Wajar saja, setelah sekian lama berfokus pada organisasi yang basisnya olahraga sedari SD hingga SMA, saya tidak pernah benar-benar merasa sebagai “anak organisatoris”, dalam arti berkelindan dengan dinamika struktural maupun hal-hal terkait kepemimpinan dalam sebuah organisasi.
Maka dari itu, saat akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang basisnya pergerakan di kampus, tujuan saya sebetulnya nggak muluk-muluk—saya ingin punya ruang yang jujur, tempat belajar yang waras, dan teman diskusi yang nggak sibuk main politik receh demi jabatan apalagi soal kepentingan ego pimpinannya semata.
Digaet, Dijabatkan, Tapi Tak Pernah Benar-Benar Dikenalkan

Di awal-awal keterlibatan, saya mulai ngeh kalau organisasi yang saya ikuti itu “agaknya nggak begitu beres” sejak digaet lewat proses kaderisasi. Saat itu, sepertinya saya termasuk salah satu anak yang ditargetkan untuk diajak bergabung, namun tanpa pernah benar-benar diperkenalkan secara utuh tentang arah, tujuan, maupun nilai-nilai organisasi yang diusung organisasi tersebut.
Dapat dilihat bahwa ada semacam gap yang cukup kentara—baik dari segi komunikasi, arah gerak, perbedaan pandangan, maupun komitmen para anggotanya sendiri. Kaderisasi pun terasa kacau dan terburu-buru, padahal seharusnya ini jadi momen penting untuk mengenalkan identitas dan nilai-nilai dasar serta semangat organisasi. Sayangnya, yang tumbuh bukan komitmen kolektif, tapi justru ego dan tradisi lama yang lebih sibuk mengurusi seremonial dan politik internal ketimbang substansi.
Alih-alih jadi ruang yang membebaskan dan memberdayakan, organisasi malah terasa kaku, dipenuhi ego masing-masing karena beda prinsip dan pandangan. Pada akhirnya, ruang yang semestinya bisa jadi tempat belajar dan bertumbuh bareng justru terasa melelahkan.
Di tengah kondisi yang begitu, sebetulnya saya sempat berpikir untuk nggak terlalu larut. Saya hanya ingin cukup belajar seperlunya, ikut seperlunya. Tapi, namanya juga organisasi kampus, kadang suka ada momen di mana kamu ditunjuk jadi ini-itu tanpa benar-benar dikasih ruang buat nolak. Begitulah awalnya saya—mau nggak mau—ditunjuk jadi kepala bidang.
Bukan karena saya merasa paling mampu, apalagi paling layak. Tapi lebih karena ada semacam anggapan bahwa saya lebih dulu bergabung, maka otomatis dianggap paling siap, bukan juga karena benar-benar dipertimbangkan apakah saya paham arah geraknya atau siap dengan peran dan tanggung jawab yang akan dijalani ke depannya.
Ironisnya, sejak saat itu saya makin sadar bahwa banyak hal dalam organisasi ini berjalan bukan karena sistem yang terstruktur, tapi karena lebih banyak bergantung pada inisiatif orang-orang yang merasa perlu mengisi kekosongan yang sebetulnya tak pernah benar-benar dibenahi.
Gebrakan Inklusif: Merawat Kewarasan dalam Organisasi

Setelah mencoba menyesuaikan diri dengan hiruk pikuk organisasi yang seperti itu, saya mulai melihat sosok pemimpin dengan pendekatan yang berbeda, lebih terbuka, dan cukup berani menata ulang tradisi lama. Ia mencoba membuat gebrakan—sesuatu yang cukup berani dibanding gaya kepemimpinan sebelumnya.
Alih-alih meneruskan pola lama yang penuh drama internal dan seremonial tanpa makna, ia justru ingin merombak sistem yang selama ini terasa berantakan. Visi yang dia bawa jelas: memperbaiki struktur organisasi, membangun komunikasi yang sehat, salah satunya lewat upaya-upaya sederhana seperti bonding antaranggota.
Bukan bonding yang isinya sekadar kumpul dan foto-foto bareng, tapi benar-benar jadi ruang buat saling dengerin keluh kesah, berbagi keresahan, dan mengenal satu sama lain di luar urusan teknis, sekaligus mengembalikan semangat kolektif ke arah pergerakan yang lebih progresif dan inklusif.
Di fase itu, saya mulai merasa ada celah harapan bahwa organisasi ini mungkin masih bisa jadi tempat belajar yang waras, asalkan ada komitmen dan kemauan buat berubah dari pola yang lama dan bertumbuh bareng.
Ya, pada dasarnya, setiap orang punya potensi menjadi sosok pemimpin dalam sebuah organisasi. Namun, tidak semua orang mengetahui caranya. Karena memimpin adalah seni mengandalkan rasa bukan hanya titel jabatan semata.
Tentang Peran, Rasa, dan Kesadaran dalam Kepemimpinan Organisasi

Ketika saya diamanahi, ah tidak, atau lebih tepatnya ditunjuk tanpa banyak diskusi sebagai kepala bidang, saya sadar betul bahwa saya belum sepenuhnya siap. Pengalaman masih minim, belum sepenuhnya lepas dari sikap egois alias masih cenderung keukeuh pada prinsip dan cara pandang sendiri, bahkan agaknya pun belum tentu siap mengakomodir berbagai perspektif tiap anggota divisi. Proses adaptasi dengan dinamika organisasi pun masih jadi proses yang naik-turun. Belum lagi, tiap anggota datang dengan kepentingan, ekspektasi, kompetensi, dan karakter yang berbeda-beda.
Menjadi seorang pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling vokal atau paling sering ngasih perintah, apalagi sekadar ngatur-ngatur atau bagi-bagi tugas. Justru sebaliknya, harus mau mendengarkan dengan hati bukan hanya telinga, peka terhadap situasi, dan hadir sebagai penengah di tengah perbedaan pandangan.
Dari peran ini, saya mulai paham bahwa sebetulnya kepemimpinan itu bukan tentang kontrol, tapi tentang kontribusi. Tentang kehadiran yang bisa menghadirkan ruang yang aman dan nyaman, bukan rasa takut. Karena itu pula, saya belajar untuk tidak menjadikan konteks “kedewasaan” sebagai alasan untuk lepas dari tanggung jawab, apalagi dengan dalih, “toh udah sama-sama dewasa, ngapain harus selalu diingetin soal tanggung jawab.” Buat saya, cara berpikir seperti itu seharusnya nggak berlaku kalau kamu berada di posisi sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi.
Di situ saya juga belajar bahwa ketika ada anggota yang terkesan ‘ribet’ atau sulit diajak kerja sama, pemimpin nggak bisa langsung mengeluh, menyalahkan, apalagi memarahi. Bukan begitu caranya. Sebagai pemimpin, justru di situlah letak tanggung jawabnya: sabar, mengawal, dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tiap anggotanya.
Mengingat kapasitas setiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat nangkep, ada yang harus ditemenin dulu, diajak diskusi, dikasih arahan sampai benar-benar ngerti. Dan itu bukan sesuatu yang salah karena memang tugas sebagai pemimpin bukan hanya membagi tugas, tapi juga membentuk ruang belajar yang manusiawi.
Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka juga datang secara sukarela, jadi semestinya diperlakukan dengan kesadaran bahwa mereka datang untuk belajar, bukan untuk disuruh-suruh atau diberi perintah ini-itu, kecuali kalau memang dibayar.
Pemimpin yang Belajar Mengenali Kapasitas & Mengakomodasi Setiap Kontribusi

Pemimpin yang baik harus paham bahwa tiap anggotanya punya caranya masing-masing untuk dapat berkontribusi. Maka penting untuk bisa menyesuaikan cara pendekatan dan pendelegasian tugas sesuai dengan karakter dan potensi dari masing-masing anggota. Bahkan dalam hal paling teknis sekalipun, seperti manajemen tugas, seorang pemimpin dituntut untuk cermat dalam mempertimbangkan kesesuaian peran dan tugas dengan kapasitas dan kompetensi tiap anggotanya.
Di titik itu, saya sadar bahwa jadi pemimpin juga artinya harus rela mengosongkan gelas, membuka ruang belajar dari siapa pun, dan merefleksikan diri, bukan sekadar mengevaluasi anggotanya. Suatu anggota bisa hadir karena dua hal: kepentingan dan cinta. Maka tugas seorang pemimpin adalah mengakomodasi keduanya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap organisasi bisa dimulai dari tiga hal: menciptakan identitas yang bikin bangga, opportunity cost, dan memberi ruang untuk berkontribusi sekecil apa pun bentuknya.
Karena pada akhirnya, jadi pemimpin itu juga tentang belajar memanusiakan manusia. Kalau ada yang belum paham, ya dibimbing. Kalau ada yang belum bisa, ya didampingi. Dan kalau pemimpinnya sendiri yang salah, ya akui dan perbaiki. Turunkan ego, buka ruang, dan beri contoh karena pemimpin yang baik bukan yang paling tahu, tapi yang paling siap mengakomodasi semua kebutuhan tiap anggotanya untuk belajar dan berkembang bareng-bareng.
Terlepas dari itu semua, menjadi seorang pemimpin itu idealnya nggak cukup hanya bermodalkan niat. Harus dibarengi dengan strategi, taktik, dan kesadaran ideologis. Kalau kamu nggak punya strategi dan taktik atau nggak ngerti arah gerak dan belum paham medan, atau belum siap secara mental, mungkin memang belum waktunya memimpin.