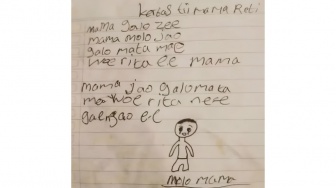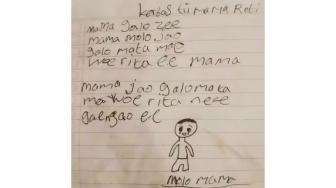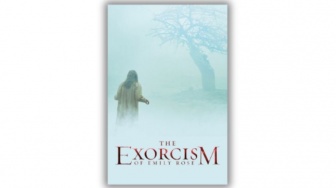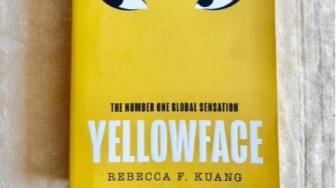Trailer film Merah Putih One For All baru saja rilis, dan netizen seperti biasa mulai membedah, membandingkan, lalu menghakimi.
Ada yang memuji ide ceritanya yang beragam budaya, dan tak sedikit pula yang langsung mengkritik kualitas visualnya, terutama jika disejajarkan dengan Jumbo, film animasi lokal yang dianggap telah mematok standar baru industri.
Hal yang paling memicu tanda tanya publik adalah klaim bahwa produksi film berdurasi 70 menit ini hanya memakan waktu sekitar satu bulan. Apalagi, anggarannya disebut mencapai Rp6,7 miliar.
Angka yang tidak kecil, namun publik punya ekspektasi besar bahwa dana sebesar itu akan menghasilkan visual setidaknya setara atau mendekati kualitas internasional.
Kisah film ini sebenarnya cukup menjanjikan, bercerita tentang delapan anak dari berbagai latar budaya Indonesia bersatu menyelamatkan bendera merah putih yang hilang tiga hari sebelum HUT RI.
Ada Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa, yang secara konsep, layak diangkat. Namun, seperti banyak proyek dengan semangat nasionalisme tinggi, masalahnya sering muncul di tahap eksekusi.
Ketika film Jumbo berhasil membuktikan bahwa animasi Indonesia bisa tampil layak di layar lebar dengan cerita dan visual yang memikat, publik otomatis menjadikan film itu sebagai patokan. Maka ketika trailer Merah Putih One For All hadir dengan kualitas yang menurut banyak orang “asal-asalan,” wajar jika kekecewaan muncul.
Apalagi, publik tahu bahwa Jumbo butuh waktu produksi bertahun-tahun, sementara Merah Putih One For All disebut hanya butuh sebulan.
Reaksi produser Toto Soegriwo pun menambah kontroversi. Alih-alih menanggapi kritik dengan penjelasan teknis atau permintaan maaf, Toto memilih santai dan berkata, “Senyumin aja. Komentator lebih pandai dari pemain.” Ini mungkin terdengar enteng, tapi publik kadang butuh lebih dari sekadar senyuman untuk memahami kenapa film yang mengusung semangat kemerdekaan justru terkesan asal-asalan.
Ketika proyek ini diumumkan akan tayang hanya dua bulan setelah mulai digarap, orang yang paham industri animasi otomatis mengernyit. Produksi animasi 3D biasanya memakan waktu 1–3 tahun untuk skala bioskop, bahkan untuk studio besar sekali pun.
Kritik terhadap Merah Putih One For All sebetulnya bukan semata ejekan atau perundungan visual. Ini adalah cermin ekspektasi masyarakat terhadap karya seni yang membawa nama besar Indonesia. Publik ingin merasa bangga saat menonton film ini di layar lebar, bukan sekadar tersentuh oleh ceritanya tapi terganggu oleh eksekusinya.
Kita juga tidak bisa mengabaikan dampak reputasi. Jika Merah Putih One For All gagal memikat, bukan hanya film ini yang kena, tapi juga industri animasi lokal yang sedang berusaha naik kelas. Jumbo telah berhasil membuktikan animasi Indonesia bisa bersaing, dan kegagalan proyek secepat Merah Putih One For All bisa membuat keberhasilan itu runtuh.
Mungkin Merah Putih One For All akan tetap menemukan penontonnya. Anak-anak yang belum terbiasa membandingkan kualitas visual internasional mungkin akan menikmati ceritanya. Tapi untuk mereka yang mengikuti perkembangan animasi, sulit mengabaikan bahwa ini terasa seperti kesempatan emas yang tergelincir karena kurangnya waktu dan perencanaan.
Di era media sosial, respons publik tidak bisa dibungkam dengan “senyumin aja.” Justru di situlah peluang untuk berdialog, menjelaskan, bahkan mengedukasi penonton tentang proses kreatif yang sesungguhnya. Publik mungkin lebih memaafkan keterbatasan yang diakui daripada kekurangan yang diabaikan.
Merah Putih One For All ini menjadi pengingat bahwa semangat nasionalisme tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan kualitas. Apalagi di dunia film, di mana karya akan berbicara lebih keras daripada niat.