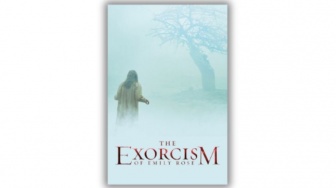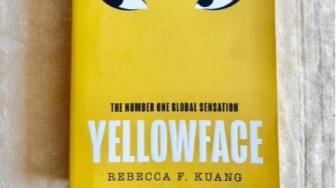Hari ini, langit seakan kehilangan warnanya. Awan hitam menggumpal rendah, menggantung berat di atas kepala, seperti menahan amarah yang siap ditumpahkan kapan saja. Udara terasa dingin dan lembap, menekan dada tanpa alasan yang jelas. Meski jarum jam baru menunjuk pukul satu siang, cahaya matahari lenyap sepenuhnya, memaksa lampu-lampu jalan menyala satu per satu, memancarkan cahaya pucat yang tak mampu mengusir muramnya hari.
Di rumah nenek, kegelapan terasa lebih cepat datang. Lampu-lampu dinyalakan di setiap ruangan, seolah rumah tua itu takut ditinggal sendirian dalam gelap. Bayangan-bayangan panjang merayap di dinding, bergerak perlahan mengikuti kelap-kelip cahaya, membuat suasana semakin sunyi dan tidak nyaman. Ada firasat ganjil yang tak bisa kujelaskan seakan hari ini bukan sekadar mendung biasa, melainkan awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku temui.
Namun, benar saja. Aku menemukan sebuah buku harian tua dan aneh bersampul kulit coklat. Sebelumnya aku tak pernah merasa was-was, tapi saat aku menemukan buku ini, jantungku berdegup cepat.
Aku menemukannya di balik dinding palsu kamar nenek bukan di loteng seperti dugaan awalku. Dinding itu rapuh, seolah sengaja dibuat untuk disembunyikan dan sekaligus ditemukan. Saat papan kayu itu roboh, bau busuk langsung menyergap hidungku.
Bukan bau debu. Bau itu seperti daging lama yang terkurung. Buku harian itu terikat kulit gelap yang sudah mengeras, bukan karena termakan usia melainkan karena sesuatu yang pernah basah dan kemudian mengering di atasnya. Saat kusentuh, kulitnya terasa hangat. Aku menarik tanganku refleks.
Aku seharusnya berhenti di situ. Halaman pertama terbuka sendiri.
Di sana tertulis kalimat yang nyaris membuat jantungku copot, “Aku menulis ini agar mereka tahu bahwa masa depan tidak menunggu. Ia datang untuk diambil”.
Tulisan itu ditulis pada hari Jumat, 16 Juni 1916. Bahkan tanggalnya lebih tua dari usia rumah dan nenekku.
Aku membaca sambil berdiri, karena entah kenapa aku takut duduk. Setiap halaman berisi satu kejadian kematian, mutilasi, orang-orang yang menghilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi yang tidak bisa dikenali sebagai manusia lagi.
Tulisan itu tidak deskriptif justru itulah yang membuatnya tampak sangat kejam. Seolah penulisnya sudah terlalu terbiasa dengan kematian untuk peduli pada detail. Lalu, aku sampai pada halaman yang punya tanggal yang sama seperti minggu hari lalu, yakni 16 Oktobe.
“Seorang ibu menusuk anaknya sendiri karena depresi mendengar suara dari dinding yang ternyata diganggu oleh sosok tak kasat mata.”
Tanganku bergetar. Itu terjadi minggu lalu. Aku sendiri membaca beritanya di media. Halaman berikutnya menuliskan kejadian besok.
Aku menutup buku itu dan muntah di lantai.
Malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat nenek duduk di ranjangnya, menulis di buku yang sama. Jarinya berdarah, kukunya terkelupas, tapi ia terus menulis sambil menangis pelan.
“Aku tidak ingin menulis lagi,” katanya dengan suara merintih memohon untuk menyerah tapi tak bisa.
“Tapi kalau berhenti, mereka akan datang.”
Aku terbangun dengan tenggorokan kering dan kuku-kukuku berlumuran darah seolah aku mencakar dinding saat tidur.
Dengan napas yang terengah-engah, aku memberanikan diri untuk membuka buku itu lagi. Halaman terakhir masih kosong, kecuali satu kalimat baru yang tidak kutulis.
“Ia sudah membaca sampai sini”.
Aku mencoba membuangnya. Membakarnya. Merendamnya. Menghancurkannya. Setiap kali aku gagal, satu baris baru muncul lebih personal, lebih sadis seakan buku itu mencoba berkomunikasi kepadaku. Ini tidak benar, buku ini buku kutukan.
“Ia memotong halaman ini, tapi lupa bahwa buku ini tidak terbuat dari kertas saja”.
Suatu pagi, aku bangun dengan luka panjang di lengan. Bukan goresan. Bekas tulisan. Huruf-huruf kecil terukir di kulitku, masih merah, perih dan basah. Tulisan itu sama dengan yang ada di buku.
Aku mulai mendengar suara aneh. Bukan bisikan lebih seperti seseorang membaca keras-keras di dalam kepalaku. Membacakan masa depanku dengan nada netral, tanpa belas kasihan.
Pada hari ketiga, akhirnya aku mengerti sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Buku itu tidak sekadar meramal masa depan. Ia membutuhkan saksi. Setiap nama yang tercatat di dalamnya bukan korban acak, melainkan orang-orang yang pernah membaca halaman-halamannya sampai akhir. Mereka tahu. Dan karena itu, mereka harus mati.
Aku membalik halaman-halaman lama dengan tangan gemetar. Semua korban sebelumnya tercatat rapi. Tak satu pun selamat. Semua berakhir setelah membaca halaman terakhir mereka sendiri.
Lalu aku melihat tanggal itu muncul. Itu terjadi besok dan di bawahnya, tertulis namaku.
Tintanya masih basah, seolah baru saja ditulis oleh sesuatu yang masih berdiri di dekatku.
“Ia akan mati dengan mata terbuka, karena ia menantang dan ingin melihat siapa yang datang.”
Kalimat itu membuat napasku terhenti. Aku tidak ingin melihat apa pun. Aku tidak ingin tahu siapa “yang datang”. Malam itu, aku memutuskan melarikan diri. Kupikir, jika aku pergi sejauh mungkin atau bahkan mati lebih dulu buku itu tidak akan menang.
Pisau sudah berada di tanganku. Ujungnya menekan leherku. Satu dorongan kecil saja, namun, tubuhku membeku.
Tanganku gemetar, lalu perlahan menurunkan pisau itu, bukan karena aku ragu, melainkan karena aku dipaksa. Aku berteriak, menangis, menggigit lidahku sendiri sampai darah memenuhi mulutku, berharap rasa sakit bisa mematahkan kendali itu. Tapi sia-sia.
Tubuhku bukan milikku lagi. Aku diseret ke kursi. Dipaksa duduk di depan meja. Buku itu terbuka sendiri di halaman terakhir. Pena bergerak di antara jari-jariku, meski aku tidak menggerakkannya. Tulisan tanganku muncul, huruf demi huruf, seperti luka yang ditorehkan perlahan.
“Aku mengerti sekarang. Buku ini tidak mencatat kematian tapi menciptakannya.”
Jam berdentang tepat tengah malam. Lampu-lampu padam serempak.
Dalam kegelapan, aku melihat pantulan di kaca jendela. Seseorang berdiri di belakangku. Wajahnya wajahku tetapi kosong, pucat, dengan senyum yang terlalu lebar. Darah mengalir di sekujur tubuhnya, menetes ke lantai tanpa suara.
Ia membungkuk ke telingaku dan berbisik, “Tenang saja. Setelah kamu mati, kamu tidak akan menulis selanjutnya.”
Namun saat itu juga, sesuatu menghantam kesadaranku. Ia berkata setelah aku mati. Artinya selama aku belum mati, aku masih di luar buku.
Aku menatap halaman terakhir sekali lagi. Di sana, di antara kalimat-kalimat kematianku, ada satu hal yang tidak berubah sejak awal buku itu tidak pernah bisa menulis tanpa saksi yang sadar. Ia hanya berkuasa selama aku membaca, selama aku mempercayainya.
Dengan sisa tenaga, aku menutup mataku. Untuk pertama kalinya sejak menemukan buku itu, aku berhenti membaca.
Aku merobek halaman terakhir, bukan dengan tangan melainkan dengan pikiran yang menolak mengakui kata-katanya. Dunia di sekitarku bergetar. Sosok di belakangku menjerit, suaranya pecah seperti kertas disobek paksa.
Aku terjatuh.
Aku tidak langsung pergi jauh setelah lolos dari malam itu. Ada sesuatu yang tertinggal bukan di rumah nenek, melainkan di dalam kepalaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku masih melihat halaman kosong terakhir, seolah menungguku kembali menulis.
Aku tahu satu hal, buku itu tidak bisa dibiarkan dan harus segera dimusnahkan agar tidaj menelan korban.
Tiga hari kemudian, aku menemui Pastor Adrian, seorang pastor tua yang dikenal alim dan ahli dalam dunia supernatural. Ketika aku meletakkan buku itu di atas mejanya, wajahnya langsung berubah. Ia tidak membukanya. Ia bahkan tidak ingin menyentuhnya.
“Ini bukan benda yang ingin dibaca,” katanya lirih. “Ini benda yang ingin dipercaya. Iblis melakukan semuanya dan memintamu patuh dengan semua yang dimintanya agar kau tidak mati.”
Pastor Adrian membawaku ke ruang bawah gereja malam itu. Tidak ada lilin hias. Tidak ada nyanyian. Hanya lingkaran kapur di lantai, kitab suci terbuka, dan sebuah tungku besi tua yang sudah lama tak dipakai.
“Ada buku yang tidak bisa dihancurkan dengan api biasa,” ujarnya. “Tapi kita tetap harus mencoba. Bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk memutus siklusnya.”
Saat api mulai menyala, buku itu bergetar. Sampulnya berdenyut seperti kulit hidup. Dari sela-sela halamannya terdengar suara berbisik puluhan suara, bertumpuk, saling menindih. Aku mengenali beberapa nama. Nama-nama korban.
Pastor Adrian mulai membaca doa, suaranya berat dan tegas bahkan ia juga menyiramkan air suci ke sekeliling buku terkutuk itu. Ketika buku itu dimasukkan ke dalam api, sesuatu yang tidak kuduga terjadi.
Halaman-halaman terbakar, namun tulisan di udara muncul. Kalimat-kalimat melayang seperti asap hitam yang penuh dendam amarah, “Jika buku ini musnah, saksi berikutnya akan lahir”.
Api tiba-tiba padam, ruangan menjadi dingin.
Pastor Adrian terhuyung, berlutut, napasnya terengah. Dengan suara hampir habis, ia berkata,
“Ini bukan kutukan yang ingin berakhir. Ini warisan turun temurun dari keluargamu.”
Aku sadar saat itu buku itu tidak pernah tinggal di satu bentuk. Ia hanya membutuhkan media. Jika kertasnya musnah, ia akan berpindah.
Dengan tangan gemetar, aku mengambil abu sisa pembakaran. Tidak ada lagi bentuk buku hanya serbuk hitam, hangat, dan berdenyut pelan.
“Apa yang harus kulakukan?” tanyaku.
Pastor Adrian menatapku lama, “Jangan biarkan siapa pun membacanya. Jangan biarkan siapa pun tahu kisah lengkapnya. Selama cerita ini tidak diceritakan utuh, siklusnya berhenti. Jika ingin menghentikannya, kubur buku ini di tempat yang tak seorang pun tahu, tapi jika itu tidak berhasil, kau harus mengakhirinya dengan menulis kalimat pemutus di halaman terakhir tapi ini akan mempertaruhkan nyawamu.”
Aku mengubur abu itu jauh dari siapa pun. Tidak ada penanda. Tidak ada doa. Tidak ada saksi.
Bertahun-tahun kemudian, aku hidup normal. Aku menikah. Aku bekerja. Aku hampir percaya semua itu sudah berakhir. Sampai suatu hari, aku menemukan sebuah buku catatan kosong di meja anakku.
Di halaman pertama, tertulis dengan tulisan yang belum pernah kutahui, itu bertuliskan “Hari ini, cuaca mendung sekali, perasaanku kacau….”
Dan di halaman terakhir yang masih kosong, aku tahu, suatu hari nanti, akan ada nama baru yang menunggu untuk ditulis. Jantungku seperti berhenti berdetak saat membaca kalimat itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut melainkan karena mengingat satu hal mengerikan saat itu.
Kalimat pembuka itu persis seperti yang pernah kutulis. Seperti yang selalu ditulis oleh setiap korban sebelum segalanya dimulai.
Aku menutup buku itu dengan kasar dan memanggil nama anakku. Ia menoleh polos, sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu sedang mencoba menjadikannya media berikutnya.
Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku kembali teringat kata-kata Pastor Adrian “Jika ingin menghentikannya, kubur buku ini di tempat yang tak seorang pun tahu, tapi jika itu tidak berhasil, kau harus mengakhirinya dengan menulis kalimat pemutus di halaman terakhir tapi ini akan mempertaruhkan nyawamu”.
Aku akhirnya mengerti kesalahan terbesarku, dulu aku mencoba menyembunyikan kutukan, bukan mengakhirinya.
Kutukan ini hidup dari kesinambungan. Dari pewarisan diam-diam. Dari ketakutan yang diwariskan tanpa pernah dihadapi.
Pagi buta, aku menggali kembali tempat abu itu dikubur. Serbuk hitam itu masih ada. Masih hangat. Masih berdenyut seperti jantung kecil yang menunggu tubuh baru. Aku mencampurnya dengan tinta hitam pekat dan untuk pertama kalinya, aku menulis dengan kesadaran penuh.
Aku tidak menulis ramalan.
Aku tidak menulis kematian.
Aku menulis akhirnya untuk memutus kutukan turun temurun ini.
Aku menulis seluruh kisah ini tanpa sensor, tanpa potongan, tanpa misteri yang dibiarkan menggantung. Aku menuliskan asal-usul kutukan keluargaku, pengorbanan para korban, tipu daya buku itu, hingga cara ia berpindah media. Aku menulis namaku sendiri, lalu menulis satu kalimat terakhir yang tidak pernah ada sebelumnya,
“Kutukan ini berakhir pada orang yang berani menceritakan segalanya. Dengan ini, kuputuskan segala kutukan. Apapun yang terjadi, aku siap menerimanya.”
Saat titik terakhir kutulis, tinta itu mengering menjadi abu. Buku catatan itu retak di tanganku, huruf-hurufnya runtuh seperti pasir, dan denyutan yang selama ini hidup, ini berhenti.
Aku jatuh pingsan.
Ketika terbangun, buku itu telah menjadi kertas kosong biasa. Tidak ada halaman yang menunggu. Tidak ada nama.
Anakku tumbuh tanpa pernah menulis kalimat aneh itu lagi.
Namun kadang, di malam-malam tertentu, ketika hujan turun deras dan lampu rumah meredup, aku merasakan dorongan kuat untuk kembali menceritakan kisah ini kepada orang lain, tapi kuhentikan karena jika ini kembali terucap, buku itu akan kembali lagi.
Karena aku tahu satu hal yang mengerikan, “Kutukan itu tidak mati.Ia hanya kehilangan tempat bersembunyi dan selama kisah ini tidak ditulis dan diceritakan, ia tidak akan pernah bisa kembali.”