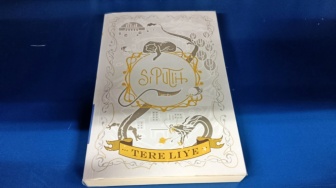Ada satu kenyataan pahit yang baru disadari setelah Film Weapons menebar teror di berbagai bioskop. Ternyata, tema horor ilmu hitam (santet dan sejenisnya) bisa dibikin keren, elegan, dan tetap bikin jantung berdebar tanpa harus muntah paku tiap lima menit.
‘Weapons’ merupakan film horor-thriller terbaru garapan Zach Cregger (Barbarian) yang bermain di wilayah misteri supranatural bercampur drama psikologis. Ceritanya dimulai saat satu kelas, 17 murid sekolah dasar tiba-tiba menghilang secara misterius di tengah malam di sebuah kota kecil Amerika, yang tersisa cuma satu murid.
Kejadian itu memicu rangkaian peristiwa ganjil yang dilihat dari beberapa sudut pandang karakter. Mulai dari guru, orang tua, hingga remaja setempat, yang perlahan mengungkap keberadaan sosok Aunt Gladys.
Gladys digambarkan sebagai wanita tua misterius yang menggunakan praktik ilmu hitam untuk mengendalikan pikiran dan tubuh anak-anak, memanfaatkan benda-benda pribadi mereka sebagai medium ritual. Sihir ini bekerja halus, mengikat korban tanpa mereka sadari, hingga semuanya bermuara pada satu titik pertemuan antar para tokoh dan sang dalang.
Alih-alih menampilkan teror secara gamblang, Cregger membangun ketegangan lewat potongan-potongan cerita yang saling mengisi, membuat misteri Gladys dan praktik ilmu hitam ini terasa semakin mencekam hingga akhir.
Rasanya kayak menemukan racikan jamu yang biasa kita minum, rupanya bisa diracik jadi mocktail mewah di bar hotel bintang lima. Dan ironisnya, di saat lagi kagum sama betapa kerennya gambaran serangan ilmu hitam versi Hollywood, eh, langsung ingat deh ada film horor lokal yang berkaitan dengan ilmu hitam yang … ya, gitu-gitu doang.
Padahal, kalau urusan mistis, Indonesia bisa dibilang surganya bahan baku. Nggak usah jauh-jauh riset ke luar negeri, tinggal keluar rumah, ngobrol sama tetangga, pasti dapat tiga cerita soal ilmu hitam, tempat gosip mistis, dan mungkin bonus cerita klenik soal serangan santet yang nggak akan pernah muncul di Google Search.
Namun, entah kenapa, begitu ada PH bikin film horor semacam itu dan sampai ke layar lebar, yang muncul malah horor dengan aroma basi yang sama dari tahun ke tahun, alias ceritanya tambal sulam doang.
Kita semua kayak sudah hafal alur dari film horor lokal deh. Tokoh utama biasanya perempuan cantik atau cowok ganteng, yang tersakiti, atau yang hidupnya adem ayem, lalu pelan-pelan diganggu orang sirik, mantan sakit hati, atau dukun profesional suruhan seseorang yang punya track record panjang.
Serangannya pun sudah bisa diprediksi. Mulai dari mimpi buruk, kulit melepuh, keluar ular dari perut atau mulut, sampai adegan muntah paku atau bahkan ulat, yang entah kenapa jadi semacam kewajiban. Setelah itu, selalu ada selingan komedi yang dipasang entah untuk apa. Mungkin biar filmnya terasa ringan cerita, tapi jadinya kayak makan rendang pedas lalu tiba-tiba disiram rendaman air asam. Nah, di ujung cerita, pelaku ketahuan atau mati konyol, lalu penonton pulang sambil bawa pesan moral yang dijejali begitu saja.
Sementara itu, perfilman Hollywood mainnya beda. Mereka nggak buru-buru membongkar siapa pelaku, kalaupun dibongkar sejak awal, ‘alasan kenapa semua itu terjadi’ nggak akan langsung dibongkar. Misterinya pun dibangun perlahan, bikin kita ikut merangkai potongan-potongan cerita. Karakternya nggak cuma hitam-putih; korban bisa punya rahasia kelam, pelaku bisa punya alasan yang bikin kita mau nggak mau mikir dua kali sebelum menghakiminya. Kebanyakan, kita bakal dibikin peduli dulu sama orang-orang di dalam cerita, bukan sekadar menunggu trik serangan apa yang bakal muncul selanjutnya.
Masalah terbesarnya ada di karakter. Korban dalam horor lokal sering cuma jadi objek penderita: nangis, teriak, pingsan, ulang dari awal. Pelaku? Mesin kejahatan tanpa satu pun dimensi manusia. Jarang sekali ada film (bukan berarti nggak ada ya) yang mau masuk ke lapisan psikologis mereka. Padahal, di situ letak horor paling ngeri—saat orang yang kita kenal, yang kelihatannya biasa saja, tiba-tiba berbuat sesuatu di luar nalar karena dendam, iri hati, atau trauma di masa lalu.
Yang bikin tambah gemas dari horor lokal tuh, ketegangan yang sudah susah payah dibangun sering hancur gara-gara komedi yang nyelip di waktu yang salah. Semua ini terjadi karena satu hal, yakni takut ambil risiko. Produser tahu pola lama masih laku, jadi jarang ada dorongan untuk bereksperimen. Misteri multi-lapis? Sudut pandang gonta-ganti? Karakter abu-abu yang bikin kita dilema? Ah, itu bikin pusing. Yang penting ada setan, ada korban, ada efek spesial. Selesai. Iya, kan?
Ironisnya, cerita ilmu hitam di dunia nyata justru jauh lebih mengerikan daripada yang kita lihat di film. Misalnya santet yang nggak cuma serangan fisik, tapi juga teror psikologis; rasa curiga yang memutus silaturahmi, gosip yang membunuh reputasi, paranoia yang membuat orang takut keluar rumah. Kalau semua itu diolah dengan serius, kita bisa bikin horor yang nancep di kepala penonton lama setelah mereka meninggalkan bioskop, tanpa satu pun adegan muntah paku atau CGI bentuk ular.
Masalahnya, industri kita sering melihat horor hanya sebagai mesin tiket cepat laku. Akibatnya, kita kehilangan peluang untuk memakai genre ini sebagai cerminan dari ketakutan untuk bicara soal iri hati, kesenjangan, atau keretakan sosial. Kita membiarkan horor di layar jadi karikatur. Dan ketika Film Weapons mengambil akar cerita seperti halnya ‘ilmj hitam’, dan membungkusnya dengan narasi yang matang, aku pun jadi bertanya-tanya, mau sampai kapan tema horor di perfilman lokal dibuat biasa-biasa saja?
Kendatipun begitu, aku percaya perfilman Indonesia akan terus berkembang. Dan semoga saja, ke depannya film horor buatan sineas Indonesia akan jauh lebih berkualitas.