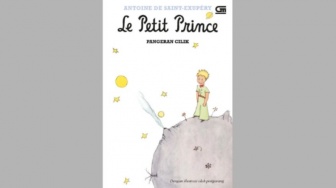“Bangga jadi #BoyMom!” Kalimat ini sering menghiasi media sosial, disertai foto ibu dan anak laki-laki yang tampak kompak dan menggemaskan. Tren ini terlihat manis dan penuh kasih sayang, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, hal ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa identitas sebagai ibu anak laki-laki begitu diagungkan? Mengapa jarang kita melihat euforia serupa untuk ibu anak perempuan? Fenomena ini memunculkan diskusi menarik tentang peran gender, media sosial, dan budaya yang kita hidupi.
Fenomena Boy Mom menarik karena bukan sekadar soal tren media sosial, tetapi menyentuh akar budaya patriarki yang masih berakar kuat. Banyak orang menganggap wajar jika seorang ibu merasa bangga memiliki anak laki-laki. Namun, di balik itu, ada pesan implisit yang mengisyaratkan bahwa anak laki-laki lebih istimewa dibanding anak perempuan. Apakah ini sekadar ekspresi cinta atau bentuk bias gender yang disamarkan dengan estetika media sosial?
Apa Itu Boy Mom Culture?
Boy Mom Culture merujuk pada kebiasaan para ibu yang mengidentifikasi dirinya sebagai “ibu anak laki-laki” dan merayakannya, terutama di media sosial. Tagar #BoyMom sering digunakan untuk menandai kebanggaan dan kebahagiaan karena memiliki anak laki-laki, biasanya disertai foto anak berpakaian rapi, bermain olahraga, atau aktivitas yang dianggap “maskulin”. Tren ini menjadi semacam identitas sosial baru di era digital.
Kepopuleran Boy Mom Culture tidak terjadi begitu saja. Media sosial menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman dan identitas, termasuk peran sebagai orang tua. Bagi sebagian ibu, menjadi “Boy Mom” terasa berbeda dan spesial karena anak laki-laki kerap diasosiasikan dengan sifat aktif, kuat, dan melindungi. Namun, apakah yang dirayakan benar-benar pengalaman membesarkan anak laki-laki, atau superioritas gender yang terus direproduksi?
Antara Kebanggaan dan Bias Gender
Dari satu sisi, wajar jika seorang ibu merasa bangga dengan anaknya, terlepas dari gender. Boy Mom bisa menjadi ekspresi cinta tulus seorang ibu. Banyak yang menganggap label ini hanya sebagai bentuk kebersamaan, bukan pernyataan diskriminatif. Bahkan, sebagian berargumen bahwa memiliki anak laki-laki memang membawa pengalaman berbeda dalam pola asuh.
Namun, di sisi lain, Boy Mom Culture menyimpan potensi bias gender yang tidak bisa diabaikan. Ketika menjadi “ibu anak laki-laki” dianggap prestise, secara tidak langsung anak perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang istimewa. Lebih jauh, ini mereproduksi nilai patriarki yang mengagungkan laki-laki sebagai simbol kekuatan, sementara perempuan tetap dipandang sebagai sosok sekunder. Jika tidak disadari, tren ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
Dampaknya pada Pola Asuh dan Persepsi Sosial
Boy Mom Culture tidak hanya hidup di ranah digital, tetapi juga berpengaruh pada pola asuh di dunia nyata. Ketika anak laki-laki dirayakan dengan cara yang berbeda, mereka bisa merasa lebih diistimewakan. Sebaliknya, anak perempuan berisiko merasa kurang dihargai. Pola ini, jika berlanjut, menanamkan keyakinan sejak dini bahwa gender menentukan nilai diri.
Selain itu, glorifikasi terhadap anak laki-laki juga dapat memicu stereotip berbahaya, seperti mengaitkan laki-laki dengan kekuatan, keberanian, dan dominasi, sedangkan perempuan dianggap lemah dan harus dilindungi. Dampak jangka panjangnya, konsep toxic masculinity dan ketimpangan gender akan terus lestari. Bukankah cinta orang tua seharusnya hadir tanpa harus mengukur nilai anak dari jenis kelaminnya?
Tagar #BoyMom mungkin terlihat sepele, tetapi di baliknya ada dinamika sosial yang menarik untuk ditelaah. Jika tidak disikapi dengan kritis, tren ini berpotensi memperkuat bias gender yang sudah lama mengakar. Menjadi orang tua adalah kebanggaan, entah itu ibu anak laki-laki atau perempuan. Kasih sayang seharusnya tidak memerlukan label yang menempatkan satu gender lebih istimewa dari yang lain. Pada akhirnya, cinta sejati orang tua tidak mengenal tagar, tidak mengenal perbedaan gender karena semua anak layak dirayakan tanpa bias.